Tuesday, July 31, 2007
Asthma cases on the rise among children
The Jakarta Post, Tuesday, July 31, 2007 Page A1
Worsening air pollution in Jakarta has made children more prone to suffering from asthma, a health expert has said.
Budi Haryanto of the University of Indonesia's Public Health School blamed Jakarta's traffic chaos for the continued pollution of the city's air.
Budi said a car moving slower than 30 kilometers per hour produced more carbon monoxide gas, which in turn triggered asthma, than a faster moving car.
"It's dangerous if people, especially children, breathe the gas because it can disturb blood circulation," Budi told The Jakarta Post last week.
"The higher the level of air pollution, the bigger the chance of children suffering from asthma attacks," he said.
Around 6.5 million vehicles drive through Jakarta streets each day. Besides carbon monoxide, vehicles also produce nitrogen oxide that can cause dizziness, headaches and loss of coordination.
Asthma is caused by a genetic predisposition combined with environmental factors or an unhealthy lifestyle.
According to data from the Ministry of Health, in 1995 as many as 2.1 percent of children in Indonesia suffered from asthma, the figure increasing to 5.2 percent in 2003.
The Jakarta Health Agency said there was no data on the prevalence of asthma in the city.
A pediatrician specializing in asthma, Noenoeng Rahajoe, said asthma could be controlled but could never be cured completely.
"(This is) because a genetic factor is playing a role here, which is then triggered by other factors," he said.
The other factors, he said, were not only vehicle pollution but also smoke from kerosene stoves and dust allergies.
Children with asthma often had trouble sleeping, meaning many could not study well at school, Noenoeng said.
The high prevalence of childhood asthma spurred Noenoeng and other physicians to form Pusat Asthma Anak Suddhaprana (The Suddhaprana Child Asthma Center) at Cipto Mangunkusumo General Hospital in Central Jakarta. Suddhaprana was a Sanskrit word that could be translated as "pure soul", "unpolluted environment" or "clean air", Noenoeng said.
Bambang Supriyanto from the hospital's Respiratory Division said 80 percent of children suffering from asthma were able to recover, although unhealthy surroundings or stress could cause them to relapse when they were older.
"The other 20 percent can live with the disease until they die," he added.
Budi and Noenoeng said more green areas could help prevent the spread of asthma by reducing pollution.
"The administration should provide more green areas (and) not only give permits for those wanting to build malls," Noenoeng said.
Minah, the mother of four-year-old Arya, brought her son to the hospital after he coughed continually for more than a week.
"At first I thought it was just a common cough, but after a few days without it stopping I brought him to a general practitioner near the house. But my son didn't get any better so I brought him to the hospital," she said.
"The doctors at the center found that my son was allergic to dust blown by a fan," Minah said, adding that she learned how to look after Arya if he relapsed.
The World Health Organization released an estimate this year that 100 to 150 million people around the world had asthma, a number predicted to increase by around 180,000 each year.
Sunday, July 29, 2007
✒
“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it"
--writer George Santayana (1863-1952)

Peserta dan instruktur kursus Jurnalisme Sastrawi XII di atap kantor Yayasan Pantau di bilangan Kebayoran Lama. Mayoritas bekerja di Jakarta namun ada juga yang datang dari luar Jakarta. Berdiri belakang (kiri ke kanan): Edy Purnomo, Yayan Ahdiat, Said Abdullah Dahlawi (Batam), Hillarius Gani, Janet Steele (Washington). Berdiri tengah: Sunaryo Adhiatmoko, Adriana Sri Adhiati (London), Yuyun Wahyuningrum (Bangkok), Endah Imawati (Surabaya), Lisa Suroso, Rozzana Ahmad Rony (Kuching), Stefanus Akim (Pontianak), Emmy Kuswandari, Dayu Pratiwi. Duduk: Aditya Heru Wardhana, Frans S. Imung, Andreas Harsono, Frans Obon (Ende)
Gordon Bishop Meninggal Dunia
Dia punya bisnis di Jogjakarta, menikahi penari cantik Jawa, kecelakaan di Banyumas dan mendirikan Joyo Indonesian News Service di Manhattan.
Mug Bill Kovach
Sandy Pauling dari rumah disain H2O merancang lima mug Pantau dengan quotation dari Bill Kovach. Anda suka yang mana?
Debat Sastra dan Pornografi
Pengarang Hudan Hidayat berdebat dengan penyair Taufiq Ismail soal maraknya pornografi serta kebebasan berekspresi dalam sastra.
Masalah dalam Proyek Seabad Pers Indonesia
Kapan sebenarnya "pers Indonesia" dimulai? Indexpress pimpinan Taufik Rahzen menetapkannya 1907 ketika Tirto Adhi Soerjo menerbitkan Medan Prijaji dengan alasan dia pribumi?
Indonesia: A Lobbying Bonanza
Taufik Kiemas, when his wife Megawati Sukarnoputri was still president, collected political money to hire a Washington firm to lobby for Indonesian weapons. This story is a part of a project called Collateral Damage: Human Rights and US Military Aid
 Dari Sabang Sampai Merauke
Dari Sabang Sampai MeraukeSejak Juli 2003, saya berkelana dari Sabang ke Merauke, guna wawancara dan riset buku. Intinya, saya pergi ke tujuh pulau besar, dari Sumatra hingga Papua, plus puluhan pulau kecil macam Miangas, Salibabu, Ternate dan Ndana. Inilah catatan kecil perjalanan tersebut.
Hoakiao dari Jember
Ong Tjie Liang, satu travel writer kelahiran Jember, malang melintang di Asia Tenggara. Dia ada di kamp gerilya Aceh namun juga muncul di Rangoon, bertemu Nobel laureate Aung San Suu Kyi maupun Jose Ramos-Horta.
State Intelligence Agency hired Washington firm
Indonesia's intelligence body used Abdurrahman Wahid’s charitable foundation to hire a Washington lobbying firm to press the U.S. Congress for a full resumption of military assistance to Indonesia. Press Release and Malay version
From the Thames to the Ciliwung
Giant water conglomerates, RWE Thames Water and Suez, took over Jakarta's water company in February 1998. It turns out to be the dirty business of selling clean water.
Media dan Jurnalisme
Saya suka menulis soal media dan jurnalisme. Pernah juga belajar dengan asuhan Bill Kovach dari Universitas Harvard. Ini makin sering sesudah diminta menyunting majalah Pantau.
Bagaimana Cara Belajar Menulis Bahasa Inggris
Bahasa punya punya empat komponen: kosakata, tata bahasa, bunyi dan makna. Belajar bahasa bukan sekedar teknik menterjemahkan kata dan makna. Ini juga terkait soal alih pikiran.
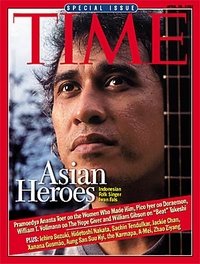 Dewa dari Leuwinanggung
Dewa dari LeuwinanggungSaya meliput Iwan Fals sejak 1990 ketika dia meluncurkan album Swami. Waktu itu Iwan gelisah dengan rezim Soeharto. Dia membaca selebaran gelap dan buku terlarang. Dia belajar dari W.S. Rendra dan Arief Budiman. Karir Iwan naik terus. Iwan Fals jadi salah satu penyanyi terbesar yang pernah lahir di Pulau Jawa. Lalu anak sulungnya meninggal dunia. Dia terpukul. Bagaimana Iwan Fals bangkit dari kerusuhan jiwa dan menjadi saksi?
Debat Sastra dan Pornografi
Selama beberapa bulan terakhir ini terjadi perdebatan antara orang yang protes soal maraknya pornografi di media kita versus orang yang membela kebebasan berekspresi. Salah satu debat menarik terjadi antara penyair Taufiq Ismail dan esais Hudan Hidayat.
Mulanya, Desember lalu, penyair Taufiq Ismail bikin pidato di Taman Ismal Marzuki, sekali lagi soal media, yang menurutnya membangkitkan syahwat. Taufiq, seorang yang pandai bikin retorika, memakai istilah FAK (fiksi alat kelamin) serta SMS (sastra mazhab selangkangan). Ini mengambil padanan suara dari kata bahasa Inggris "fuck," yang dibaca "fak" secara Melayu, artinya bersetubuh. Judulnya, Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka.
Hudan Hidayat menanggapi pidato ini dalam sebuah esai di harian Jawa Pos Minggu, 06 Mei 2007, Sastra yang Hendak Menjauh dari Tuhannya.
Taufiq Ismail menanggapinya lagi pada harian sama, Minggu, 17 Juni 2007 HH dan Gerakan Syahwat Merdeka. HH maksudnya Hudan Hidayat.
Hudan Hidayat menanggapinya lagi dalam Nabi tanpa Wahyu di harian Jawa Pos pada 1 Juli 2007. Saya kira ini perdebatan menarik. Linda Christanty, rekan saya dari Pantau, menganjurkan saya memuatnya dalam blog. Taufiq Ismail dan Hudan Hidayat memberikan izin saya menaruh perdebatan mereka disini.
Ternyata perdebatan ini tak berhenti disini. Hudan Hidayat dan tiga orang rekannya mengeluarkan Memo Indonesia di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Intinya, mereka menekankan tentang perlunya "toleransi atas keberagaman nilai" di mana warga bangsa-bangsa berbahagia atas keberbedaannya. "Setiap upaya atas dasar moral, nilai-nilai atau kekuasaan yang hendak membelenggunya adalah menghambat dan menjauhkan manusia dari kemajuan dan kebebasannya sendiri."
Pernyataan berbalas pernyataan. Di Serang, ketika berlangsung suatu pertemuan, Temu Komunitas Sastra se-Nusantara, 20-22 Juli 2007, dikeluarkan Pernyataan Sikap Sastrawan Ode Kampung. Pernyataan ini menyerang Komunitas Utan Kayu, yang salah satu anggotanya, novelis Ayu Utami, disebut oleh Taufiq Ismail. Uniknya, serangan ini dilakukan tanpa menyebut langsung nama Komunitas Utan Kayu. Ini memang bikin repot. Namun kalau baca-baca dari beberapa penerbitan yang jadi latar belakang pernyataan ini, tersurat bahwa sasaran serangan adalah Komunitas Utan Kayu.
Tanggapan Goenawan Mohamad, orang nomor satu Utan Kayu, muncul dalam suatu wawancara dengan Mediacare, sebuah mailing list. Goenawan tak menganggap Ode Kampung serius, "Saya kira kalau nanti mereka lebih dewasa, akan berubah cara menulisnya."
Selamat membaca!
Wawancara Goenawan Mohamad
Berikut ini hasil wawancara saya dengan Goenawan Mohamad, di Teater Utan Kayu, Kamis sore, 26 Juli 2007 lalu:
Oleh Rizka Maulana
RM: Tim Komunitas Utan Kayu diberitakan akan buka satu tempat kegiatan baru di Jalan Salihara, dekat Ragunan dan Universitas Nasional, Jakarta Selatan. Apakah alasannya? Untuk mengembangkan sayap?
GM: Itu sebagian kebetulan. Ada sepetak tanah yang cukup luas dan tidak mahal untuk ukuran Jakarta. Ada bantuan dana dari harian Jawa Pos, yang selama beberapa tahun terakhir ini membiayai program dan pengeluaran rutin Teater Utan Kayu. Kami putuskan untuk memanfaatkan semua itu buat membuat satu tempat kegiatan baru. Diketahui bahwa banyak penonton kegiatan kesenian di Gedung Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki datang dari Jakarta Selatan. Satu tempat altenatif yang memudahkan mereka, akan membantu banyak hal. Lagipula tempat kegiatan itu dekat sekali dengan Balai Rakyat. Kami berencana menjalin hubungan simbiotis dengan kegiatan anak-anak di sana.
Jadi Teater Utan Kayu (TUK) akan terus berjalan?
Ya. Kami sedang menyusun pembagian kerja antara kedua tempat itu. Belum selesai.
Ada pihak-pihak yang menuduh TUK sebagai “arogan” dan “eksklusif”. Bagaimana komentar Anda?
Apakah dalam tuduhan itu ada contoh yang menggambarkan “arogansi” dan sikap “eksklusif” TUK?
Kayaknya tidak.
Kalau ditunjukkan kasusnya dan terbukti, kami akan memperbaiki diri. Kalau tidak ada, bagaimana akan saya tanggapi?
Anda sudah baca “Pernyataan sikap Sastrawan Ode Kampung” baru-baru ini?
Belum.
Di dalamnya ada penolakan terhadap “arogansi dan dominasi sebuah komunitas atas komunitas lainnya”. Tampaknya ini serangan kepada TUK.
Apakah TUK disebut-sebut?
Tidak.
Kalau begitu sulit dikatakan itu serangan kepada TUK.
Anda sudah baca buletin yang disebut “Bumi Putra”?
Belum.
Kok nggak peduli?
Saya sedang tak punya banyak waktu. Di samping menulis Catatan Pinggir tiap minggu untuk majalah Tempo, saya sedang menuliskan kembali ceramah saya tentang "estetika jeda" dan satu telaah tentang Pramoedya. Saya juga sedang menyelesaikan serangkaian sajak dengan mengambil dasar novel Cervantes, Don Quixote. Sebentar lagi saya harus menuliskan satu libretto, Tan Malaka.
Kok sibuk sekali? Nggak ada waktu buat polemik?
Karena waktu saya terbatas, saya mendahulukan menulis dan menelaah. Lagipula, dalam pengalaman, di Indonesia ini sejak Polemik Kebudayaan sangat sedikit polemik yang bermutu.
Dalam buletin Bumi Putera ada kata-kata yang mengasosiasikan Anda dengan "gigolo" dan "pelacur budaya". Juga ada disebut nama "Ayu Tapi Mambu". Dengan kata lain, kata-kata yang umumnya akan dianggap kasar dan kotor.
Hmmm ....
Maksud Anda?
Mungkin penulisnya anak-anak remaja. Gejala itu seperti corat-coret di tembok kakus. Bagi saya, tak perlu dianggap serius. Saya kira kalau nanti mereka lebih dewasa, akan berubah cara menulisnya.
Taufiq Ismail menyebut adanya GSM, “Gerakan Syahwat Merdeka”. Ada yang mengatakan akronim itu mirip dengan akronim anda, “Goenawan Susatyo Mohamad”.
Ha,ha,ha.
Bagaimana tanggapan Anda tentang apa yang oleh Taufiq Ismail disebut "FAK", "Fiksi Alat Kelamin"?
Produksi akronim lagi naik, rupanya.
Menurut Taufiq Ismail, “Fiksi Alat Kelamin” itu dipelopori Ayu Utami dan Jenar Mahesa Ayu. Menurut Anda, apakah itu tepat?
Apakah Mas Taufiq menunjukkan secara persis karya mana dari kedua sastrawan itu yang menunjang statemennya?
Tidak.
Hmm. Aneh ....
Oleh Rizka Maulana
RM: Tim Komunitas Utan Kayu diberitakan akan buka satu tempat kegiatan baru di Jalan Salihara, dekat Ragunan dan Universitas Nasional, Jakarta Selatan. Apakah alasannya? Untuk mengembangkan sayap?
GM: Itu sebagian kebetulan. Ada sepetak tanah yang cukup luas dan tidak mahal untuk ukuran Jakarta. Ada bantuan dana dari harian Jawa Pos, yang selama beberapa tahun terakhir ini membiayai program dan pengeluaran rutin Teater Utan Kayu. Kami putuskan untuk memanfaatkan semua itu buat membuat satu tempat kegiatan baru. Diketahui bahwa banyak penonton kegiatan kesenian di Gedung Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki datang dari Jakarta Selatan. Satu tempat altenatif yang memudahkan mereka, akan membantu banyak hal. Lagipula tempat kegiatan itu dekat sekali dengan Balai Rakyat. Kami berencana menjalin hubungan simbiotis dengan kegiatan anak-anak di sana.
Jadi Teater Utan Kayu (TUK) akan terus berjalan?
Ya. Kami sedang menyusun pembagian kerja antara kedua tempat itu. Belum selesai.
Ada pihak-pihak yang menuduh TUK sebagai “arogan” dan “eksklusif”. Bagaimana komentar Anda?
Apakah dalam tuduhan itu ada contoh yang menggambarkan “arogansi” dan sikap “eksklusif” TUK?
Kayaknya tidak.
Kalau ditunjukkan kasusnya dan terbukti, kami akan memperbaiki diri. Kalau tidak ada, bagaimana akan saya tanggapi?
Anda sudah baca “Pernyataan sikap Sastrawan Ode Kampung” baru-baru ini?
Belum.
Di dalamnya ada penolakan terhadap “arogansi dan dominasi sebuah komunitas atas komunitas lainnya”. Tampaknya ini serangan kepada TUK.
Apakah TUK disebut-sebut?
Tidak.
Kalau begitu sulit dikatakan itu serangan kepada TUK.
Anda sudah baca buletin yang disebut “Bumi Putra”?
Belum.
Kok nggak peduli?
Saya sedang tak punya banyak waktu. Di samping menulis Catatan Pinggir tiap minggu untuk majalah Tempo, saya sedang menuliskan kembali ceramah saya tentang "estetika jeda" dan satu telaah tentang Pramoedya. Saya juga sedang menyelesaikan serangkaian sajak dengan mengambil dasar novel Cervantes, Don Quixote. Sebentar lagi saya harus menuliskan satu libretto, Tan Malaka.
Kok sibuk sekali? Nggak ada waktu buat polemik?
Karena waktu saya terbatas, saya mendahulukan menulis dan menelaah. Lagipula, dalam pengalaman, di Indonesia ini sejak Polemik Kebudayaan sangat sedikit polemik yang bermutu.
Dalam buletin Bumi Putera ada kata-kata yang mengasosiasikan Anda dengan "gigolo" dan "pelacur budaya". Juga ada disebut nama "Ayu Tapi Mambu". Dengan kata lain, kata-kata yang umumnya akan dianggap kasar dan kotor.
Hmmm ....
Maksud Anda?
Mungkin penulisnya anak-anak remaja. Gejala itu seperti corat-coret di tembok kakus. Bagi saya, tak perlu dianggap serius. Saya kira kalau nanti mereka lebih dewasa, akan berubah cara menulisnya.
Taufiq Ismail menyebut adanya GSM, “Gerakan Syahwat Merdeka”. Ada yang mengatakan akronim itu mirip dengan akronim anda, “Goenawan Susatyo Mohamad”.
Ha,ha,ha.
Bagaimana tanggapan Anda tentang apa yang oleh Taufiq Ismail disebut "FAK", "Fiksi Alat Kelamin"?
Produksi akronim lagi naik, rupanya.
Menurut Taufiq Ismail, “Fiksi Alat Kelamin” itu dipelopori Ayu Utami dan Jenar Mahesa Ayu. Menurut Anda, apakah itu tepat?
Apakah Mas Taufiq menunjukkan secara persis karya mana dari kedua sastrawan itu yang menunjang statemennya?
Tidak.
Hmm. Aneh ....
Pernyataan Sikap Satrawan Ode Kampung
Serang, Banten, 20 - 22 Juli 2007
Kondisi Sastra Indonesia saat ini memperlihatkan gejala berlangsungnya dominasi sebuah komunitas dan azas yang dianutnya terhadap komunitas-komunitas sastra lainnya. Dominasi itu bahkan tampil dalam bentuknya yang paling arogan, yaitu merasa berhak merumuskan dan memetakan perkembangan sastra menurut standar estetika dan ideologi yang dianutnya. Kondisi ini jelas meresahkan komunitas-komunitas sastra yang ada di Indonesia karena kontraproduktif dan destruktif bagi perkembangan sastra Indonesia yang sehat, setara, dan bermartabat.
Dalam menyikapi kondisi ini, kami sastrawan dan penggiat komunitas-komunitas sastra memaklumatkan Pernyataan Sikap sebagai berikut:
1. Menolak arogansi dan dominasi sebuah komunitas atas komunitas lainnya.
2. Menolak eksploitasi seksual sebagai standar estetika.
3. Menolak bantuan asing yang memperalat keindonesiaan kebudayaan kita.
Bagi kami sastra adalah ekspresi seni yang merefleksikan keindonesiaan kebudayaan kita di mana moralitas merupakan salah satu pilar utamanya. Terkait dengan itu sudah tentu sastrawan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat(pembaca). Oleh karena itu kami menentang sikap ketidakpedulian pemerintah terhadap musibah-musibah yang disebabkan baik oleh perusahaan, individu, maupun kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, misalnya tragedi lumpur gas Lapindo di Sidoarjo. Kami juga mengecam keras sastrawan yang nyata-nyata tidak mempedulikan musibah-musibah tersebut, bahkan berafiliasi dengan pengusaha yang mengakibatkan musibah tersebut.
Demikianlah Pernyataan Sikap ini kami buat sebagai pendirian kami terhadap kondisi sastra Indonesia saat ini, sekaligus solidaritas terhadap korban-korban musibah kejahatan kapitalisme di seluruh Indonesia.
Kami yang menyuarakan dan mendukung pernyataan ini:
01. Wowok Hesti Prabowo (Tangerang)
02. Saut Situmorang (Yogyakarta)
03. Kusprihyanto Namma (Ngawi)
04. Wan Anwar (Serang)
05. Hasan Bisri BFC (Bekasi)
06. Ahmadun Y. Herfanda (Jakarta)
07. Helvy Tiana Rosa (Jakarta)
08. Viddy AD Daeri (Lamongan)
09. Yanusa Nugroho (Ciputat)
10. Raudal Tanjung Banua (Yogya)
11. Gola Gong (Serang)
12. Maman S. Mahayana (Jakarta)
13. Diah Hadaning (Bogor)
14. Jumari Hs (Kudus)
15. Chavcay Saefullah (Lebak)
16. Toto St. Radik (Serang)
17. Ruby Ach. Baedhawy (Serang)
18. Firman Venayaksa (Serang)
19. Slamet Raharjo Rais (Jakarta)
20. Arie MP.Tamba (Jakarta)
21. Ahmad Nurullah (Jakarta)
22. Bonnie Triyana (Jakarta)
23. Dwi Fitria (Jakarta)
24. Doddi Ahmad Fauzi (Jakarta)
25. Mat Don (Bandung)
26. Ahmad Supena (Pandeglang)
27. Mahdi Duri (Tangerang)
28. Bonari Nabonenar (Malang)
29. Asma Nadia (Depok)
30. Nur Wahida Idris (Yogyakarta)
31. Y. Thendra BP (Yogyakarta)
32. Damhuri Muhammad (Depok) 33. Katrin Bandell (Yogya)
34. Din Sadja (Banda Aceh)
35. Fahmi Faqih (Surabaya)
36. Idris Pasaribu (Medan)
37. Indriyan Koto (Medan)
38. Muda Wijaya (Bali)
39. Pranita Dewi (Bali)
40. Sindu Putra (Lombok)
41. Suharyoto Sastrosuwignyo (Riau)
42. Asep Semboja (Depok)
43. M. Arman AZ (Lampung)
44. Bilven Ultimus (Bandung)
45. Pramita Gayatri (Serang)
46. Ayuni Hasna (Bandung)
47. Sri Alhidayati (Bandung)
48. Suci Zwastydikaningtyas (Bandung)
49. Riksariote M. Padl (bandung)
50. Solmah (Bekasi)
51. Herti (Bekasi)
52. Hayyu (Bekasi)
53. Endah Hamasah (Thullabi)
54. Nabila (DKI)
55. Manik Susanti
56. Nurfahmi Taufik el-Sha’b
57. Benny Rhamdani (Bandung)
58. Selvy (Bandung)
59. Azura Dayana (Palembang)
60. Dani Ardiansyah (Bogor)
61. Uryati zulkifli (DKI)
62. Ervan ( DKI)
63. Andi Tenri Dala (DKI)
64. Azimah Rahayu (DKI)
65. Habiburrahman el-Shirazy
66. Elili al-Maliky
67. Wahyu Heriyadi
68. Lusiana Monohevita
69. Asma Sembiring (Bogor)
70. Yeli Sarvina (Bogor)
71. Dwi Ferriyati (Bekasi)
72. Hayyu Alynda (Bekasi)
73. herti Windya (Bekasi)
74. Nadiah Abidin (Bekasi)
75. Ima Akip (Bekasi)
76. Lina M (Ciputat)
77. Murni (Ciputat)
78. Giyanto Subagio (Jakarta)
79. Santo (Cilegon)
80. Meiliana (DKI)
81. Ambhita Dhyaningrum (Solo)
82. Lia Oktavia (DKI)
83. Endah (Bandung)
84. Ahmad Lamuna (DKI)
85. Billy Antoro (DKI)
86. Wildan Nugraha (DKI)
87. M. Rhadyal Wilson (Bukitingi)
88. Asril Novian Alifi (Surabaya)
89. Jairi Irawan ( Surabaya)
90. Langlang Randhawa (Serang)
91. Muhzen Den (Serang)
92. Renhard Renn (Serang)
93. Fikar W. Eda (Aceh)
94. Acep Iwan Saidi (Bandung)
95. Usman Didi Hamdani (Brebes)
96. Diah S. (Tegal)
97. Cunong Suraja (Bogor)
98. Muhamad Husen (Jambi)
99. Leonowen (Jakarta)
100. Rahmat Ali (Jakarta)
101. Makanudin RS (Bekasi)
102. Ali Ibnu Anwar ( Jawa Timur)
103. Syarif Hidayatullah (Depok)
104. Moh Hamzah Arsa (Madura)
105. Mita Indrawati (Padang)
106. Suci Zwastydikaningtyas (Bandung)
107. Sri al-Hidayati (Bandung)
108. Nabilah (DKI)
109. Siti Sarah (DKI)
110. Rina Yulian (DKI)
111. Lilyani Taurisia WM (DKI)
112. Rina Prihatin (DKI)
113. Dwi Hariyanto (Serang)
114. Rachmat Nugraha (Jakarta)
115. Ressa Novita (Jakarta)
116. Sokat (DKI)
117. Koko Nata Kusuma (DKI)
118. Ali Muakhir (Bandung)
119. M. Ifan Hidayatullah (Bandung)
120. Denny Prabowo (Depok)
121. Ratono Fadillah (Depok)
122. Sulistami Prihandini (Depok)
123. Nurhadiansyah (Depok)
124. Trimanto (Depok)
125. Birulaut (Pusat)
126. Rahmadiyanti (Pusat)
127. Riki Cahya (Jabar)
128. Aswi (Bandung)
129. Lian Kagura (Bandung)
130. Duddy Fachruddin (Bandung)
131. Alang Nemo (Bandung)
132. Epri Tsaqib Adew Habtsa (Bandung)
133. Tena Avragnai (Bandung)
134. Gatot Aryo (Bogor)
135. Andika (Jambi)
136. Widzar al-Ghiffary (Bandung)
137. Azizi Irawan Dwi Poetra (Serang)
138. Gebar Sasmita (Pandeglang)
 Firman Venyaksa, Toto ST Radik, Ruby Bhaedowy, Gola Gong, Wowok Hesti Prabowo, Wan Anwar, dan Saut Situmorang membacakan pernyataan sikap.
Firman Venyaksa, Toto ST Radik, Ruby Bhaedowy, Gola Gong, Wowok Hesti Prabowo, Wan Anwar, dan Saut Situmorang membacakan pernyataan sikap.
Kondisi Sastra Indonesia saat ini memperlihatkan gejala berlangsungnya dominasi sebuah komunitas dan azas yang dianutnya terhadap komunitas-komunitas sastra lainnya. Dominasi itu bahkan tampil dalam bentuknya yang paling arogan, yaitu merasa berhak merumuskan dan memetakan perkembangan sastra menurut standar estetika dan ideologi yang dianutnya. Kondisi ini jelas meresahkan komunitas-komunitas sastra yang ada di Indonesia karena kontraproduktif dan destruktif bagi perkembangan sastra Indonesia yang sehat, setara, dan bermartabat.
Dalam menyikapi kondisi ini, kami sastrawan dan penggiat komunitas-komunitas sastra memaklumatkan Pernyataan Sikap sebagai berikut:
1. Menolak arogansi dan dominasi sebuah komunitas atas komunitas lainnya.
2. Menolak eksploitasi seksual sebagai standar estetika.
3. Menolak bantuan asing yang memperalat keindonesiaan kebudayaan kita.
Bagi kami sastra adalah ekspresi seni yang merefleksikan keindonesiaan kebudayaan kita di mana moralitas merupakan salah satu pilar utamanya. Terkait dengan itu sudah tentu sastrawan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat(pembaca). Oleh karena itu kami menentang sikap ketidakpedulian pemerintah terhadap musibah-musibah yang disebabkan baik oleh perusahaan, individu, maupun kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, misalnya tragedi lumpur gas Lapindo di Sidoarjo. Kami juga mengecam keras sastrawan yang nyata-nyata tidak mempedulikan musibah-musibah tersebut, bahkan berafiliasi dengan pengusaha yang mengakibatkan musibah tersebut.
Demikianlah Pernyataan Sikap ini kami buat sebagai pendirian kami terhadap kondisi sastra Indonesia saat ini, sekaligus solidaritas terhadap korban-korban musibah kejahatan kapitalisme di seluruh Indonesia.
Kami yang menyuarakan dan mendukung pernyataan ini:
01. Wowok Hesti Prabowo (Tangerang)
02. Saut Situmorang (Yogyakarta)
03. Kusprihyanto Namma (Ngawi)
04. Wan Anwar (Serang)
05. Hasan Bisri BFC (Bekasi)
06. Ahmadun Y. Herfanda (Jakarta)
07. Helvy Tiana Rosa (Jakarta)
08. Viddy AD Daeri (Lamongan)
09. Yanusa Nugroho (Ciputat)
10. Raudal Tanjung Banua (Yogya)
11. Gola Gong (Serang)
12. Maman S. Mahayana (Jakarta)
13. Diah Hadaning (Bogor)
14. Jumari Hs (Kudus)
15. Chavcay Saefullah (Lebak)
16. Toto St. Radik (Serang)
17. Ruby Ach. Baedhawy (Serang)
18. Firman Venayaksa (Serang)
19. Slamet Raharjo Rais (Jakarta)
20. Arie MP.Tamba (Jakarta)
21. Ahmad Nurullah (Jakarta)
22. Bonnie Triyana (Jakarta)
23. Dwi Fitria (Jakarta)
24. Doddi Ahmad Fauzi (Jakarta)
25. Mat Don (Bandung)
26. Ahmad Supena (Pandeglang)
27. Mahdi Duri (Tangerang)
28. Bonari Nabonenar (Malang)
29. Asma Nadia (Depok)
30. Nur Wahida Idris (Yogyakarta)
31. Y. Thendra BP (Yogyakarta)
32. Damhuri Muhammad (Depok) 33. Katrin Bandell (Yogya)
34. Din Sadja (Banda Aceh)
35. Fahmi Faqih (Surabaya)
36. Idris Pasaribu (Medan)
37. Indriyan Koto (Medan)
38. Muda Wijaya (Bali)
39. Pranita Dewi (Bali)
40. Sindu Putra (Lombok)
41. Suharyoto Sastrosuwignyo (Riau)
42. Asep Semboja (Depok)
43. M. Arman AZ (Lampung)
44. Bilven Ultimus (Bandung)
45. Pramita Gayatri (Serang)
46. Ayuni Hasna (Bandung)
47. Sri Alhidayati (Bandung)
48. Suci Zwastydikaningtyas (Bandung)
49. Riksariote M. Padl (bandung)
50. Solmah (Bekasi)
51. Herti (Bekasi)
52. Hayyu (Bekasi)
53. Endah Hamasah (Thullabi)
54. Nabila (DKI)
55. Manik Susanti
56. Nurfahmi Taufik el-Sha’b
57. Benny Rhamdani (Bandung)
58. Selvy (Bandung)
59. Azura Dayana (Palembang)
60. Dani Ardiansyah (Bogor)
61. Uryati zulkifli (DKI)
62. Ervan ( DKI)
63. Andi Tenri Dala (DKI)
64. Azimah Rahayu (DKI)
65. Habiburrahman el-Shirazy
66. Elili al-Maliky
67. Wahyu Heriyadi
68. Lusiana Monohevita
69. Asma Sembiring (Bogor)
70. Yeli Sarvina (Bogor)
71. Dwi Ferriyati (Bekasi)
72. Hayyu Alynda (Bekasi)
73. herti Windya (Bekasi)
74. Nadiah Abidin (Bekasi)
75. Ima Akip (Bekasi)
76. Lina M (Ciputat)
77. Murni (Ciputat)
78. Giyanto Subagio (Jakarta)
79. Santo (Cilegon)
80. Meiliana (DKI)
81. Ambhita Dhyaningrum (Solo)
82. Lia Oktavia (DKI)
83. Endah (Bandung)
84. Ahmad Lamuna (DKI)
85. Billy Antoro (DKI)
86. Wildan Nugraha (DKI)
87. M. Rhadyal Wilson (Bukitingi)
88. Asril Novian Alifi (Surabaya)
89. Jairi Irawan ( Surabaya)
90. Langlang Randhawa (Serang)
91. Muhzen Den (Serang)
92. Renhard Renn (Serang)
93. Fikar W. Eda (Aceh)
94. Acep Iwan Saidi (Bandung)
95. Usman Didi Hamdani (Brebes)
96. Diah S. (Tegal)
97. Cunong Suraja (Bogor)
98. Muhamad Husen (Jambi)
99. Leonowen (Jakarta)
100. Rahmat Ali (Jakarta)
101. Makanudin RS (Bekasi)
102. Ali Ibnu Anwar ( Jawa Timur)
103. Syarif Hidayatullah (Depok)
104. Moh Hamzah Arsa (Madura)
105. Mita Indrawati (Padang)
106. Suci Zwastydikaningtyas (Bandung)
107. Sri al-Hidayati (Bandung)
108. Nabilah (DKI)
109. Siti Sarah (DKI)
110. Rina Yulian (DKI)
111. Lilyani Taurisia WM (DKI)
112. Rina Prihatin (DKI)
113. Dwi Hariyanto (Serang)
114. Rachmat Nugraha (Jakarta)
115. Ressa Novita (Jakarta)
116. Sokat (DKI)
117. Koko Nata Kusuma (DKI)
118. Ali Muakhir (Bandung)
119. M. Ifan Hidayatullah (Bandung)
120. Denny Prabowo (Depok)
121. Ratono Fadillah (Depok)
122. Sulistami Prihandini (Depok)
123. Nurhadiansyah (Depok)
124. Trimanto (Depok)
125. Birulaut (Pusat)
126. Rahmadiyanti (Pusat)
127. Riki Cahya (Jabar)
128. Aswi (Bandung)
129. Lian Kagura (Bandung)
130. Duddy Fachruddin (Bandung)
131. Alang Nemo (Bandung)
132. Epri Tsaqib Adew Habtsa (Bandung)
133. Tena Avragnai (Bandung)
134. Gatot Aryo (Bogor)
135. Andika (Jambi)
136. Widzar al-Ghiffary (Bandung)
137. Azizi Irawan Dwi Poetra (Serang)
138. Gebar Sasmita (Pandeglang)
 Firman Venyaksa, Toto ST Radik, Ruby Bhaedowy, Gola Gong, Wowok Hesti Prabowo, Wan Anwar, dan Saut Situmorang membacakan pernyataan sikap.
Firman Venyaksa, Toto ST Radik, Ruby Bhaedowy, Gola Gong, Wowok Hesti Prabowo, Wan Anwar, dan Saut Situmorang membacakan pernyataan sikap.
Saturday, July 21, 2007
Gordon Bishop Loses Battle with Cancer
It is with deep sadness that we announce Gordon Bishop (Joyo) has lost his courageous battle with cancer. On Saturday, July 21, 2007, Joyo passed away at Mt. Sinai Hospital in New York.
On behalf of Joyo and the Joyo Indonesia News Service staff, we'd like to convey our heartfelt gratitude to all the subscribers who have expressed their support and love for Joyo over the course of his battle with cancer. Those many messages not only comforted him, but contributed to the fighting spirit that prolonged his life.
After the tragic loss of his beloved wife in a 1993 car accident, Joyo had to leave Indonesia for surgery in the United States. Beginning with emailing from his hospital bed, Joyo founded Indonesia's first online news service in 1996.
Today it is read by thousands, including journalists, academics, government officials, NGOs, human rights organizations, and embassy officials throughout the globe for the latest news and analysis about Indonesia.
In 2005, Joyo received the Indonesian Alliance of Independent Journalists' annual Suardi Tasrif Award, presented to individuals or institutions considered to have contributed to freedom of speech or access to information.
For Joyo, the news service was much more than a way of keeping subscribers around the world informed about Indonesia in all of its vast complexity: It was a way for him to stay connected to the people and country he loved...and missed...so much.
Finally, Joyo expressed his wish that the news service continue in the event of his death. The Joyo Indonesia News Staff will fulfill that wish, continuing the same high standards that he always demanded.
Sincerely,
JoyoNews, JoyoNews2, and the staff of Joyo Indonesia News Service
Funeral Information:
Tuesday, July 24, 2007 at 11:45am
Riverside Memorial Chapel
180 West 76th Street
New York, New York 10023
212-362-6600
Thursday, July 19, 2007
Mug Bill Kovach

Pantau lagi membuat sekitar 500 buah mug dengan pesan dari guru jurnalisme Bill Kovach. Pesannya tercetak pada mug bagian luar, "Journalism is the closest thing I have to a religion." Kalimat ini sering diucapkan Kovach bila memberi ceramah atau menerima wartawan di kantornya.
Kalimat ini juga sering dikutip oleh berbagai media. Ia dianggap quotation Bill Kovach. Saya selalu ingat cara dia mengucapkannya. Duduk santai di kursi khas Harvard. Kaki kursi dimiringkan. Lalu dengan suara berat dan parau, dia memberitahu kami bahwa ia percaya kegunaan jurnalisme buat perbaikan mutu masyarakat, “Journalism is the closest thing I have to a religion, because I believe deeply in the role and responsibility the journalists have to the people of a self-governing community.”
Pantau ingin membuat mug dengan kalimat ini sebagai kenang-kenangan bila sedang bikin kursus atau memberi hadiah. Pantau kebetulan cukup sering dikunjungi tamu, entah dari Kuala Lumpur, Kuching, Bangkok, Rangoon, Banda Aceh, Malang, Merauke, Pontianak, New York, Washington DC, Melbourne, Berlin dan sebagainya. Disain ini dibuat oleh Sandy Pauling, seorang mahasiswa Universitas Bina Nusantara di Jakarta.
Sandy Pauling lagi magang di rumah disain H2O di Jakarta. Vera Rosana, art director H2O, adalah orang yang sering menggarap disain Pantau. Kini H2O menggarap disain blocknot, kaos, sampul buku dan mug untuk Pantau. Ada beberapa pilihan disain mug. Kami belum memutuskan mana yang hendak kami pilih. Lucu-lucu sih. Warnanya beda-beda. Namun juga disainnya.
Kovach sendiri adalah mantan kurator Nieman Foundation on Journalism di Universitas Harvard. Dia juga menulis buku The Elements of Journalism bersama Tom Rosenstiel, yang sudah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa di dunia. Dia juga kerja lebih dari 20 tahun untuk The New York Times. Kini dia pensiun dan tinggal bersama isterinya di Washington DC. Dia juga masih duduk sebagai ketua kehormatan dari Committee of Concerned Journalists. Kovach beberapa kali disebut sebagai "hati nurani" jurnalisme Amerika. Pantau mengundangkan ke Medan, Jakarta, Jogjakarta, Bali dan Surabaya pada Desember 2003.
Anda suka yang mana?
Tuesday, July 17, 2007
Mbah Ndut
Semalam teman saya luluran. Mbah Ndut tukang lulurnya, dia juga berprofesi sebagai tukang pijet dan dukun bayi. Usianya 53 tahun. Meski wajahnya keriput, dia masih terlihat cantik dan bersemangat. “Dalam sehari saya masih bisa mijit paling banyak 5 orang mbak,” katanya. Kalo cuma pijat, ongkosnya Rp 35 ribu, kalo lulur Rp 75 ribu.
Saya duduk di sebelah Mbah Ndut, sambil membaca The Silent Season of a Hero-nya Gay Talese. Kami ngobrol sekali-kali. Obrolan yang membuat saya menghentikan membaca kalimat-kalimat anggun tentang Joe di Maggio, sang hero. Mbah Ndut bercerita tentang pasangannya.
Ini pernikahan kedua buat Mbah Ndut, perbedaan usia Mbah Ndut dengan pasangannya mencapai 20 tahun. Lebih dahsyat dari beda umur pasangan Joe di Maggio dan Maryln Monroe.
“Bukan saya yang jatuh cinta duluan mbak, tapi anak muda itu. Akhirnya saya tresno beneran dan kami menikah”, kata Mbah Ndut diselingi logat Jawa halusnya, dia lahir dan besar di Solo. Dalam bahasa Jawa, tresno berarti cinta.
“Tapi memang beda umur terlalu jauh, tidak baik. Saya baru tahu belakangan kalau suami saya menikah lagi dan punya anak. Dia dan istri barunya tinggal di Cawang. Sesekali dia masih pulang ke rumah Mampang. Biasanya dia tidak mau pulang jika tidak diberi sangu.“ Sang suami biasanya diberi sangu atau uang saku, besarnya Rp 200 ribu setiap datang.
“Sudah lebih sesasi (sebulan) dia tak datang. Saya pergi ke orang pinter, biar dipageri, biar dia tidak datang lagi,” ujarnya.
“Suami kedua saya tidak bekerja mbak, tapi sejak punya istri baru dia bekerja jadi cleaning service. Dulu saya sering dipukuli mbak. Kadang pake tangan, kadang kipas angin”.
Biasanya, habis dipukuli saya memilih minggat, cari kos-an baru. Tapi suami saya biasanya yang mencari, minta maaf dan ikut tinggal di tempat baru. Akhirnya saya memilih pulang,” cerita Mbah Ndut.
Saya takjub dengan perempuan ini, begitu nyantainya bercerita - tanpa rasa marah, nadanya datar saja. Begitu pula saat dia tambahkan cerita tentang suami pertamanya.
“Suami saya yang pertama tak beda jauh umurnya, hanya sekitar setahunan,” kata Mbah Ndut memulai kisah babak keduanya.
“Kakak perempuan saya jatuh cinta pada suami saya. Padahal dia sudah punya suami juga. Dulunya saya tidak tahu, setelah melahirkan anak pertama -saya sering sakit-sakitan. Sementara suami dan kakak perempuan saya, sering pergi bersama mencari pekerjaan. Kadang mereka merantau keluar kabupaten, kadang keluar pulau,” tambah Mbah Ndut.
“Akhirnya, sepulang dari merantau, suami saya mengaku akan menikah lagi…. kakak perempuan sayalah pengantinnya. Saya tak bisa menolak, saya dimadu -setelah mengajukan beberapa persyaratan. Saya hanya mau menyusui dan mengasuh anaknya, tak mau melayani kebutuhan suami lainnya,” tambah Mbah Ndut.
Tengah malam Mbah Ndut berhenti ceritanya, bersamaan dengan selesainya melulur badan teman saya dengan pasta berwarna kuning, buatan sendiri.
Hmmm … terlalu banyak potret-potret seperti Mbah Ndut di sekeliling saya, dari kampung di ujung timur pulau Jawa, ujung timur Flores hingga ibu kota negara ini.
Tidak tahu kenapa Tuhan membagi cerita yang sama kepada saya, di banyak tempat - terlalu sering.
Karya ini ditulis oleh Siti Maemunah, seorang peserta kursus Narasi di Yayasan Pantau. Karya pendek ini salah satu hasil latihannya menulis. Maemunah adalah koordinator nasional Jaringan Advokasi Pertambangan di Jakarta.
Thursday, July 12, 2007
Memo Indonesia
Kemajuan suatu bangsa adalah buah dari kebebasan itu sendiri, kebebasan untuk menjelmakan cabang-cabang kehidupannya. Kemajuan dan kebebasan demi merengkuh dan mewujudkan kesempurnaan kemanusiaannya.
Kesempurnaan kemanusiaan bagi kami adalah toleransi atas keberagaman nilai, tempat di mana warga bangsa-bangsa berbahagia atas keberbedaannya. Setiap upaya atas dasar moral, nilai-nilai atau kekuasaan yang hendak membelenggunya adalah menghambat dan menjauhkan manusia dari kemajuan dan kebebasannya sendiri.
Kami adalah manusia bebas. Berdaulat atas jiwa dan raga kami untuk mencipta kemanusiaan kami sendiri, dalam kebebasan penciptaan tanpa penjajahan. Sumber penciptaan untuk meraih kemajuan, akan kami gali dari bumi mana pun yang kami olah dan kami persembahkan bagi kemajuan dan kemuliaan kemanusiaan.
Kemajuan dan kebebasan kemanusiaan adalah cita-cita kami. Hukum dan demokrasi adalah tempat kami mengembalikan segala keberbedaan.
Jakarta, 9 Juli 2007
Hudan Hidayat
Djenar Maesa Ayu
Mariana Aminuddin
Fadjroel Rahman
Kesempurnaan kemanusiaan bagi kami adalah toleransi atas keberagaman nilai, tempat di mana warga bangsa-bangsa berbahagia atas keberbedaannya. Setiap upaya atas dasar moral, nilai-nilai atau kekuasaan yang hendak membelenggunya adalah menghambat dan menjauhkan manusia dari kemajuan dan kebebasannya sendiri.
Kami adalah manusia bebas. Berdaulat atas jiwa dan raga kami untuk mencipta kemanusiaan kami sendiri, dalam kebebasan penciptaan tanpa penjajahan. Sumber penciptaan untuk meraih kemajuan, akan kami gali dari bumi mana pun yang kami olah dan kami persembahkan bagi kemajuan dan kemuliaan kemanusiaan.
Kemajuan dan kebebasan kemanusiaan adalah cita-cita kami. Hukum dan demokrasi adalah tempat kami mengembalikan segala keberbedaan.
Jakarta, 9 Juli 2007
Hudan Hidayat
Djenar Maesa Ayu
Mariana Aminuddin
Fadjroel Rahman
Saturday, July 07, 2007
Langganan The New Yorker
Saya mau rekomendasi Anda untuk berlangganan mingguan The New Yorker, sebuah majalah yang jadi icon kebudayaan dan pemikiran di Amerika, langsung dari pusat distribusi mereka di New York.
Saya minggu lalu membayar dengan kartu kredit US$47 untuk langganan setahun. Mulanya saya duga ada biaya ongkos kirim terpisah. Kalau beli eceran di Jakarta, satu eksemplar dijual Rp 90,000 di toko buku besar yang menjual buku-buku bahasa Inggris. Ternyata tak ada ongkos kirim. Langganan dari mana pun di seluruh dunia, sama dengan langganan dari dalam Amerika hanya $47 setahun.
Ini artinya, satu majalah hanya seharga sekitar Rp 10,000, langsung tiba di pintu rumah saya. Ini bahkan lebih murah dari majalah terbitan Jakarta. Saya duga The New Yorker, yang pendapatan iklannya besar, memang mencari pelanggan long term. Dalam permintaan langganan, saya katakan bahwa saya baca majalah ini secara eceran sejak 1988. Saya juga langganan majalah ini ketika dulu tinggal di Cambridge, dekat Boston.
Saya pernah menulis resensi soal The New Yorker berjudul "Cermin Jakarta, Cermin New York". Ini majalah bagus. Banyak naskah klasik, misalnya "Hiroshima" karya John Hersey, "Silent Spring" karya Rachel Carson, "Down at the Cross" karya James Baldwin, "In Cold Blood" karya Truman Capote" dan masih banyak lainnya, terbit dari majalah ini. Mereka kini juga punya banyak penulis dan artis, yang termasuk terbaik di dunia.
Anda harus punya kartu kredit untul langganan via situs web The New Yorker.
Tuesday, July 03, 2007
✒
"But what is the difference between literature and journalism? ... Journalism is unreadable and literature is not read. That is all.
-- Oscar Wilde (1854 - 1900) in The Critic as Artist, 1891
"Literature is the art of writing something that will be read twice; journalism what will be read once."
-- Cyril Connolly (1903 - 1974) in Enemies of Promise, 1938

Daoed and Sri Soelastri Joesoef (duduk di kursi) bersama para peserta kursus Yayasan Pantau, yang datang ke rumah mereka di daerah Kemang guna berdiskusi soal penulisan buku Emak.
Belajar dari Ryszard Kapuscinski
Deskripsi bisa dibuat dengan menggunakan foto-foto lama. Ini trik khas Kapuscinski guna cerita secara kronologis.
Daoed Joesoef Bertutur
Mellyana F. Silalahi cerita kesannya ikut diskusi dengan Daoed Joesoef, seorang sarjana Sorbonne, yang menulis buku Emak, di rumahnya di selatan Jakarta.
Masalah dalam Proyek Seabad Pers Indonesia
Kapan sebenarnya "pers Indonesia" dimulai? Indexpress pimpinan Taufik Rahzen menetapkannya 1907 ketika Tirto Adhi Soerjo menerbitkan Medan Prijaji dengan alasan dia pribumi?
Sisa Kesultanan Banten
Lima ratus tahun lalu, Banten dibandingkan besar dan modernnya dengan Paris. Ia lebih besar dari Sunda Kelapa. Hari ini ia jadi desa nelayan terpencil dan gersang.
Kursus Jurnalisme Sastrawi XII
Mulanya, genre ini diterangkan oleh Tom Wolfe pada 1960an di New England. Muncul bermacam tanggapan, baik yang sinis maupun memuji. Janet Steele dan saya mencoba belajar dari pengalaman itu.
Indonesia: A Lobbying Bonanza
Taufik Kiemas, when his wife Megawati Sukarnoputri was still president, collected political money to hire a Washington firm to lobby for Indonesian weapons. This story is a part of a project called Collateral Damage: Human Rights and US Military Aid
 Dari Sabang Sampai Merauke
Dari Sabang Sampai MeraukeSejak Juli 2003, saya berkelana dari Sabang ke Merauke, guna wawancara dan riset buku. Intinya, saya pergi ke tujuh pulau besar, dari Sumatra hingga Papua, plus puluhan pulau kecil macam Miangas, Salibabu, Ternate dan Ndana. Inilah catatan kecil perjalanan tersebut.
Hoakiao dari Jember
Ong Tjie Liang, satu travel writer kelahiran Jember, malang melintang di Asia Tenggara. Dia ada di kamp gerilya Aceh namun juga muncul di Rangoon, bertemu Nobel laureate Aung San Suu Kyi maupun Jose Ramos-Horta.
State Intelligence Agency hired Washington firm
Indonesia's intelligence body used Abdurrahman Wahid’s charitable foundation to hire a Washington lobbying firm to press the U.S. Congress for a full resumption of military assistance to Indonesia. Press Release and Malay version
From the Thames to the Ciliwung
Giant water conglomerates, RWE Thames Water and Suez, took over Jakarta's water company in February 1998. It turns out to be the dirty business of selling clean water.
Media dan Jurnalisme
Saya suka menulis soal media dan jurnalisme. Pernah juga belajar dengan asuhan Bill Kovach dari Universitas Harvard. Ini makin sering sesudah diminta menyunting majalah Pantau.
Bagaimana Cara Belajar Menulis Bahasa Inggris
Bahasa punya punya empat komponen: kosakata, tata bahasa, bunyi dan makna. Belajar bahasa bukan sekedar teknik menterjemahkan kata dan makna. Ini juga terkait soal alih pikiran.
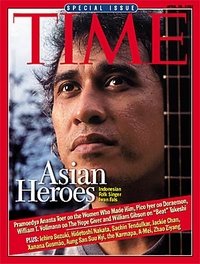 Dewa dari Leuwinanggung
Dewa dari LeuwinanggungSaya meliput Iwan Fals sejak 1990 ketika dia meluncurkan album Swami. Waktu itu Iwan gelisah dengan rezim Soeharto. Dia membaca selebaran gelap dan buku terlarang. Dia belajar dari W.S. Rendra dan Arief Budiman. Karir Iwan naik terus. Iwan Fals jadi salah satu penyanyi terbesar yang pernah lahir di Pulau Jawa. Lalu anak sulungnya meninggal dunia. Dia terpukul. Bagaimana Iwan Fals bangkit dari kerusuhan jiwa dan menjadi saksi?
Sunday, July 01, 2007
Nabi Tanpa Wahyu
Jawa Pos, 1 Juli 2007
Oleh Hudan Hidayat
Dalam upayanya meredam filsafat dan ideologi penciptaan yang saya ajukan, yakni keyakinan saya bahwa penceritaan ketelanjangan dibolehkan oleh kitab suci, dan kitab suci pun telah mendemonstrasikannya melalui kisah Adam dan Hawa, Taufiq Ismail melancarkan serangan balik dengan menggesernya ke dalam sebuah upaya stigma akan tendensi sastra: sastra SMS (sastra mazhab selangkangan) atau sastra FAK--fiksi alat kelamin--(Jawa Pos, 17 Juni 2007). Inilah upaya yang mengingatkan saya akan cara-cara Lekra menggempur lawan-lawannya dulu, dengan menyebut mereka "Manikebu".
Terasa bagi saya serangan balik Taufiq sangat mematikan. Dengan semangat anti-dialog dan anti-wacana, Taufiq seolah petinju yang memukul lawannya dengan tinju "kalang-kabut". Atau seolah banjir bandang yang menyerbu permukiman manusia tanpa nurani-nurani sastra. Dalam SMS-nya pada saya, Taufiq menyebut tentang "kebakaran budaya", yang penyebabnya antara lain sastra SMS atau sastra FAK, yang "bersama VCD porno dan situs seks internet... ikut merangsang perkosaan, menyebarkan penyakit kelamin menular, aborsi dan (minimum) masturbasi".
Begitulah serangan balik Taufiq Ismail yang mematikan itu. Dan, saya merasa terkunci: saya mewacanakan kemungkinan melukiskan ketelanjangan dalam sastra, sepanjang ketelanjangan itu berfungsi untuk sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi Taufiq berkelit akan kemungkinan sebuah tafsir. Ia lebih suka berteriak seolah nabi tanpa wahyu, yang mengacukan kepalannya pada fenomena sastra yang berseberangan dengan dirinya. Maka, bagaimana bila Taufiq malas berpikir akan kemungkinan tafsir, tapi serentak dengan itu gemar menghujat fenomena sastra yang disebutnya sastra SMS atau sastra FAK?
Kategori yang dibuat Taufiq dengan menstigma sastra SMS atau sastra FAK, menimbulkan persoalan dalam cara kita memandang dunia sastra. Termasuk cara kita berlogika dalam dunia sastra. Seperti SMS Goenawan Mohamad kepada saya, "Akan lebih berharga jika polemik yang timbul bukan seperti teriakan 'copet!', 'lonte lu!', atau 'babi!'. Serangan terhadap satu tendensi dalam sastra akan lebih berharga jika dikemukakan dalam cara kritik sastra: dengan telaah, argumentasi, penalaran yang kuat, gaya menulis yang meyakinkan atau menggugah." Karena itu, bagi saya, mematahkan kecenderungan sastra tanpa telaah sastra, tampak seakan "tujuan menghalalkan cara".
Pertanyaan untuk Taufiq, sudahkah dia membaca buku-buku penulis yang diserangnya dengan gencar itu? Apakah boleh pelukisan ketelanjangan di dalam buku-buku itu? Apakah ketelanjangan di sana bukan sebuah ancang-ancang, untuk meraih makna kesepian atau ketuhanan? Di sinilah Taufiq tidak bisa menghindar dari filsafat penciptaan dan ideologi penciptaan yang saya ajukan. Menghindarinya sambil memukul langsung fenomena itu sebagai sastra FAK adalah ibarat hakim tuli dalam satu sidang.
Sang hakim tidak mau mendengar alasan mengapa sang terdakwa "melakukan persetubuhan". Sang hakim hanya berpegang pada saksi-saksi, yang mungkin dirinya sendiri. Saksi yang tidak melihat keseluruhan rangkaian kejadian. Saksi yang hanya melihat scene persetubuhan. Dan, kemudian mengatakan telah terjadi persetubuhan. Padahal yang terjadi sebaliknya: bukan persetubuhan tapi pemerkosaan. Di mana sang wanita diperkosa, bersetubuh bukan atas kemauannya. Inilah prototipe sang hakim otoriter. Dia sudah bukan hakim lagi. Tetapi menjadi pemerkosa juga. Pemerkosa terhadap hak korban untuk berbicara.
Saya berpendapat, sastra yang disebut Taufiq sastra FAK itu, bukan sastra FAK atau sastra SMS. Sebutlah novel Saman karya Ayu Utami atau cerpen-cerpen Djenar Maesa Ayu. Mereka bukan sastra FAK. Tokoh Saman memang bukan karya sastra sekuat klaim tokoh di sampul belakang buku Saman. Tetapi bukan sastra FAK. Di sana, tubuh diangkat mengatasi tubuh. Meski tak terlalu meninggi. Karena itu menyebutnya sebagai sastra FAK adalah ibarat memandang malam tak bercahaya. Padahal di angkasa ada juga cahaya. Sebuah generalisasi yang menyesatkan.
Demikian juga dengan cerpen-cerpen Djenar. Ambillah contoh cerpen Menyusu Ayah di Jurnal Perempuan atau Melukis Jendela di majalah sastra Horison. Di kedua cerpen ini Djenar memang menyebutkan alat kelamin, tapi alat kelamin itu sekadar pintu masuk untuk makna lain. Yakni penderitaan sang anak yang menjadi korban kekerasan keluarga.
Darinya menyembul simpati akan korban kekerasan. Bukan nafsu seks dalam konteks "sastra mazhab selangkangan" yang dituduhkan Taufiq.
Lihatlah, betapa mengharukan bagaimana seorang anak di dalam cerpen Menyusu Ayah harus memetamorfosakan dirinya menjadi lelaki, demi terhindar dari kekerasan kaum lelaki. Atau lambang "jendela" dalam cerpen Djenar Melukis Jendela. Sebuah kehendak untuk berpindah dari kehidupan kini yang menyesakkannya. Tapi jendela yang dibayangkan itu pun menelan dirinya. Dengan hasrat berpindah dan hilangnya tokoh Mayra ke dalam jendela lain, seolah Djenar hendak mengatakan, "Dengarlah, tak ada yang sempurna di bumi!" Jadi cerpen itu sebuah metafora (dan karena itu para redaktur Horison yang muda-muda dan cerdas itu memuatnya). Maka, di mana FAK atau "sastra mazhab selangkangan" di kedua cerpen itu?
Demikian juga kalau kita membaca cerpen Mariana Amiruddin, Kota Kelamin, yang timbul bukan hasrat seks tetapi simpati akan manusia modern yang lelah mengatasi hipokrisi, yang selalu ditutup rapat seolah kelamin yang dibalut pada tubuh manusia.
Taufiq menyebut Ayu dan Djenar sebagai pelopor sastra FAK. Definisinya sederhana. Yakni, sastra yang ada atau berputar pada kelamin. Tanpa mau melihat ada transendensi. Tetapi Taufiq a historis. Sebab, kalau seperti itu definisi sastra FAK, mengapa Taufiq tidak menggugat novel Belenggu (yang ditolak Balai Pustaka karena moral selingkuhnya), atau novel Telegram dan Olenka. Bahkan puisi-puisi Rendra (yang memuja genital wanita) dan puisi Amuk Sutardji Calzoum Bachri –sebuah pencarian ketuhanan dengan lambang kucing, tetapi tak juga bisa menghindar dari menyebut nama alat kelamin laki-laki di dalam baris-barisnya.
Khusus novel Telegram Putu Wijaya dan Olenka Budi Darma, baik tokoh "aku" maupun Fanton bertindak gila-gilaan dengan hidup. Fanton bahkan merebut istri orang (Olenka) dan menidurinya tiap ada kesempatan. Olenka diperlakukannya seolah peta. Tangannya menyusur ke segenap tubuh Olenka dan kemudian berhenti di satu lubang: "Ini jalan ke surga!"
Tokoh "aku" lebih gila lagi. Dia membayangkan bersetubuh dengan ibunya yang "telah" mati. Sambil mereguk bir, dia menyetubuhi ibunya dalam mimpi. Tetapi toh nasib kedua novel ini mendapat tempat terhormat dalam sastra Indonesia. Mengapa? Karena ada transendensi. Walau pada Olenka, hemat saya, transendensi di sana terkesan takluk pada "dunia". Dengan lanturan yang bersandar pada "dunia", meski berhasil pada bentuk, membuat Olenka seolah inlanderisasi dalam sastra Indonesia. Olenka tak mampu mencari sumber orientasi sendiri.
Fenomena penulis "tubuh" ini sudah dibelokkan kapitalisasi pasar, dengan menggesernya ke soal seolah melulu seks dalam blow-up opini. Konon karena begitulah rating yang disukai masyarakat: seks. Dan, orang seperti Taufiq, yang seharusnya melawan kapitalisasi opini sastra seperti itu, dengan menunjukkan bahwa substansi sastra mereka bukan melulu seks, malah ikut-ikutan menunggang gelombang. Dunia sastra yang pernah membesarkannya, "diselewengkannya" ke dalam arus besar yang disebutnya "Gerakan Syahwat Merdeka". Padahal sastra yang ditulis itu bukanlah semata "syahwat merdeka". Tetapi "syahwat" sebagai sampiran untuk kemerdekaan manusia. Kemuliaan manusia. Persis seperti novel Sendalu yang bertaburan alat dan nafsu kelamin yang ditulis Chavchay Syaifullah, tetapi dengan motif memperjuangkan perempuan sebagai korban perkosaan. Atau tokoh pelacur dalam cerpen Ahmadun Pintu, yang mengoyak-ngoyak pakaiannya sendiri di dalam masjid demi kehendak untuk telanjang (suci) saat menghadap Tuhannya.
Saya disebutnya sebagai komponen sastra FAK (pastilah Mariana Amiruddin juga). Apakah dasarnya? Karena kami menulis novel Tuan dan Nona Kosong? Karena saya dan Mariana melepaskan payudara, vagina, dan penis dari tempatnya dan benda-benda itu berkitar-kitar mengunjungi penonton?
Memang benar kami melukiskan hal-hal yang demikian. Tetapi, sastra FAK-kah itu? Tengok sekali lagi: betapa benda-benda itu cara kami menghampiri Tuhan. Seperti dalam irama lain (cerpen Lelaki Ikan dan Tongkatku, Musa) saya menyapa Tuhan. Lihatlah seorang lelaki di dalam novel itu melompat ke udara sambil berteriak, "Tuhan tidak seperti kita kira. Jadi mari kita rayakan hidup ini. Jangan benci kami!"
Tuan Taufiq, barangkali seniman memang mengidap kegilaan. Tetapi kegilaan yang meninggi untuk menjangkau Tuhan. Menjangkau Tuhan dengan lambang dan sampiran, sehingga sastra menjadi dunia metafora yang sedap untuk dibaca. Mencerahkan manusia. Duh, nasib seekor hh. (*)
Hudan Hidayat, penulis novel Tuan dan Nona Kosong bersama Mariana Amiruddin
Oleh Hudan Hidayat
Dalam upayanya meredam filsafat dan ideologi penciptaan yang saya ajukan, yakni keyakinan saya bahwa penceritaan ketelanjangan dibolehkan oleh kitab suci, dan kitab suci pun telah mendemonstrasikannya melalui kisah Adam dan Hawa, Taufiq Ismail melancarkan serangan balik dengan menggesernya ke dalam sebuah upaya stigma akan tendensi sastra: sastra SMS (sastra mazhab selangkangan) atau sastra FAK--fiksi alat kelamin--(Jawa Pos, 17 Juni 2007). Inilah upaya yang mengingatkan saya akan cara-cara Lekra menggempur lawan-lawannya dulu, dengan menyebut mereka "Manikebu".
Terasa bagi saya serangan balik Taufiq sangat mematikan. Dengan semangat anti-dialog dan anti-wacana, Taufiq seolah petinju yang memukul lawannya dengan tinju "kalang-kabut". Atau seolah banjir bandang yang menyerbu permukiman manusia tanpa nurani-nurani sastra. Dalam SMS-nya pada saya, Taufiq menyebut tentang "kebakaran budaya", yang penyebabnya antara lain sastra SMS atau sastra FAK, yang "bersama VCD porno dan situs seks internet... ikut merangsang perkosaan, menyebarkan penyakit kelamin menular, aborsi dan (minimum) masturbasi".
Begitulah serangan balik Taufiq Ismail yang mematikan itu. Dan, saya merasa terkunci: saya mewacanakan kemungkinan melukiskan ketelanjangan dalam sastra, sepanjang ketelanjangan itu berfungsi untuk sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi Taufiq berkelit akan kemungkinan sebuah tafsir. Ia lebih suka berteriak seolah nabi tanpa wahyu, yang mengacukan kepalannya pada fenomena sastra yang berseberangan dengan dirinya. Maka, bagaimana bila Taufiq malas berpikir akan kemungkinan tafsir, tapi serentak dengan itu gemar menghujat fenomena sastra yang disebutnya sastra SMS atau sastra FAK?
Kategori yang dibuat Taufiq dengan menstigma sastra SMS atau sastra FAK, menimbulkan persoalan dalam cara kita memandang dunia sastra. Termasuk cara kita berlogika dalam dunia sastra. Seperti SMS Goenawan Mohamad kepada saya, "Akan lebih berharga jika polemik yang timbul bukan seperti teriakan 'copet!', 'lonte lu!', atau 'babi!'. Serangan terhadap satu tendensi dalam sastra akan lebih berharga jika dikemukakan dalam cara kritik sastra: dengan telaah, argumentasi, penalaran yang kuat, gaya menulis yang meyakinkan atau menggugah." Karena itu, bagi saya, mematahkan kecenderungan sastra tanpa telaah sastra, tampak seakan "tujuan menghalalkan cara".
Pertanyaan untuk Taufiq, sudahkah dia membaca buku-buku penulis yang diserangnya dengan gencar itu? Apakah boleh pelukisan ketelanjangan di dalam buku-buku itu? Apakah ketelanjangan di sana bukan sebuah ancang-ancang, untuk meraih makna kesepian atau ketuhanan? Di sinilah Taufiq tidak bisa menghindar dari filsafat penciptaan dan ideologi penciptaan yang saya ajukan. Menghindarinya sambil memukul langsung fenomena itu sebagai sastra FAK adalah ibarat hakim tuli dalam satu sidang.
Sang hakim tidak mau mendengar alasan mengapa sang terdakwa "melakukan persetubuhan". Sang hakim hanya berpegang pada saksi-saksi, yang mungkin dirinya sendiri. Saksi yang tidak melihat keseluruhan rangkaian kejadian. Saksi yang hanya melihat scene persetubuhan. Dan, kemudian mengatakan telah terjadi persetubuhan. Padahal yang terjadi sebaliknya: bukan persetubuhan tapi pemerkosaan. Di mana sang wanita diperkosa, bersetubuh bukan atas kemauannya. Inilah prototipe sang hakim otoriter. Dia sudah bukan hakim lagi. Tetapi menjadi pemerkosa juga. Pemerkosa terhadap hak korban untuk berbicara.
Saya berpendapat, sastra yang disebut Taufiq sastra FAK itu, bukan sastra FAK atau sastra SMS. Sebutlah novel Saman karya Ayu Utami atau cerpen-cerpen Djenar Maesa Ayu. Mereka bukan sastra FAK. Tokoh Saman memang bukan karya sastra sekuat klaim tokoh di sampul belakang buku Saman. Tetapi bukan sastra FAK. Di sana, tubuh diangkat mengatasi tubuh. Meski tak terlalu meninggi. Karena itu menyebutnya sebagai sastra FAK adalah ibarat memandang malam tak bercahaya. Padahal di angkasa ada juga cahaya. Sebuah generalisasi yang menyesatkan.
Demikian juga dengan cerpen-cerpen Djenar. Ambillah contoh cerpen Menyusu Ayah di Jurnal Perempuan atau Melukis Jendela di majalah sastra Horison. Di kedua cerpen ini Djenar memang menyebutkan alat kelamin, tapi alat kelamin itu sekadar pintu masuk untuk makna lain. Yakni penderitaan sang anak yang menjadi korban kekerasan keluarga.
Darinya menyembul simpati akan korban kekerasan. Bukan nafsu seks dalam konteks "sastra mazhab selangkangan" yang dituduhkan Taufiq.
Lihatlah, betapa mengharukan bagaimana seorang anak di dalam cerpen Menyusu Ayah harus memetamorfosakan dirinya menjadi lelaki, demi terhindar dari kekerasan kaum lelaki. Atau lambang "jendela" dalam cerpen Djenar Melukis Jendela. Sebuah kehendak untuk berpindah dari kehidupan kini yang menyesakkannya. Tapi jendela yang dibayangkan itu pun menelan dirinya. Dengan hasrat berpindah dan hilangnya tokoh Mayra ke dalam jendela lain, seolah Djenar hendak mengatakan, "Dengarlah, tak ada yang sempurna di bumi!" Jadi cerpen itu sebuah metafora (dan karena itu para redaktur Horison yang muda-muda dan cerdas itu memuatnya). Maka, di mana FAK atau "sastra mazhab selangkangan" di kedua cerpen itu?
Demikian juga kalau kita membaca cerpen Mariana Amiruddin, Kota Kelamin, yang timbul bukan hasrat seks tetapi simpati akan manusia modern yang lelah mengatasi hipokrisi, yang selalu ditutup rapat seolah kelamin yang dibalut pada tubuh manusia.
Taufiq menyebut Ayu dan Djenar sebagai pelopor sastra FAK. Definisinya sederhana. Yakni, sastra yang ada atau berputar pada kelamin. Tanpa mau melihat ada transendensi. Tetapi Taufiq a historis. Sebab, kalau seperti itu definisi sastra FAK, mengapa Taufiq tidak menggugat novel Belenggu (yang ditolak Balai Pustaka karena moral selingkuhnya), atau novel Telegram dan Olenka. Bahkan puisi-puisi Rendra (yang memuja genital wanita) dan puisi Amuk Sutardji Calzoum Bachri –sebuah pencarian ketuhanan dengan lambang kucing, tetapi tak juga bisa menghindar dari menyebut nama alat kelamin laki-laki di dalam baris-barisnya.
Khusus novel Telegram Putu Wijaya dan Olenka Budi Darma, baik tokoh "aku" maupun Fanton bertindak gila-gilaan dengan hidup. Fanton bahkan merebut istri orang (Olenka) dan menidurinya tiap ada kesempatan. Olenka diperlakukannya seolah peta. Tangannya menyusur ke segenap tubuh Olenka dan kemudian berhenti di satu lubang: "Ini jalan ke surga!"
Tokoh "aku" lebih gila lagi. Dia membayangkan bersetubuh dengan ibunya yang "telah" mati. Sambil mereguk bir, dia menyetubuhi ibunya dalam mimpi. Tetapi toh nasib kedua novel ini mendapat tempat terhormat dalam sastra Indonesia. Mengapa? Karena ada transendensi. Walau pada Olenka, hemat saya, transendensi di sana terkesan takluk pada "dunia". Dengan lanturan yang bersandar pada "dunia", meski berhasil pada bentuk, membuat Olenka seolah inlanderisasi dalam sastra Indonesia. Olenka tak mampu mencari sumber orientasi sendiri.
Fenomena penulis "tubuh" ini sudah dibelokkan kapitalisasi pasar, dengan menggesernya ke soal seolah melulu seks dalam blow-up opini. Konon karena begitulah rating yang disukai masyarakat: seks. Dan, orang seperti Taufiq, yang seharusnya melawan kapitalisasi opini sastra seperti itu, dengan menunjukkan bahwa substansi sastra mereka bukan melulu seks, malah ikut-ikutan menunggang gelombang. Dunia sastra yang pernah membesarkannya, "diselewengkannya" ke dalam arus besar yang disebutnya "Gerakan Syahwat Merdeka". Padahal sastra yang ditulis itu bukanlah semata "syahwat merdeka". Tetapi "syahwat" sebagai sampiran untuk kemerdekaan manusia. Kemuliaan manusia. Persis seperti novel Sendalu yang bertaburan alat dan nafsu kelamin yang ditulis Chavchay Syaifullah, tetapi dengan motif memperjuangkan perempuan sebagai korban perkosaan. Atau tokoh pelacur dalam cerpen Ahmadun Pintu, yang mengoyak-ngoyak pakaiannya sendiri di dalam masjid demi kehendak untuk telanjang (suci) saat menghadap Tuhannya.
Saya disebutnya sebagai komponen sastra FAK (pastilah Mariana Amiruddin juga). Apakah dasarnya? Karena kami menulis novel Tuan dan Nona Kosong? Karena saya dan Mariana melepaskan payudara, vagina, dan penis dari tempatnya dan benda-benda itu berkitar-kitar mengunjungi penonton?
Memang benar kami melukiskan hal-hal yang demikian. Tetapi, sastra FAK-kah itu? Tengok sekali lagi: betapa benda-benda itu cara kami menghampiri Tuhan. Seperti dalam irama lain (cerpen Lelaki Ikan dan Tongkatku, Musa) saya menyapa Tuhan. Lihatlah seorang lelaki di dalam novel itu melompat ke udara sambil berteriak, "Tuhan tidak seperti kita kira. Jadi mari kita rayakan hidup ini. Jangan benci kami!"
Tuan Taufiq, barangkali seniman memang mengidap kegilaan. Tetapi kegilaan yang meninggi untuk menjangkau Tuhan. Menjangkau Tuhan dengan lambang dan sampiran, sehingga sastra menjadi dunia metafora yang sedap untuk dibaca. Mencerahkan manusia. Duh, nasib seekor hh. (*)
Hudan Hidayat, penulis novel Tuan dan Nona Kosong bersama Mariana Amiruddin
Subscribe to:
Posts (Atom)