Monday, October 29, 2007
Janji Games, Janji Kosong
Norman menelepon dan menangis. Dia minta dibelikan satu perangkat tambahan untuk komputernya. Pasalnya, Retno Wardani, ibunya, membelikan dia satu game baru namun tak bisa dipasang. Game ini menuntut tambahan card di komputer Norman.
Retno meninggalkan CPU komputer Norman di sebuah toko komputer di Poins Square lantai 2 nomor 25. Maksudnya, Norman dimintanya tukar game dengan yang sederhana. Tapi Norman terburu suka dengan game baru itu. Walau ia butuh tambahan VGA card merk Nvidia minimal 128 MByte.
Repotnya, Retno janji menemui Norman di Poins Square. Namun Retno tak menepati janji. Norman datang sendirian dengan Fadil, sopir mobil kami. Jadinya, Norman menangis histeris.
Dia menelepon aku. Dia bilang Retno minta aku membelikannya card tersebut. Retno minta aku datang ke Poins Square dan bawa uang. Retno sendiri sudah pergi. Hujan deras.
Aku tak tega dengar Norman menangis. Aku minta dia datang saja ke apartemen di Senayan. Sesudah dia merasa tenang, aku membawanya beli card tersebut di toko Platinum Computer, Ratu Plaza lantai 3 nomor 52. Kami membeli tambahan card VGA AGP Geforce 128 MX 4000 seharga Rp 325,000.
Retno menjanjikan game ini Minggu siang ketika membujuk Norman pergi ke Bintaro sesudah insiden dengan polisi Sabtu malam. Norman awalnya tak mau pergi ke Bintaro. Mungkin janji game baru, membuat Norman tertarik datang ke Bintaro. Ternyata, game itu tak bisa dipasang. Buntutnya, aku pula yang harus memenuhi persyaratan game ini.
Retno Bawa Polisi untuk Ambil Norman
Retno Wardani, mantan isteri aku, membawa seorang polisi Sabtu malam guna menjemput anak kami, Norman Harsono, dari rumahku di Senayan sesudah Norman menolak pergi ke rumah ibu kandungnya itu di Bintaro.
Ini kejadian luar biasa, yang melelahkan sekali, melibatkan bukan hanya Retno dan aku, namun juga Sapariah, isteri aku, serta beberapa teman kami, yang kebetulan mendengar atau menyaksikan bagaimana Retno berusaha “mengambil” Norman dengan cara tak patut.
Kejadian ini bermula Sabtu siang, ketika Norman tiba-tiba menelepon aku di Pesta Blogger di Blitz Megaplex, Grand Indonesia. Norman bilang ibunya minta dia segera pergi ke Bintaro.
Namun Norman menolak pergi ke Bintaro. Dia bilang, sesuai janji pertukaran waktu tinggal selama liburan, Norman bisa tinggal di Senayan bersama aku, hingga Minggu siang. Liburan Lebaran kemarin, Norman tinggal bersama Retno terus.
Retno sendiri, sejak Agustus lalu, pindah ke Bintaro. Retno menumpang tinggal di rumah ibunya, M.Th. Koesmiharti, sesudah Retno kesulitan finansial dan mengkontrakkan rumah gono-gini, milik Norman, di Pondok Indah. Bintaro jauh sekali dari sekolah Norman di Kemayoran. Dia minta pindah ke Senayan saja. Retno tak mau.
Retno bersikeras Norman pergi ke Bintaro. Norman tetap mengatakan tidak mau. Norman hanya akan pergi ke Bintaro Minggu siang. “Wah, bakal ramai nih,” aku pikir. Aku beri tahu Imam Shofwan, rekan kerja, yang sama-sama datang ke Pesta Blogger.
Babak pertama. Kami segera pulang ke Senayan. Norman terlihat kesal. Dia mengatakan kuatir ibunya menjemput paksa. Aku menelepon Retno dan memberitahu keinginan Norman. Retno menolak dan bersikeras aku mengantar Norman ke Bintaro. Aku katakan berkali-kali Norman tidak mau.
Siangnya, bersama Sapariah serta beberapa kolega dari Pantau – Anugerah “Nugi” Perkasa, Basil Triharyanto, Dayu Pratiwi, Imam Shofwan, Khoiruddien, Rina Erayanti, Siti Nurrofiqoh— Norman dan aku pergi ke resepsi pernikahan Samiaji Bintang dengan Fitriana Rusli di Kebun Jeruk. Bintang rekan kerja kami di Pantau Aceh. Kami ramai-ramai datang ke acara bahagia untuk Bintang dan Fitri.
Norman membawa buku Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Dia sibuk makan siomay serta membaca buku sembari menemani kami semua mengobrol dan bergurau dalam pesta. Norman tampaknya melupakan permintaan ibunya.
Babak kedua. Pulangnya, Nugi dan Imam menumpang mobil kami. Disinilah ketegangan muncul lagi ketika Retno tiba-tiba menelepon. Retno minta aku membawa Norman ke Bintaro. Aku bilang Norman tak mau. Retno minta bicara langsung dengan Norman.
Ketika telepon aku berikan ke Norman, Norman mendengar, namun tak bicara. Retno mematikan telepon. Norman bilang kepada kami bahwa dia sudah menjelaskan tiga kali pagi ini bahwa dia tak mau ke Bintaro.
Retno menelepon lagi. Aku berikan Norman lagi. Tak dijawab lagi. Retno menelepon lagi. Norman menolak lagi. Aku capek. Aku minta tolong Sapariah menjawab. Sapariah menjawabnya. Retno minta bicara pada Norman. Sapariah memberikan pada Norman. Norman menolak menjawab. Ini berulang kira-kira enam atau tujuh kali.
Nugi ikut membantu menjawab. Nugi memberitahu Retno bahwa telepon sudah diberikan ke Norman tapi dia tidak mau bicara. Retno mengebel lagi. Nugi, Sapariah maupun Imam sama-sama tak mau menjawab. Kapok. Ada usul agar telepon dimatikan saja.
Aku angkat lagi. Retno memaki-maki. Dia bilang aku yang “ngompor-ngompori” Norman. Dia bilang kalau Norman tinggal dengan aku, saat itu juga Norman berubah. “Sekarang, aku minta kamu bertanggungjawab. Kamu antar Norman ke Bintaro!” katanya.
Aku jawab, “Aku tidak mau. Kalau Norman tidak mau, aku juga tidak mau.”
Norman minta kami tidak pulang ke Senayan. Dia kuatir Retno menjemputnya di Senayan. Aku bilang tak apa. Toh kami harus ganti pakaian. Aku lelah, sepagian ikut Pesta Blogger, siang resepsi serta kehujanan, seraya kena macet di Kebun Jeruk. Aku juga masih menghadapi telepon Retno terus-menerus. Norman jadi nervous.
Babak ketiga. Malam hari, Imam, Norman dan aku pergi menjemput seorang tamu, Glenn Raynor, dari Vancouver di Wisma PGI di Menteng. Glenn mengantar titipan satu set CD ROM majalah The New Yorker serta satu dokumen dari National Security Archive di Washington DC. Aku memang lagi mencari dokumen-dokumen ini guna riset.
Kami pergi makan malam di rumah makan khas Jawa Timur “Handayani” di Matraman. Makanannya lezat. Norman makan ayam goreng dan nonton Cartoon Network.
Tiba-tiba Retno menelepon. Dia bilang dia sudah ada di apartemen Senayan. Retno minta aku membawa Norman ke Senayan. Aku bilang Norman tidak mau. Aku membantu anakku.
Menurut Sapariah, Retno naik dan masuk ke apartemen bersama pengasuh Norman, Sri Maryani. Sapariah mempersilahkannya duduk. Handphone aku mati kehabisan baterai. Retno minta nomor Imam kepada Sapariah. Norman mendengar permintaan itu ketika Imam menyampaikannya kepada aku. “Papa, she gets on my nerves,” kata Norman. Dia menangis.
Retno menelepon Imam lagi. Aku sampaikan kepada Retno, Norman menolak pulang ke Senayan. Retno teriak-teriak, “Kalau kamu nggak bawa Norman ke sini, aku panggil polisi. Ini keputusan pengadilan. Kamu jangan serakah. Kamu pakai otakmu!”
Glenn merasa ada yang tak beres. Aku cerita singkat saja. Glenn ikut prihatin. Kami mengantar Glenn kembali ke hotel. Ketika keluar dari mobil, Norman merangkul aku lagi. Matanya basah.
Aku memutuskan pergi ke sebuah toko Indosat di pertokoan Sarinah. Tujuannya, membereskan tagihan telepon Matrix, yang membengkak, gara-gara ada otomatis SMS keluar saat aku di Napoli dan Roma bulan lalu. Lama menunggu giliran layanan Matrix. Mereka berjanji melakukan "investigasi."
Disinilah, Retno menelepon lagi dan bilang dia sudah datang bersama seorang polisi. Dia minta aku membawa Norman ke Senayan “sekarang juga.” Menurut Sapariah, dalam apartemen kami, Retno duduk di ruang makan bersama polisi tersebut. Retno bicara terus, soal aku yang sering menggunakan kekerasan terhadap Norman. Retno menuduh aku pernah menghalanginya membawa Norman dari Senayan. Aku memukul Retno “hingga berdarah-darah.” Dia mengatakan tak pernah secuil pun menyakiti Norman. Retno juga membawa dokumen-dokumen, seperti perjanjian notaris terkait perceraian, lalu menunjukkannya ke polisi. Retno menekankan bahwa aku pernah memukulinya di Cambridge.
Norman lari ke lantai bawah di Sarinah, menghindar dari kemungkinan Imam atau aku memberikan telepon kepadanya. Aku kasihan sekali lihat dia lari. Aku putuskan Norman tak perlu pergi ke Senayan. Norman tak perlu merasa lebih tertekan lagi. Imam bilang ini tak baik untuk psikologi Norman. Imam setuju. Sekali, Norman mengatakan kepada si polisi, via telepon, dia tak mau menemui ibunya.
Polisi mengatakan pada Sapariah bahwa dia menemani Retno sebagai tindakan “pengamanan” saja. Menurut Sapariah, polisi ini lebih banyak diam dan tersenyum.
Di Senayan, Sapariah dan Isah, mamak mertua aku, yang kebetulan lagi main di tempat kami, mencoba menenangkan Retno. Usaha yang sia-sia. Retno minta Sapariah tidak ikut campur urusan ini. Sapariah tersinggung. Ini tamu datang ke rumah dan minta si tuan rumah tidak bicara. Sapariah mencoba menjelaskan logika bolak-baliknya Retno.
Retno mengancam menggugat aku ke pengadilan karena tidak mentaati kesepakatan perceraian kami. Aku bilang dia "sinting" dengan logika terbolak-balik, mencampur aduk antara fakta dan fiksi. "Kapan aku memukul kamu hingga berdarah-darah ketika mau ambil Norman?"
Dia jawab, "Di Amerika dulu, kamu dipenjara karena memukul aku!" Dia bilang ke polisi, "Dengar sendiri? Dia melakukan kekerasan. Dia bilang saya 'sinting.'"
Babak terakhir.Di tengah banjir telepon, aku pinjam telepon Imam untuk menelepon Susilahati dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Susilahati lagi dalam perjalanan menuju Makassar bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Susilahati mengatakan aku sebaiknya menelepon seorang perwira polisi di Kepolisian Daerah Metro Jakarta, yang bertanggungjawab mengurus masalah anak. Dia memberi nomor telepon "Pak Rivai."
Ajun Komisaris Besar Ahmad Rivai, Kepala Satuan Remaja, Anak dan Wanita Kepolisian Jakarta, mengatakan polisi tak berhak membantu penjemputan anak dalam sengketa begini. Aku adalah ayah kandung Norman. Dia ingin bicara langsung dengan polisi yang menemani Retno. Namun mereka sudah pergi.
Kami pun mengantar Imam pulang. Norman masih merasa nervous. Dia ingin mampir di tempat Imam. Aku bilang sudah larut. Norman dan aku kembali ke Senayan pukul 23:00. Hari yang melelahkan sekali. Norman minta aku membuatkan pasta. Sapariah cerita soal kedatangan Retno. Kelihatannya, dia juga tertekan. Namun kami merasa harus bertahan dari tekanan ini.
Related Stories
Norman Menjelang Perceraian
Asthma Cases on the Rise Among Children
"Jangan Seenak Jidatmu Sendiri!"
Norman Dipindah ke Bintaro
Surat untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kronologi Hak Pengasuhan Norman Harsono
Dokter Andreas Liando di Siloam Gleneagles
20 Menit Senayan-Kemayoran
Norman Bertemu Komisi Perlindungan Anak
Transportasi Norman Rp 4.5 Juta Sebulan
Kemayoran-Bintaro 64 Kilometer
Susilahati dari Komisi Anak
Superhero Norman
Mobil Norman Serempetan
Catatan Liburan Lebaran
Friday, October 26, 2007
Quo vadis jurnalisme Islami?
Dear Rudi Agung,
Terima kasih untuk penjelasannya soal berbagai pendapat "pakar nasional" soal apa yang mereka sebut "jurnalisme Islami." Singkatnya, saya pikir pendapat orang-orang ini belum cukup kuat. Mereka belum menghasilkan metode baru, yang membuat genre ini bisa dipertahankan secara teoritis. Mereka hanya akan bikin mahasiswa macam Anda, bingung. Mereka mengambil kesimpulan dari bacaan-bacaan Barat tersebut dengan campur aduk antara perspektif Islam, audiens Muslim serta pekerjaan wartawan.
Tidakkah Zaim Uchrowi dan Nurul Hamami, keduanya wartawan dari harian Republika, yang memiliki target pasar warga Muslim, mengatakan sendiri kepada Anda bahwa jurnalisme tak bisa dibagi-bagi dengan agama. Singkatnya, tidak ada jurnalisme Islami.
Mari kita lihat argumentasi para "pakar" tersebut!
"... jurnalisme Islam, dapat dimaknakan sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayaknya. Jurnalisme Islam dapat pula dimaknai sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam dengan mengedepankan dakwah Islamiyah."
Apa bedanya dengan propaganda? Kalau suatu jurnalisme dikaitkan dengan pemahaman lain, entah itu fasisme, komunisme, kapitalisme atau agama apapun, definisi yang lebih tepat, saya kira, adalah propaganda.
Propaganda adalah suatu peliputan, penulisan serta penyajian informasi dimana fakta-fakta itu disajikan, termasuk ditekan dan diperkuat pada bagian tertentu, agar selaras dengan kepentingan ideologi atau kekuasaan yang memanipulasi komunikasi tersebut.
Jurnalisme adalah bagian dari komunikasi. Namun tak semua elemen komunikasi adalah jurnalisme. Propaganda maupun dakwah juga bagian dari komunikasi. Namun menyamakan propaganda dengan jurnalisme, atau menyamakan dakwah dengan jurnalisme, saya kira akan menciptakan kebingungan yang serius dengan daya rusak besar.
Coba kita ganti kata "jurnalisme" dengan "dakwah" dalam frasa "jurnalisme Islami."
"... dakwah Islam, dapat dimaknakan sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayaknya. Dakwah Islam dapat pula dimaknai sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam dengan mengedepankan dakwah Islamiyah."
Saya kira lebih masuk akal memakai frasa "dakwah Islam" daripada "jurnalisme Islami."
Sekarang kita lihat definisi lainnya.
"... jurnalisme Islam sarat dengan tuntutan dakwah yang mengemban misi 'amar ma'ruf nahyi munkar.' Jurnalisme Islam adalah upaya dakwah Islamiyah. Karena jurnalisme Islam bermisi amar ma'ruf nahyi munkar, maka ciri khasnya adalah menyebarluaskan informasi tentang perintah dan larangan Allah SWT. Jurnalistik ini berusaha keras untuk mempengaruhi komunikan/khalayaknya agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam."
Bagaimana kalau frasa 'amar ma'ruf nahyi munkar' itu kita ganti dengan, misalnya, semboyan kaum Protestan, "Cintailah sesamamu manusia." Atau ganti saja dengan semboyan Kejawen, Buddha, Parmalin dan lainnya.
Pakar komunikasi yang beragama Protestan, kelak mudah saja bilang, "jurnalisme Protestan" adalah upaya missionaris Kristen dengan semboyan, "Cintailah sesamamu manusia," dalam meliput dan menyiarkan informasi. Cirinya, menyebarluaskan informasi tentang Kalam Allah serta ajaran Yesus Kristus. Ia berusaha mempengaruhi khalayaknya agar berperilaku sesuai ajaran Kristus.
Menempelkan semboyan kepada kata "jurnalisme" bukanlah pekerjaan yang sulit. Namun ia akan menciptakan masalah banyak. Siapa yang berhak menilai sebuah karya itu Islami atau Kristiani?
Ukuran dalam agama itu kan bisa senantiasa diperdebatkan? Para "pakar nasional" itu mengatakan jurnalisme Islami ini memperjuangkan keadilan, kesejahteraan orang banyak dan sebagainya. Emangnya wartawan tidak memperjuangkan kepentingan publik? Apakah kalau seorang wartawan pakai label "jurnalisme Islami," maka otomatis tingkah-lakunya jadi beres, suci dan bebas dosa? Emangnya dia dijamin takkan terima amplop? Emangnya dia dijamin takkan masuk tim sukses para politisi?
Suatu genre dalam jurnalisme bisa diakui sebagai gerakan baru bila orang-orang yang mempromosikannya bisa menerangkan seperangkat metode, yang lebih advanced dari metode sebelumnya, tanpa melawan elemen-elemen klasik dalam jurnalisme.
Misalnya, investigative reporting diakui sebagai jurnalisme karena metode kerjanya lebih advanced dari liputan sehari-hari. Atau narrative reporting dianggap advanced karena ia memperkuat elemen jurnalisme dimana jurnalisme harus harus menarik dan relevan. Investigasi terkait dengan elemen jurnalisme dimana wartawan diperlukan untuk memantau kekuasaan.
Kalau Anda diminta untuk bikin paper soal "jurnalisme Islami," saya kira, perlu bilang dulu dengan dosen Anda soal definisi-definisi yang kacau balau itu.
Kalau begitu bagaimana dengan berbagai macam pertemuan wartawan dengan slogan agama? Sederhana saja. Pertemuan itu lebih untuk keperluan menggalang kerja sama, katakanlah, sesama media yang memperhitungkan audiens agama sebagai target mereka. Ini sih biasa dan sah. Menjalin kerja sama sesama media Islam, sesama media Buddha, Katolik dan sebagainya, tak berarti menciptakan genre baru dalam jurnalisme.
Namun upaya-upaya ngawur menciptakan istilah "jurnalisme Islami" hanya akan merugikan kepentingan dan makna dari "jurnalisme" maupun "Islam." Ini akan memancing debat kusir berkepanjangan. Islam yang mana? Masak Islam dibilang propaganda?
Upaya ini mirip dengan upaya Departemen Penerangan menciptakan istilah "jurnalisme Pancasila" zaman Orde Baru dulu. Mereka mengatakan genre ini khas Indonesia. Pedomannya, UUD 1945, Pancasila dan NKRI. Hari ini, syukurlah, orang sudah tak bicara lagi soal semboyan ciptaan Menteri Penerangan Harmoko tersebut.
Anda mungkin tidak mengalami kerja sebagai wartawan pada zaman Orde Baru. Zaman itu repotnya setengah mati. Zaman itu, kalau orang mempertanyakan "jurnalisme Pancasila," aduh, bisa masuk penjara. Kini, jangan-jangan orang bisa dituduh menghina Islam bila bilang, "jurnalisme Islami" itu mengada-ada.
Jadi, sudahlah nggak usah repot-repot bikin paper soal "jurnalisme Islami." Orang Madura bilang, "Ndek lakona." Kayak nggak punya kerjaan saja. Ini menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tak ada. Sekelangkong.
Pemberontakan Sandal Jepit
IMBAS (edisi khusus 1987)
Andreas Harsono
Andreas Harsono
TAHUN INI ada seorang mahasiswa yang diperingatkan dosennya, bahwa kalau sang mahasiswa masuk kuliah sekali lagi memakai sandal (jepit), dia akan dikeluarkan dari kelas. Peristiwa itu terjadi di Salatiga dan kuliahnya kebetulan Fisika Dasar I. Di kota yang sama itu, ketika lagi ramai-ramainya Pekan Ilmiah Mahasiswa (saya lebih senang pakai nama Pekan Ilmiah-Ilmiahan Maharesi), juga ada kasus serupa tapi tak sama. Serupa karena korbannya juga mahasiswa, tak sama karena kali ini subyeknya bukan dosen tetapi sesama mahasiswa. Mahasiswa memerintah (atau mungkin malah mengancam) mahasiswa. Terjadi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro di pintu ruang C107 (dulu namanya BU 1), berupa surat “ancaman” bagi siapa saja yang pakai sandal tidak boleh ikut seminar yang diadakan di balik pintu itu.
Lain dulu lain sekarang. Contoh paling baru adalah penyelenggaraan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM), semua peserta harus pakai sepatu berhubung panitia merasa (entah siapa) kurang dihormati kalau ada peserta LDKM yang memakai sandal. Atau adapula yang mengatakan bahwa segala tetek bengek yang melelahkan di latihan itu, untuk mempersiapkan mental kandidat-kandidat FTJE dalam rakornya Lembaga Kemahasiswaaan. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu forum resmi sehingga jaket almamater (yang harus tetap dipakai walaupun siang hari panas) dan sepatu harus dipakai. Saya tidak akan memperpanjang masalah itu, atau paling tidak memperdebatkannya, tetapi saya ingin “bercerita” sedikit tentang sandal. Sandal yang dulu juga dipakai oleh dosen-dosennya, bahkan sandal jepit dan pernah ditropikan pada acara malam keakraban 1985. Nah!
Anda, saya dan dia; kita sama-sama mahasiswa FTJE, pasti tahu bahwa dulu-dulunya sandal kepit begitu merajalela di Gedung C. Sekarangpun “raja lela” itu masih ada meskipun bentuknya bukan sandal jepit lagi, tetapi entah Neckermann entah sandal “pijat” yang bertutul-tutul itu, pokoknya masih sandal. Masih sandal karena pinggiran dari solnya tidak tertutup semua. Dan sandal itu masih dilengkapi dengan atribut-atribut lain meskipun tidak sering. Yakni kaos, celana jean, tas kain dan lainnya sehingga lengkaplah gambaran orang, bahwa anak elektro adalah orang yang seenaknya.
Gambaran yang tersohor itu dibarengi dengan tuduhan-tuduhan. Tuduhan bahwa kita kurang menghormati lawan bicara kita (kalau misalnya bertemu dengan entah Rektor, dosen fakultas lain ataupun mahasiswa yang merasa dirinya mahasiswa plus karena dia akitvis Lembaga Kemahasiswaan). Tidihan lain mengatakan, dan ini lebih kebangetan, anak Elektro itu tidak tahu aturan (aturannya siapa?) atau tuduhan, bahwa kita semua harus tetap pandai mengatur penampilan kita.
Tampaknya terlalu kekanak-kanakan untuk menerima penghormatan sebatas kaki. Bagi saya, dan mungkin juga kebanyakan anak Elektro, kepribadian saya tidak boleh dinilai dengan terlalu banyak atribut. Artinya atribut yang mendatangkan simpati tertentu.
Misalnya pakaian perlente, peralatan belajar yang mewah, mobil bagus (padahal yang lain paling banter sepeda motor), sedemikian rupa sehingga kepribadian saya yang asli tertutup oleh produk-produk kebanggaan itu. Boleh saja bermobil tetapi dengan catatan ketika mobil itu lepas dari tangan, orang masih tetap menghargai saya. Karena itulah, dan alasan-alasan lain, saya menolak untuk selalu bersepatu di kampus. Selain demi kepentingan pribadi juga demi kepentingan orang lain. Bahwa kita masih tetap harus prihatin akan adat budaya kita yang selalu sok kaya, sok pamer. Apalagi di tengah situasi kemiskinan saat ini, sandal merupakan salah satu bentuk ekspresinya.
Tetapi akhir-akhir ini saya lihat kita telah mulai berubah. Dulu anak Elektro banyak yang bersandal jepit di rapat, di kuliah, di asistensi atau acara lainnya. Sekarang, entah karan yang lagi “berkuasa” orang bersepatu, kebebasan itu semakin terbatas, sehingga timbullah kasus-kasus seperti di atas yang seharusnya masih bisa diperpanjang dengan contoh-contoh lain.
Bersepatu boleh-boleh saja asal jangan kemudian memaksa orang lain untuk turut bersepatu. Ini sudah bukan masalah “tahu aturan” atau tidak tapi sudah menjadi pemaksaan. Ikut seminar yang diadakan mahasiswa pekan ilmiah-ilmiahan harus bersepatu, masuk Biro Keuangan harus bersepatu. Sehingga saya benar-benar ketakutan kalau suatu hari aturan ini diperpanjang menjadi bersepatu dan berpakaian rapi (kaos boleh asal berkerah) seperti yang sudah berlaku di Universitas Kristen Petra Surabaya. Dan akan lebih mengecewakan kalau kemudian aturan yang menyesakkan itu dipaksakan tanpa tanda kurung. Pakaian rapi non kaos. Apakah kaos itu bukan termasuk pakaian yang rapi? Dan akan lebih menjengkelkan lagi bila kemudian ada aturan baru, baik tertulis maupun tidak, bahwa mahasiswi tidak boleh ikut kuliah memakai celana panjang, yang belakangan sudah menjadi umum berlaku di setiap perguruan tinggi negeri yang pernah saya kunjungi.
Kalau aturan-aturan yang menunjang birokrasi itu diteruskan, saya sangsi orang desa yang belum bisa bersepatu misalnya, beranikah mereka mengadukan nasib buruknya ke DPR? Beranikah tukang kebun yang tak punya seragam KORPRI masuk kantor dekan? Beranikah mahasiswa yang kebetulan urusannya sangat mendesak untuk masuk kantor Rektor? Semua bisa jadi semrawut kalau hal yang sepele ini diberlalukan secara ketat. Lembaga diciptakan untuk mengumpulkan kekuatan bersama dalam hal melawan hambatan-hambatan. Nah! Kalau suatu saat lembaga itu terlalu berat (over load) dengan segala aturan main, birokrasi dan rutinitas sehingga biaya untuk membayarnya menjadi terlalu mahal. Apa tidak seharusnya diadakan penyegaran kembali di lembaga itu. Atau kalau hal itu sudah tidak memungkinkan, lebih baik lembaga yang justru menghambat pencapaian tujuan itu dihancurkan saja. Dan untuk menghancurkan diperlukan lembaga tandingan yang umum disebut organisasi bawah tanah atau gerakan subversif.
Alasan lain yang bisa kita cari dari asal-usul sandal. Kebudayaan kita, katakanlah kebudayaan Jawa, tidak mengenal sepatu. Sepatu itu sendiri menyentuh kebudayaan Jawa bersamaan dengan datangnya penjajah Belanda. Di negara asalnya sepatu benar-benar dibutuhkan oleh orang Belanda. Bukan hanya sebagai alas kaki tetapi juga untuk melindungi kaki dari cuaca yang kelewat dingin, sehingga untuk menyambungnya diciptakan kaos kaki agar seluruh kakinya menjadi hangat.
Tetapi kita yang hidup di alam tropika ini seharusnya tidak begitu memerlukan sepatu. Alam kita cukup hangat. Dan kalaupun memerlukan alas kaki yang bisa dipakai untuk berlari, di Jawa ada semacam sepatu sandal untuk itu, di Minangkabau juga sepatu sandal. Sedangkan di acara-acara resmi, katakanlah di kerajaan Mataram, para kawulanya boleh bertelanjang kaki. Raja juga bertelanjang kaki atau boleh juga memakai selop (selop itu mungkin juga setelah pengaruh Belanda), tetapi seselop-selopnyapun masih bukan sepatu.
Lantas kalau Ariel Heryanto pernah menulis, “Ganasnya bahasa ganasnya politik,” dengan sebagian intinya, bahasa tidak netral. Saya juga bisa bilang, bahwa sepatu tidak netral (tentunya sandal jiga tidak), selalu ada konteks di belakang sepatu. Seperti judul buku Marshall MacLuhan, “Medium is the message”, tidak ada alat yang benar-benar netral. Teknologi, militer, bahasa, ilmu pengetahuan, seni apalagi politik, semuanya tidak netral.
Di Indonesia sudah umum lihat pejabat negara memakai jas komplit. Setelan jas, dasi, peniti bahkan vest (rompinya jas). Tetapi cocokkah pakaian dengan kerah yang mencekik leher itu dipakai di daerah sepanas Indonesia? Padahal tidak sedikit pejabat-pejabat di negara berkembang yang mempertahankan pakaian nasionalnya. Rajiv Gandhi, Deng Xiaoping, Raja Faisal bahkan tidak sedikit kepala negara asal Afrika yang masih bertelanjang kaki. Demi kesadaran,bahwa tidak semua produk dalam negeri kalah bonafide dengan produk “barat”. Ingatlah Mahatma Gandhi dengan kefanatikan luar biasa memimpin gerakan swadesi.
Berdasi artinya kita kemudian harus mengikuti perkembangan mode dari Paris. Sepatu artinya Adidas, Puma, Nike dan lainnya. Bahan dari setelan jas terbaik bukanlah buatan lokal, tetapi batik terbaik buatan Indonesia. Kain tenun Sumba hanya ada di Sumba. Demikianlah pula halnya dengan lurik, selop Yogya, pakaian kurung dan sebagainya. Lantas kenapa tidak merasa bangga dengan lurik? Kenapa malah beli sepatu buatan Itali? Itali semakin kaya sedangkan pengrajin lurik semakin kere. Apa ini ada hubungannya dengan penanaman modal asing. Saya kesulitan menafsirkannya.
Yang jelas keharusan berbusana sudah begitu melembaga. Kalau tidak pakai “ini” anda “berdosa”. Bila yang berwenang pakai “ini”, semua harus pakai “ini”. Mungkin kondisinya bisa berbalik, cuma kesewenangan selalu menyesakkan. Dari Jakarta kita sudah di TAP MPR kan tentang banyaknya kesesakan. Dari pemerintah daerah juga keluar segudang aturan yang menjengkelkan. Kenapa di Satya Wacana masih ada oknum-oknum yang menambah beban di atas punggung dan sudah mulai rubuh ini? Karena itu saya pilih sandal sebagai simbol pemberontakan terhadap kemapanan sepihak ini.
Simbol itu menjadi semakin perlu karena ada “kebiasaan” di dalamnya. Cory Aquino punya seragam kuning karena cerita tentang “The Yellow Ribbon” banyak dikenal rakyat Filipina. Cory memilih Laban dengan ibu jari dan telunjuk karena Laban lebih “dekat” dibanding victory (telunjuk dan jari tengah). Seharusnya kita memilih sandal (jepit) untuk simbol ketidaksetujuan kita terhadap kemapanan sepihak ini. Simbol karena kita diperlakukan tidak adil. Simbol karena banyak bakul jamu, tukang becak, pedagang kaki lima, buruh tani, kuli bangunan dan rakyat kecil lainnya cuma bisa membeli sandal jepit, dan kita harus tetap prihatin terhadap nasib mereka. Sandal jepit identik dengan keengganan rakyat kecil terhadap bikrokrasi yang selalu membuat mereka susah. Sandal bisa menjadi segalanya di Fakultas kita, di dalam ketidak netralannya itu. Dan itu perlu!
* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Kristen Satya Wacana
Tetapi akhir-akhir ini saya lihat kita telah mulai berubah. Dulu anak Elektro banyak yang bersandal jepit di rapat, di kuliah, di asistensi atau acara lainnya. Sekarang, entah karan yang lagi “berkuasa” orang bersepatu, kebebasan itu semakin terbatas, sehingga timbullah kasus-kasus seperti di atas yang seharusnya masih bisa diperpanjang dengan contoh-contoh lain.
Bersepatu boleh-boleh saja asal jangan kemudian memaksa orang lain untuk turut bersepatu. Ini sudah bukan masalah “tahu aturan” atau tidak tapi sudah menjadi pemaksaan. Ikut seminar yang diadakan mahasiswa pekan ilmiah-ilmiahan harus bersepatu, masuk Biro Keuangan harus bersepatu. Sehingga saya benar-benar ketakutan kalau suatu hari aturan ini diperpanjang menjadi bersepatu dan berpakaian rapi (kaos boleh asal berkerah) seperti yang sudah berlaku di Universitas Kristen Petra Surabaya. Dan akan lebih mengecewakan kalau kemudian aturan yang menyesakkan itu dipaksakan tanpa tanda kurung. Pakaian rapi non kaos. Apakah kaos itu bukan termasuk pakaian yang rapi? Dan akan lebih menjengkelkan lagi bila kemudian ada aturan baru, baik tertulis maupun tidak, bahwa mahasiswi tidak boleh ikut kuliah memakai celana panjang, yang belakangan sudah menjadi umum berlaku di setiap perguruan tinggi negeri yang pernah saya kunjungi.
Kalau aturan-aturan yang menunjang birokrasi itu diteruskan, saya sangsi orang desa yang belum bisa bersepatu misalnya, beranikah mereka mengadukan nasib buruknya ke DPR? Beranikah tukang kebun yang tak punya seragam KORPRI masuk kantor dekan? Beranikah mahasiswa yang kebetulan urusannya sangat mendesak untuk masuk kantor Rektor? Semua bisa jadi semrawut kalau hal yang sepele ini diberlalukan secara ketat. Lembaga diciptakan untuk mengumpulkan kekuatan bersama dalam hal melawan hambatan-hambatan. Nah! Kalau suatu saat lembaga itu terlalu berat (over load) dengan segala aturan main, birokrasi dan rutinitas sehingga biaya untuk membayarnya menjadi terlalu mahal. Apa tidak seharusnya diadakan penyegaran kembali di lembaga itu. Atau kalau hal itu sudah tidak memungkinkan, lebih baik lembaga yang justru menghambat pencapaian tujuan itu dihancurkan saja. Dan untuk menghancurkan diperlukan lembaga tandingan yang umum disebut organisasi bawah tanah atau gerakan subversif.
Alasan lain yang bisa kita cari dari asal-usul sandal. Kebudayaan kita, katakanlah kebudayaan Jawa, tidak mengenal sepatu. Sepatu itu sendiri menyentuh kebudayaan Jawa bersamaan dengan datangnya penjajah Belanda. Di negara asalnya sepatu benar-benar dibutuhkan oleh orang Belanda. Bukan hanya sebagai alas kaki tetapi juga untuk melindungi kaki dari cuaca yang kelewat dingin, sehingga untuk menyambungnya diciptakan kaos kaki agar seluruh kakinya menjadi hangat.
Tetapi kita yang hidup di alam tropika ini seharusnya tidak begitu memerlukan sepatu. Alam kita cukup hangat. Dan kalaupun memerlukan alas kaki yang bisa dipakai untuk berlari, di Jawa ada semacam sepatu sandal untuk itu, di Minangkabau juga sepatu sandal. Sedangkan di acara-acara resmi, katakanlah di kerajaan Mataram, para kawulanya boleh bertelanjang kaki. Raja juga bertelanjang kaki atau boleh juga memakai selop (selop itu mungkin juga setelah pengaruh Belanda), tetapi seselop-selopnyapun masih bukan sepatu.
Lantas kalau Ariel Heryanto pernah menulis, “Ganasnya bahasa ganasnya politik,” dengan sebagian intinya, bahasa tidak netral. Saya juga bisa bilang, bahwa sepatu tidak netral (tentunya sandal jiga tidak), selalu ada konteks di belakang sepatu. Seperti judul buku Marshall MacLuhan, “Medium is the message”, tidak ada alat yang benar-benar netral. Teknologi, militer, bahasa, ilmu pengetahuan, seni apalagi politik, semuanya tidak netral.
Di Indonesia sudah umum lihat pejabat negara memakai jas komplit. Setelan jas, dasi, peniti bahkan vest (rompinya jas). Tetapi cocokkah pakaian dengan kerah yang mencekik leher itu dipakai di daerah sepanas Indonesia? Padahal tidak sedikit pejabat-pejabat di negara berkembang yang mempertahankan pakaian nasionalnya. Rajiv Gandhi, Deng Xiaoping, Raja Faisal bahkan tidak sedikit kepala negara asal Afrika yang masih bertelanjang kaki. Demi kesadaran,bahwa tidak semua produk dalam negeri kalah bonafide dengan produk “barat”. Ingatlah Mahatma Gandhi dengan kefanatikan luar biasa memimpin gerakan swadesi.
Berdasi artinya kita kemudian harus mengikuti perkembangan mode dari Paris. Sepatu artinya Adidas, Puma, Nike dan lainnya. Bahan dari setelan jas terbaik bukanlah buatan lokal, tetapi batik terbaik buatan Indonesia. Kain tenun Sumba hanya ada di Sumba. Demikianlah pula halnya dengan lurik, selop Yogya, pakaian kurung dan sebagainya. Lantas kenapa tidak merasa bangga dengan lurik? Kenapa malah beli sepatu buatan Itali? Itali semakin kaya sedangkan pengrajin lurik semakin kere. Apa ini ada hubungannya dengan penanaman modal asing. Saya kesulitan menafsirkannya.
Yang jelas keharusan berbusana sudah begitu melembaga. Kalau tidak pakai “ini” anda “berdosa”. Bila yang berwenang pakai “ini”, semua harus pakai “ini”. Mungkin kondisinya bisa berbalik, cuma kesewenangan selalu menyesakkan. Dari Jakarta kita sudah di TAP MPR kan tentang banyaknya kesesakan. Dari pemerintah daerah juga keluar segudang aturan yang menjengkelkan. Kenapa di Satya Wacana masih ada oknum-oknum yang menambah beban di atas punggung dan sudah mulai rubuh ini? Karena itu saya pilih sandal sebagai simbol pemberontakan terhadap kemapanan sepihak ini.
Simbol itu menjadi semakin perlu karena ada “kebiasaan” di dalamnya. Cory Aquino punya seragam kuning karena cerita tentang “The Yellow Ribbon” banyak dikenal rakyat Filipina. Cory memilih Laban dengan ibu jari dan telunjuk karena Laban lebih “dekat” dibanding victory (telunjuk dan jari tengah). Seharusnya kita memilih sandal (jepit) untuk simbol ketidaksetujuan kita terhadap kemapanan sepihak ini. Simbol karena kita diperlakukan tidak adil. Simbol karena banyak bakul jamu, tukang becak, pedagang kaki lima, buruh tani, kuli bangunan dan rakyat kecil lainnya cuma bisa membeli sandal jepit, dan kita harus tetap prihatin terhadap nasib mereka. Sandal jepit identik dengan keengganan rakyat kecil terhadap bikrokrasi yang selalu membuat mereka susah. Sandal bisa menjadi segalanya di Fakultas kita, di dalam ketidak netralannya itu. Dan itu perlu!
* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Kristen Satya Wacana
Silabus Kursus Jurnalisme Sastrawi XIV
Jakarta, 10–21 Desember 2007
Hari ini hampir tak ada warga yang mendapatkan breaking news dari suratkabar. Mereka mendapatkannya dari televisi, radio, SMS, telepon atau internet. Tantangan baru muncul: bagaimana suratkabar bertahan bila mereka tak bisa mengandalkan kecepatan?
Tawaran ini di New York dijawab Tom Wolfe pada 1973. Wolfe mengenalkan sebuah genre baru saat itu: New Journalism. Ia mengawinkan disiplin keras dalam jurnalisme dengan daya pikat sastra. Ibarat novel tapi faktual. Genre ini mensyaratkan liputan dalam, namun memikat. Genre ini kemudian dikenal dengan nama narative reporting atau literary journalism. Menurut Nieman Reports, sejak 1980an, suratkabar-suratkabar di Amerika banyak memakai elemennya ketika kecepatan televisi memaksa tampil dengan laporan mendalam.
Di Jakarta, genre ini diperkenalkan lewat sebuah kursus pada Juli 2001. Mula-mula hanya dua kali namun permintaan tetap datang. Angkatan-angkatan baru pun dibuat setiap satu semester. Peserta datang dari berbagai kota, dari Banda Aceh hingga Jayapura, dari Pontianak hingga Kuching, dari Ende hingga Kupang (Angkatan XIII diadakan di Banda Aceh). Alumninya, kini mulai bermunculan. Ada yang menulis buku. Ada yang jadi pemimpin redaksi. Ada yang sekolah lanjut.
Kursus ini dibuat dua minggu, berseling satu hari sesi di kelas, satu hari tugas membaca dan menulis di rumah. Peserta adalah orang yang biasa menulis untuk media. Setidaknya berpengalaman sekitar lima tahun.
Peserta maksimal 16 orang agar pengampu punya perhatian memadai buat semua peserta. Calon peserta diharapkan mengirim biodata dan contoh tulisan agar pengampu mengetahui kemampuan dasar peserta lebih awal.
Biaya pendaftaran Rp 3 juta. Biaya tersebut sudah termasuk buku dan materi kursus non buku sekitar 200 halaman serta coffe break dan makan siang. Pilihan menu makan siang cukup mengundang pujian! Kali ini akan dicoba masakan Thailand: thom yam gong, pad thai dan lainnya. Namun juga bakal coba makanan Itali: spaghetti carbonara, ravioli isi ikan, pasta plus terung bakar dalam lasagna. Menu nasi bungkus pisang ala Sunda, tak ketinggalan. Juga sayur asem, ikan asin, empal manis ala Jawa.
INSTRUKTUR
Janet Steele -- Profesor dari George Washington University, spesialisasi sejarah media, mengajar mata kuliah narrative journalism. Menulis buku The Sun Shines for All: Journalism and Ideology in the Life of Charles A. Dana dan Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia, yang ahlibahahaskan oleh Arif Zulkifli dan diterbitkan oleh P.T. Dian Rakyat tahun 2007. Juga menulis tentang jurnalisme di Timor Leste dan Malaysia.
Andreas Harsono -- Wartawan feature service Pantau, anggota International Consortium of Investigative Journalists, mendapatkan Nieman Fellowship di Universitas Harvard. Menyunting buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat. Kini menyelesaikan buku From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism, membahas hubungan media dengan kekerasan etnik, agama dan nasionalisme di Indonesia dan Timor Lorosae.
Remy Sylado – Guest speaker, pengarang Minahasa, kelahiran Makassar, mendapat penghargaan Khatulistiwa Award untuk novel Kerudung Merah Kirmizi, biasa menulis fiksi, sesi ini khusus diadakan di rumah Sylado di Bogor, pinggir hutan, acara santai, diskusi soal suka duka seorang penulis.
SILABUS
MINGGU PERTAMA oleh Andreas Harsono
Senin, 10 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 -- Pembukaan: perkenalan, membicarakan silabus dan membagi tugas. Diskusi tentang jurnalisme. Pedomannya, The Elements of Journalism karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. [Andreas Harsono]
Bacaan: Buku Sembilan Elemen Jurnalisme terjemahan karya Kovach dan Rosenstiel disediakan dalam paket. Ada resensinya oleh Andreas Harsono. “Media Bias in Covering the Tsunami in Aceh” karya Andreas Harsono.
Senin, 10 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 – Diskusi soal jurnalisme sastrawi, membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, tujuh pertimbangan dalam genre ini.
Bacaan: “Kegusaran Tom Wolfe” oleh Septiawan Santana Kurnia; “Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita” oleh Andreas Harsono dalam buku Jurnalisme Sastrawi; laporan-laporan dalam Nieman Narrative Journalism Conference.
Tugas untuk hari Rabu: Perhatikan sesuatu di lingkungan Anda. Bikin deskripsi dengan padat. Manfaatkan penciuman, pendengaran, warna, gerakan, kasar-halus, kontras (lucu, aneh, menarik) dan sebagainya. Hindarkan klise macam “nyiur melambai” atau “angin sepoi-sepoi.” Bikin deskripsi yang akan merampas perhatian pembaca! Maksimal satu halaman. Bacalah ”Reporting in the key to good journalism” oleh Steven A. Holmes.
Rabu, 12 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 – Diskusi lanjutan soal jurnalisme dan masalahnya dengan nasionalisme-agama-etnik-ideologi-gender. Contoh-contoh dari Indonesia. Membaca tugas deskripsi dari hari Senin.
Bacaan tambahan: “The Ethnic Origins of Religious Conflict in North Maluku Province, 1999-2000” oleh Chris Wilson; “Indonesia’s Unknown War and the Lineages of Violence in West Kalimantan” oleh Jamie S. Davidson dan Douglas Kammen; "Fire Without Smoke and other phantoms of Ambon's violence" oleh Patricia Spyer.
Rabu, 12 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 – Diskusi struktur narasi dengan contoh “Hiroshima” karya John Hersey.
Bacaan: “Hiroshima” oleh John Hersey; “Menyusuri Jejak John ‘Hiroshima’ Hersey” oleh Bimo Nugroho.
Tugas untuk hari Jumat: Carilah seseorang yang menarik serta wawancarailah dia. Gunakan wawancara itu guna membuat deskripsi dan dialog. Pilih kalimat-kalimat yang bernas, memikat, indah, kuat serta menyentak. Maksimal satu halaman. Pikirkan dampak dari setiap kalimat dalam mengikat emosi pembaca.
Jumat, 14 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 – Satu isu namun muncul dalam empat pendekatan. Isunya Aceh. Munculnya, empat naskah, empat gaya, empat struktur. Juga akan mendiskusikan pekerjaan rumah.
Bacaan: “Orang-orang di Tiro” karya Linda Christanty; “Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan” karya Alfian Hamzah; “Republik Indonesia Kilometer Nol” karya Andreas Harsono; “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” karya Chik Rini.
Jumat, 14 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi tentang sumber anonim dan teknik interview. Juga menonton film ”Untuk Kaum Muda” karya Erfan Agus Setiawan tentang majalah Aktuil. Remy Sylado ikut jadi wartawan Aktuil.
Bacaan: “Tujuh Kriteria Sumber Anonim”; “Ten Tips for Better Interviews;” “Interviewing Sources” oleh Isabel Wilkerson.
GUEST SPEAKER Remy Sylado
Sabtu, 15 Desember 2007 pukul 10:00-13:00 -- Berangkat pukul 9:00 dari kantor Pantau. Naik bus dari kantor Kebayoran Lama. Sekitar 90 menit mencapai Bogor. Mendiskusikan pengalaman menulis. Makan siang di rumah Remy Sylado juga. Remy mengarang lebih dari selusin buku. Pilihlah salah satu dan bacalah. Ini membantu memahami karya Remy.
MINGGU KEDUA oleh Janet Steele
(Steele tiba dari Washington hari Senin pagi, 17 Desember 2007, butuh istirahat dulu)
Selasa, 18 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 – Diskusi sekali lagi tentang kemungkinan jurnalisme sastrawi untuk keperluan suratkabar, lebih praktis, serta sejarah dan perbedaan antara "new," “literary" dan "narrative" journalism.
Bacaan: “The Girl of the Year” oleh Tom Wolfe; “Dua Jam Bersama Hasan Tiro” oleh Arif Zulkifli; “A Boy Who Was Like a Flower” oleh Anthony Shadid, “For Now, Indonesian Fishermen Are Forced to Abandon the Sea Officials Must Move Quickly to Revive Industry, Advocates Say” oleh Ellen Nakashima, “Soldiers Face Neglect, Frustration At Army’s Top Medical Facility” oleh Dana Priest dan Anne Hull, “Violence Change Fortunes Of Storied Baghdad Street” oleh Sudarsan Raghavan.
Selasa, 18 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi lanjutan tentang definisi jurnalisme sastrawi, dari Tom Wolfe hingga Mark Kramer, dan pengaruhnya pada perkembangan suratkabar mainstream di Amerika Serikat.
Tugas untuk hari Rabu: Menulis tentang sebuah peristiwa yang disaksikan. Mulai dengan adegan, tanpa "penjelasan." bersadarkan karya Tom Wolfe "The Girl of the Year." Topiknya bisa apa saja tapi yang bisa memikat pembaca untuk membaca narasi itu. Mohon tak membuat lebih panjang dari dua halaman, dua spasi agar semua peserta bisa mendapat bagian membacakan karyanya.
Rabu, 19 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 -- Diskusi tentang pekerjaan rumah.
Bacaan: “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” oleh Chik Rini; sebagian dari buku “In Cold Blood” karya Truman Capote dan kliping dari harian The New York Times pada 1959 “Wealthy Family, 3 of Family Slain.”
Rabu, 19 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi tentang immersion reporting berdasarkan karya Truman Capote “In Cold Blood” serta membandingkannya dengan “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft.”
Tugas untuk hari Jumat: Tulislah sebuah narasi dengan gaya orang pertama (“saya” atau “aku” atau “abdi” atau “gua” atau lainnya) untuk menggambarkan sebuah adegan. Gunakan model “Buru, Menziarahi Negeri penghabisan” oleh Amarzan Loebis, dimana Amarzan memasukkan dirinya dalam laporannya. Bahan ini akan dibacakan di depan kelas. Panjang maksimal dua halaman, dua spasi.
Jumat, 21 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 -- Diskusi tentang pekerjaan rumah yang dibuat berdasarkan “Buru, Menziarahi Negeri penghabisan” serta persoalan kata “saya.”
Bacaan: “Tikungan Terakhir” (laporan kematian wartawan Rudi Singgih) oleh Agus Sopian; “It’s an Honor” oleh Jimmy Breslin, “Buru, Menziarahi Negeri penghabisan” oleh Amarzan Loebis.
Jumat, 21 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi tentang persoalan struktur narasi, dan bagaimana memanfaatkan narasi dalam berita hangat (breaking news) dengan contoh “Tikungan Terakhir” oleh Agus Sopian dan “It’s an Honor” oleh Jimmy Breslin. Penutupan serta tanya jawab dan penyerahan sertifikat.
***
Hari ini hampir tak ada warga yang mendapatkan breaking news dari suratkabar. Mereka mendapatkannya dari televisi, radio, SMS, telepon atau internet. Tantangan baru muncul: bagaimana suratkabar bertahan bila mereka tak bisa mengandalkan kecepatan?
Tawaran ini di New York dijawab Tom Wolfe pada 1973. Wolfe mengenalkan sebuah genre baru saat itu: New Journalism. Ia mengawinkan disiplin keras dalam jurnalisme dengan daya pikat sastra. Ibarat novel tapi faktual. Genre ini mensyaratkan liputan dalam, namun memikat. Genre ini kemudian dikenal dengan nama narative reporting atau literary journalism. Menurut Nieman Reports, sejak 1980an, suratkabar-suratkabar di Amerika banyak memakai elemennya ketika kecepatan televisi memaksa tampil dengan laporan mendalam.
Di Jakarta, genre ini diperkenalkan lewat sebuah kursus pada Juli 2001. Mula-mula hanya dua kali namun permintaan tetap datang. Angkatan-angkatan baru pun dibuat setiap satu semester. Peserta datang dari berbagai kota, dari Banda Aceh hingga Jayapura, dari Pontianak hingga Kuching, dari Ende hingga Kupang (Angkatan XIII diadakan di Banda Aceh). Alumninya, kini mulai bermunculan. Ada yang menulis buku. Ada yang jadi pemimpin redaksi. Ada yang sekolah lanjut.
Kursus ini dibuat dua minggu, berseling satu hari sesi di kelas, satu hari tugas membaca dan menulis di rumah. Peserta adalah orang yang biasa menulis untuk media. Setidaknya berpengalaman sekitar lima tahun.
Peserta maksimal 16 orang agar pengampu punya perhatian memadai buat semua peserta. Calon peserta diharapkan mengirim biodata dan contoh tulisan agar pengampu mengetahui kemampuan dasar peserta lebih awal.
Biaya pendaftaran Rp 3 juta. Biaya tersebut sudah termasuk buku dan materi kursus non buku sekitar 200 halaman serta coffe break dan makan siang. Pilihan menu makan siang cukup mengundang pujian! Kali ini akan dicoba masakan Thailand: thom yam gong, pad thai dan lainnya. Namun juga bakal coba makanan Itali: spaghetti carbonara, ravioli isi ikan, pasta plus terung bakar dalam lasagna. Menu nasi bungkus pisang ala Sunda, tak ketinggalan. Juga sayur asem, ikan asin, empal manis ala Jawa.
INSTRUKTUR
Janet Steele -- Profesor dari George Washington University, spesialisasi sejarah media, mengajar mata kuliah narrative journalism. Menulis buku The Sun Shines for All: Journalism and Ideology in the Life of Charles A. Dana dan Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia, yang ahlibahahaskan oleh Arif Zulkifli dan diterbitkan oleh P.T. Dian Rakyat tahun 2007. Juga menulis tentang jurnalisme di Timor Leste dan Malaysia.
Andreas Harsono -- Wartawan feature service Pantau, anggota International Consortium of Investigative Journalists, mendapatkan Nieman Fellowship di Universitas Harvard. Menyunting buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat. Kini menyelesaikan buku From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism, membahas hubungan media dengan kekerasan etnik, agama dan nasionalisme di Indonesia dan Timor Lorosae.
Remy Sylado – Guest speaker, pengarang Minahasa, kelahiran Makassar, mendapat penghargaan Khatulistiwa Award untuk novel Kerudung Merah Kirmizi, biasa menulis fiksi, sesi ini khusus diadakan di rumah Sylado di Bogor, pinggir hutan, acara santai, diskusi soal suka duka seorang penulis.
SILABUS
MINGGU PERTAMA oleh Andreas Harsono
Senin, 10 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 -- Pembukaan: perkenalan, membicarakan silabus dan membagi tugas. Diskusi tentang jurnalisme. Pedomannya, The Elements of Journalism karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. [Andreas Harsono]
Bacaan: Buku Sembilan Elemen Jurnalisme terjemahan karya Kovach dan Rosenstiel disediakan dalam paket. Ada resensinya oleh Andreas Harsono. “Media Bias in Covering the Tsunami in Aceh” karya Andreas Harsono.
Senin, 10 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 – Diskusi soal jurnalisme sastrawi, membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, tujuh pertimbangan dalam genre ini.
Bacaan: “Kegusaran Tom Wolfe” oleh Septiawan Santana Kurnia; “Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita” oleh Andreas Harsono dalam buku Jurnalisme Sastrawi; laporan-laporan dalam Nieman Narrative Journalism Conference.
Tugas untuk hari Rabu: Perhatikan sesuatu di lingkungan Anda. Bikin deskripsi dengan padat. Manfaatkan penciuman, pendengaran, warna, gerakan, kasar-halus, kontras (lucu, aneh, menarik) dan sebagainya. Hindarkan klise macam “nyiur melambai” atau “angin sepoi-sepoi.” Bikin deskripsi yang akan merampas perhatian pembaca! Maksimal satu halaman. Bacalah ”Reporting in the key to good journalism” oleh Steven A. Holmes.
Rabu, 12 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 – Diskusi lanjutan soal jurnalisme dan masalahnya dengan nasionalisme-agama-etnik-ideologi-gender. Contoh-contoh dari Indonesia. Membaca tugas deskripsi dari hari Senin.
Bacaan tambahan: “The Ethnic Origins of Religious Conflict in North Maluku Province, 1999-2000” oleh Chris Wilson; “Indonesia’s Unknown War and the Lineages of Violence in West Kalimantan” oleh Jamie S. Davidson dan Douglas Kammen; "Fire Without Smoke and other phantoms of Ambon's violence" oleh Patricia Spyer.
Rabu, 12 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 – Diskusi struktur narasi dengan contoh “Hiroshima” karya John Hersey.
Bacaan: “Hiroshima” oleh John Hersey; “Menyusuri Jejak John ‘Hiroshima’ Hersey” oleh Bimo Nugroho.
Tugas untuk hari Jumat: Carilah seseorang yang menarik serta wawancarailah dia. Gunakan wawancara itu guna membuat deskripsi dan dialog. Pilih kalimat-kalimat yang bernas, memikat, indah, kuat serta menyentak. Maksimal satu halaman. Pikirkan dampak dari setiap kalimat dalam mengikat emosi pembaca.
Jumat, 14 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 – Satu isu namun muncul dalam empat pendekatan. Isunya Aceh. Munculnya, empat naskah, empat gaya, empat struktur. Juga akan mendiskusikan pekerjaan rumah.
Bacaan: “Orang-orang di Tiro” karya Linda Christanty; “Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan” karya Alfian Hamzah; “Republik Indonesia Kilometer Nol” karya Andreas Harsono; “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” karya Chik Rini.
Jumat, 14 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi tentang sumber anonim dan teknik interview. Juga menonton film ”Untuk Kaum Muda” karya Erfan Agus Setiawan tentang majalah Aktuil. Remy Sylado ikut jadi wartawan Aktuil.
Bacaan: “Tujuh Kriteria Sumber Anonim”; “Ten Tips for Better Interviews;” “Interviewing Sources” oleh Isabel Wilkerson.
GUEST SPEAKER Remy Sylado
Sabtu, 15 Desember 2007 pukul 10:00-13:00 -- Berangkat pukul 9:00 dari kantor Pantau. Naik bus dari kantor Kebayoran Lama. Sekitar 90 menit mencapai Bogor. Mendiskusikan pengalaman menulis. Makan siang di rumah Remy Sylado juga. Remy mengarang lebih dari selusin buku. Pilihlah salah satu dan bacalah. Ini membantu memahami karya Remy.
MINGGU KEDUA oleh Janet Steele
(Steele tiba dari Washington hari Senin pagi, 17 Desember 2007, butuh istirahat dulu)
Selasa, 18 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 – Diskusi sekali lagi tentang kemungkinan jurnalisme sastrawi untuk keperluan suratkabar, lebih praktis, serta sejarah dan perbedaan antara "new," “literary" dan "narrative" journalism.
Bacaan: “The Girl of the Year” oleh Tom Wolfe; “Dua Jam Bersama Hasan Tiro” oleh Arif Zulkifli; “A Boy Who Was Like a Flower” oleh Anthony Shadid, “For Now, Indonesian Fishermen Are Forced to Abandon the Sea Officials Must Move Quickly to Revive Industry, Advocates Say” oleh Ellen Nakashima, “Soldiers Face Neglect, Frustration At Army’s Top Medical Facility” oleh Dana Priest dan Anne Hull, “Violence Change Fortunes Of Storied Baghdad Street” oleh Sudarsan Raghavan.
Selasa, 18 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi lanjutan tentang definisi jurnalisme sastrawi, dari Tom Wolfe hingga Mark Kramer, dan pengaruhnya pada perkembangan suratkabar mainstream di Amerika Serikat.
Tugas untuk hari Rabu: Menulis tentang sebuah peristiwa yang disaksikan. Mulai dengan adegan, tanpa "penjelasan." bersadarkan karya Tom Wolfe "The Girl of the Year." Topiknya bisa apa saja tapi yang bisa memikat pembaca untuk membaca narasi itu. Mohon tak membuat lebih panjang dari dua halaman, dua spasi agar semua peserta bisa mendapat bagian membacakan karyanya.
Rabu, 19 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 -- Diskusi tentang pekerjaan rumah.
Bacaan: “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” oleh Chik Rini; sebagian dari buku “In Cold Blood” karya Truman Capote dan kliping dari harian The New York Times pada 1959 “Wealthy Family, 3 of Family Slain.”
Rabu, 19 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi tentang immersion reporting berdasarkan karya Truman Capote “In Cold Blood” serta membandingkannya dengan “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft.”
Tugas untuk hari Jumat: Tulislah sebuah narasi dengan gaya orang pertama (“saya” atau “aku” atau “abdi” atau “gua” atau lainnya) untuk menggambarkan sebuah adegan. Gunakan model “Buru, Menziarahi Negeri penghabisan” oleh Amarzan Loebis, dimana Amarzan memasukkan dirinya dalam laporannya. Bahan ini akan dibacakan di depan kelas. Panjang maksimal dua halaman, dua spasi.
Jumat, 21 Desember 2007 pukul 10:00-12:00 -- Diskusi tentang pekerjaan rumah yang dibuat berdasarkan “Buru, Menziarahi Negeri penghabisan” serta persoalan kata “saya.”
Bacaan: “Tikungan Terakhir” (laporan kematian wartawan Rudi Singgih) oleh Agus Sopian; “It’s an Honor” oleh Jimmy Breslin, “Buru, Menziarahi Negeri penghabisan” oleh Amarzan Loebis.
Jumat, 21 Desember 2007 pukul 13:00-15:00 -- Diskusi tentang persoalan struktur narasi, dan bagaimana memanfaatkan narasi dalam berita hangat (breaking news) dengan contoh “Tikungan Terakhir” oleh Agus Sopian dan “It’s an Honor” oleh Jimmy Breslin. Penutupan serta tanya jawab dan penyerahan sertifikat.
***
Thursday, October 25, 2007
Quo vadis jurnalisme Islami?
Dear Rudi Agung,
Terima kasih untuk Comment dalam blog saya. Anda mengatakan tertarik pada "jurnalisme Islam" --mungkin frasa yang lebih bisa dibenarkan secara linguistik adalah "jurnalisme Islami"-- dan mengacu pada Hamid Mowlana serta Majid Tehranian.
Saya kurang kenal dengan pikiran Mowlana namun pernah baca karya Tehranian. Tehranian kini jadi profesor international communication di University of Hawaii serta direktur Toda Institute for Global Peace and Policy Research. Dia juga pernah mengajar di Harvard. Hamid Mowlana, sama-sama etnik Persia atau Iran, kini profesor International Communication Program di American University, Washington DC.
Kalau bacaan saya tidak salah, Tehranian tidak bicara soal "jurnalisme Islami." Risetnya, lebih fokus pada masalah politik ekonomi internasional, komunikasi dan demokrasi. Areanya, Timur Tengah dan Asia Pacific.
Saya sendiri berpendapat tidak ada "jurnalisme Islami, atau setara dengan itu, juga tidak ada, "jurnalisme Kristiani," atau "jurnalisme Buddhist" atau kata sifat lainnya: Hindu, Yahudi, Sunda Wiwidan, Parmalin, Kaharingan, Khong Hu Chu dan masih banyak lagi. Ini belum lagi kalau kita mau bicara sekte atau aliran dalam suatu agama. Artinya, kita juga akan bicara soal "jurnalisme Protestan" atau "jurnalisme Katolik" maupun Shiah, Sunni dan seterusnya.
Agama dan jurnalisme berdiri pada ranah yang berbeda. Jurnalisme melayani publik dengan informasi yang benar agar mereka bisa mengatur dirinya sendiri dengan baik. Agama adalah seperangkat nilai untuk mengatur kehidupan seseorang maupun kehidupan bersama-sama dalam masyarakat. Ada unsur keimanan dalam agama. Jurnalisme hanya berdiri pada ranah fakta. Esensi jurnalisme adalah verifikasi. Esensi agama adalah iman. Saya kira agak janggal kalau dua ranah yang berbeda ini dijadikan dalam satu frasa.
Kalau demikian bagaimana menerangkan Al Jazeera? Apakah Reuters, Associated Press, Agence France Presse, CNN bukan media Kristen?
Disini kita bicara soal dua isu. Pertama, kita bicara soal audiens dari media bersangkutan. Kedua, kita bicara soal perspektif dari para pengelola media tersebut. Setiap media, bahkan setiap penulis, kebanyakan bekerja dengan khayalan tentang suatu audiens, yang mereka layani. Kebanyakan media di Jawa, tentu saja, berpikir dengan memasukkan unsur warga Muslim dalam khayalan tentang audiens itu. Di Kupang atau Jayapura, audiensnya dikhayalkan sebagai orang Kristen. Associated Press bikin laporan dengan khayalan soal audiens yang isinya warga Amerika, bisa bicara bahasa Inggris, pendidikan sekuler dan seterusnya.
Kedua, banyak juga media didirikan dengan tujuan agar perspektif soal tertentu ikut mewarnai editorial mereka. Al Jazeera misalnya, didirikan dengan perspektif tentang keragaman dan kekayaan dalam Islam.
Ketika Al Jazeera hendak didirikan, kebetulan saya bertemu dengan seorang calon pemimpinnya, seorang mantan wartawan BBC, ketika dia hendak bertemu dengan guru saya, Bill Kovach di Cambridge. Kovach mengatakan sangat penting bagi dunia --bukan hanya warga Muslim-- untuk memiliki sebuah televisi internasional yang mengerti dan dekat dengan Islam.
Kovach bicara soal dua CNN. Ini sebuah stasiun televisi yang berpusat di Atlanta. Kovach pernah tinggal lama di Atlanta. Pertama adalah CNN yang khusus dipancarkan di Amerika Serikat. Satunya lagi disebut CNN International, yang dipancarkan ke seluruh dunia. CNN International, menurut Kovach, jauh lebih bermutu daripada "CNN Nasional."
CNN International punya khayalan tentang audiens yang lebih beragam daripada CNN Nasional. Al Jazeera, kalau Anda perhatikan, juga dikerjakan oleh wartawan-wartawan yang background agamanya macam-macam. Banyak orang Kristen bekerja di Al Jazeera. Namun juga banyak warga Muslim. BBC juga memperkerjakan wartawan dengan background berasal dari berbagai macam agama.
Keragaman dalam ruang redaksi adalah suatu kekayaan. Ini akan membuat ruang redaksi lebih mampu memahami situasi dunia, yang memang beragam. Makin beragam suatu ruang redaksi, secara agama, etnik, kewarganegaraan, orientasi seksual dan sebagainya, maka makin kaya pula ruang redaksi bersangkutan.
Perspektif, audiens dan keragaman inilah yang sering kurang dimengerti orang. Kalau agama dijadikan label baru untuk jurnalisme, saya kira, jurnalisme bakal membingungkan orang. Saya kok jadi ingin tahu siapa "pakar nasional" yang memberitahu Anda soal "jurnalisme Islam" itu. Terima kasih.
Related Stories
Jawaban Kedua untuk Rudi Agung
Tuesday, October 23, 2007
Remy Sylado Guest Speaker Kursus
Remy Sylado atau Japi Tambajong, seorang penulis etnik Minahasa, akan berbagi pengalaman menulis dalam kursus dua-minggu Jurnalisme Sastrawi pada Sabtu, 15 Desember 2007.
Pertemuan akan diadakan, secara santai, di rumah Tambajong, dekat sebuah hutan Bogor.
Tambajong kelahiran Makassar 1945. Ia menghabiskan masa kecil dan remaja di Semarang dan Solo.
Sebagai penulis, dia memiliki sejumlah nama samaran seperti Alif Danya Munsyi, Juliana C. Panda, Jubal Anak Perang Imanuel.
Ia memulai karier sebagai wartawan majalah Tempo (Semarang, 1965), redaktur majalah Aktuil Bandung (sejak 1970), dosen Akademi Sinematografi Bandung (sejak 1971), ketua Teater Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung.
Dia dianugerahi hadiah Sastra Khatulistiwa 2002 untuk novelnya Kerudung Merah Kirmizi. Beberapa buku karyanya, Ca Bau Kan, Kembang Jepun, Parijs van Java, Sam Po Kong serta 9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah Asing.
Pertemuan ini khusus untuk peserta kursus, namun kami membuka peluang lima orang alumni program pelatihan Pantau, yang ingin ikutan, untuk mendaftarkan diri. Harap maklum tempat dibatasi mengingat kapasitas bus serta kesempatan berdiskusi dengan leluasa bersama Remy Sylado di rumahnya.
Saturday, October 20, 2007
Saya dalam 15.840 Jam
Oleh SUADI SULAIMAN
Kisah anak muda yang bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, hampir menewaskan kawan sendiri, dan dituduh mengidap AIDS.
DI HUTAN, saat istirahat, kadang-kadang saya menulis catatan harian. Saya ingin mengabadikan banyak peristiwa penting selama perang. Suatu hari catatan ini mungkin berguna bagi anak cucu, pikir saya. Meskipun sebagian orang menganggap menulis catatan harian atau diary itu mirip perbuatan anak usia belasan dan biasanya berisi curahan hati tentang cinta muda-mudi, tetapi bagi saya fungsi catatan harian tidak seremeh itu dan lebih dari sekadar pembingkai perasaan.
Banyak pejuang terkenal menulis catatan harian. Ernesto ”Che” Guevara dari Kuba misalnya, menulis catatan harian sejak ia masih belum jadi pejuang. Catatan harian yang ia tulis saat melakukan perjalanan naik motor mengelilingi Amerika Selatan membuat orang mengerti kontradiksi yang dialaminya sebagai calon dokter muda yang berurusan dengan pasien penyakit lepra sampai memilih bergerilya dan memimpin revolusi Kuba.
Saya pun teringat kisah perjalanan Nestor Paz pejuang Neoponte. Ia gerilyawan Bolivia yang melawan penindasan dan kekejian Amerika Serikat terhadap negerinya. Paz bergabung dengan Bolivias National Liberation Army dan mati kelaparan akibat membela hak rakyatnya yang dirampas.
Paz seorang komunis. Namun, saya tidak peduli apa pun ideologinya. Kesungguhan Paz membela rakyatnya yang ditindas membuat saya mengaguminya. Sikap Paz mengilhami saya agar tak mudah menyerah dalam keadaan sesulit apa pun.
Seorang teman perempuan, orang Jawa, telah memberi saya buku Nestor Paz ketika saya dirawat di sebuah rumah sakit Jakarta. Buku itu sebenarnya untuk menghibur dan membantu saya mengatasi rasa bosan. Ternyata ia menunjukkan saya cara memahami perjuangan.
SAYA bukan orang terkenal dan bukan pejuang hebat seperti Guevara dan Paz. Nama saya, Suadi Sulaiman, putra kelahiran Laweueng. Nama desa kelahiran saya adalah desa Teungku Chiek Di Laweueng. Saya biasa disapa Adi Laweueng. Orang Aceh sering dinamai dengan tempat kelahirannya.
Laweung merupakan ibukota kecamatan Muara Tiga, salah satu kecamatan di kabupaten Pidie. Laweueng terletak di ujung paling barat Pidie yang berbatasan dengan lembah Seulawah, Aceh Besar. Jarak tempuh ke Laweueng sekitar dua jam berkendaraan dari kota Banda Aceh.
Saya lahir pada 20 Juni 1980 dari pasangan Sulaiman Abdur Rahman dan Nurjannah Bansu, anak keempat dari delapan bersaudara. Ayah saya nelayan, sedangkan ibu bekerja sebagai petani musiman. Keduanya asli Laweueng.
Abang, kakak, dan dua adik saya mengikuti jejak orang tua saya, menjadi nelayan dan petani musiman. Hanya saya sendiri yang memilih jalan berbeda.
Penampilan saya terbilang agak kusut. Brewokan, berkumis dan berjambang lebat. Saya juga tak terlalu pusing dengan pakaian. Saya juga tak fanatik pada warna tertentu. Asalkan nyaman dipakai dan apa pun coraknya, baju itu akan menjadi kesayangan saya.
Menekuni hidup ini kadang susah, kadang mudah. Itu kata orang-orang di sekeliling saya. Jalan hidup tiap orang pun berbeda dan tiap jalan selalu menyimpan risikonya sendiri. Dan betapa pun panjang, penuh batu, berliku, turun-naik permukaannya, mencapai ujung jalan itu adalah puncak kemenangan seseorang yang berjuang melaluinya. Dengan keyakinan inilah, saya terus berjalan.
PADA tahun 1999, saya bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Organisasi ini dianggap melawan negara Indonesia, karena GAM menuntut kemerdekaan Aceh. Barangsiapa yang teridentifikasi sebagai anggota GAM dan simpatisannya, ia akan menanggung risiko yang tak main-main. Ditangkap, disiksa, dipenjarakan, dibunuh, atau dihilangkan paksa. Risiko ini tak hanya dialami GAM, namun dialami oleh semua gerakan perlawanan di seluruh dunia.
Pertama kali saya mengetahui keberadaan GAM di Aceh ketika juru bicara Teuntara Neugara Atjeh (TNA) wilayah Peureulak, Teungku Ishak Daud, disidang di pengadilan negeri Banda Aceh dan Sabang pada tahun 1998 sampai 1999. Ishak Daud kemudian meninggal dunia dalam sebuah kontak senjata dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selain tentang dia, saya juga mendengar nama Ahmad Kandang, pemimpin GAM wilayah Pase, Aceh Utara. Namanya begitu terkenal, karena pasukan yang dipimpinnya sering bentrok dengan militer Indonesia. Masih pada masa itu, saya juga membaca pernyataan-pernyataan Teungku Ismail Syahputra. Ia juru bicara Acheh Sumatra Nation Liberation Front (ASNLF). Organisasi ini bermarkas di Swedia dan merupakan nama untuk GAM dalam memimpin perlawanan di pengasingan. Ia diculik aparat Indonesia tak lama setelah Jaffar Hamzah Siddiq, ketua International Forum Acheh (IFA), diculik dan dibunuh Satuan Gabungan Intelijen pada tahun 1999.
Sesungguhnya ketertarikan saya kepada politik atau khususnya GAM telah dimulai saat saya duduk di kelas dua sekolah menengah atas (SMA). Saya sempat membuat sebuah daftar isi masalah menyangkut keberadaan GAM di Aceh: apa itu GAM, dari mana GAM, ke mana GAM, siapa GAM, dan bagaimana GAM.
Saya bergabung dengan GAM tidak dilandasi dendam. Tak seorang pun anggota keluarga saya yang menjadi korban militer Indonesia di masa Daerah Operasi Militer atau DOM pada tahun 1989 sampai 1998.
Keputusan ini semata-mata didasari rasa kemanusiaan setelah mendengar dan menyaksikan orang-orang biasa menjadi korban perang, dan rasa memiliki Aceh sebagai bangsa Aceh.
Pembantaian terhadap Teungku Bantaqiah, putra dan para santrinya di Beutong Ateuh, Aceh Barat menambah kemarahan saya kepada Indonesia, begitu pula sederet kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang terjadi pasca DOM. Belum lagi penghinaan dan pemerkosaan yang dilakukan TNI terhadap perempuan-perempuan di Aceh, kaum ibu dan saudari kami, makin membakar hati.
Saya merasa martabat kami sebagai orang Aceh telah diinjak-injak atas nama kepentingan negara Indonesia. Dalam hati kecil saya tercetus bahwa Aceh ini milik ”kita” orang Aceh dan bukan milik ”mereka” orang Indonesia.
PADA tanggal 20 Mei 2003, di hari kedua Darurat Militer diberlakukan presiden Megawati Soekarno, pasukan pemerintah Indonesia menggempur Pulo Aceh atau di peta dinamai Pulau Breueh. Ketika itu saya tengah ditugaskan di sana. Pulau ini terletak di antara Pulau Weh dan ujung barat Pulau Sumatra atau Aceh.
Pasukan pemerintah melancarkan serangan dengan menggunakan dua pesawat Hawk buatan Inggris, sebuah F-16 buatan Amerika, 20 speed boat dan empat armada marinir dari Sabang. Sehari sebelumnya, bertepatan dengan pemberlakuan Darurat Militer di Aceh, mereka membombardir kawasan Cot Keu Eung, Aceh Besar.
Konfrontasi antara TNA dan TNI di Pulo Aceh dan Lambadeuk ini berlangsung selama 10 jam secara beruntun, sehingga memakan korban di kedua belah pihak. Tujuh di antara kami syahid kala itu.
Penggempuran tersebut menjadi tindak lanjut dari kegagalan proses perundingan pemerintah Indonesia dan GAM di Tokyo, Jepang, pada tanggal 17 Mei sampai 18 Mei 2003.
Masing-masing pihak bertahan pada pendiriannya. GAM bersikeras untuk merdeka. Pemerintah Indonesia hanya setuju memberi status otonomi khusus untuk Aceh. Dari Swedia, delegasi GAM dipimpin Malik Mahmud. Anehnya, utusan GAM dari Aceh yang dipimpin Teungku Sofyan Ibrahim Tiba ditolak izin berangkatnya ke Tokyo oleh pemerintah Indonesia dan mereka ditangkap polisi dari Kepolisian Daerah Aceh di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh. Mereka kemudian dijebloskan ke penjara. Para utusan yang berubah status jadi tahanan itu antara lain Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, Teungku Kamaruzzaman, Teungku Nashiruddin Ahmad, dan Amni Ahmad Marzuki.
Di Pulo Aceh ini saya bergabung dengan pasukan GAM yang dipimpin Muhammad Nasir Mahmud alias Polem, sekarang telah almarhum, dan Ijil Azhar alias Ayah Merin. Polem ketika itu bertindak sebagai bagian keuangan GAM wilayah Aceh Besar, sedangkan Ayah Merin sebagai panglima GAM Sabang, Pulau Weh.
Jumlah anggota pasukan kami mencapai ratusan orang yang siap tempur dan lengkap dengan peralatan perang. Jenis-jenis senjata yang kami pakai antara lain senapan laras panjang (SS-1, M-16 AI, AK-45, AK-47) dan bazoka.
Pada hari ke-47 Darurat Militer di Aceh, saya pindah ke Pidie atas persetujuan pemimpin saya.
Hari itu, Jumat 4 Juli 2003, saya yang ditemani abang sepupu mengendarai mobil Kijang dari Beurawe, Banda Aceh, tempat singgah sementara saya, menuju Beureunuen yang terletak di kabupaten Pidie.
Dalam perjalanan menuju Pidie, kami sempat terjaring sweeping di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pidie. Polisi-polisi melakukan operasi pemeriksaan kartu tanda penduduk atau KTP. Bagi mereka yang memiliki KTP Merah Putih akan selamat dan bagi yang tidak memilikinya, seperti saya, pasti akan dapat masalah besar. KTP Merah Putih adalah tanda kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang tak memilikinya dianggap GAM.
Nasib saya di ujung tanduk dan hanya faktor kebetulan yang menyelamatkan saya. Di antara polisi tersebut terdapat kawan sekelas saya waktu SMA. Ia menyatakan kepada polisi-polisi yang lain bahwa saya anggota keluarganya. Ia meyakinkan mereka bahwa saya baru tiba dari Jakarta, karena kuliah di sana. Pemeriksaan ini membuat perjalanan saya tertunda selama 15 menit.
Tepat pukul 14.25 saya tiba di Beureunuen. Beberapa kawan menjemput saya untuk dibawa ke markas TNA wilayah Pidie, yang dipimpin Teungku Sardjani Abdullah. Markas ini terletak di pegunungan Tiro.
Sardjani alumnus Tripoli atau sekarang dikenal sebagai Libya. Ia dididik kemiliteran di negeri Moammar Khadafi itu. Pertama kali ia bergerilya di belantara Pidie antara tahun 1989 sampai 1993 dengan beberapa kawannya sesama Tripoli. Sardjani sangat disiplin dan taat beragama. Ayahnya, Teungku Abdullah, salah satu ulama Pidie.
Pukul 18.17 saya tiba di markas panglima dan sekaligus menandai babak baru dalam pengalaman gerilya saya, yaitu berbasis di pegunungan. Berada di pegunungan juga terasa lebih aman. Di tempat ini saya menghabiskan waktu selama 15.840 jam atau 22 bulan.
Kehidupan kami di sini serba sederhana. Kami, para gerilyawan, membangun tenda plastik dan menjadikan jerami sebagai kasur tidur. Jumlah anggota pasukan kami tak tetap. Kadang-kadang, 12 orang. Kadang-kadang, sekitar seratus orang jika dalam keadaan darurat.
Namun, kami tak pernah kekurangan bahan makanan. Selain pasukan tempur, kami juga memiliki pasukan khusus untuk menyediakan logistik. Tugas mereka ya hanya mengurus dan mensuplai bahan makanan ke pasukan yang ada di pegunungan.
BAGI orang biasa yang tak memiliki latar belakang tempur seperti saya, berperang bukan hal mudah. Dalam film-film perang, kita menyaksikan prajurit mengangkat senjata dan menembakkannya dengan gerakan yang gagah, ringan, dan pasti. Kenyataannya tidaklah semulus itu, setidaknya untuk saya.
Saya harus ikut latihan menembak dan bongkar senjata. Baru latihan pun rasanya sudah setengah mati.
Selama latihan tersebut saya mengetahui hal-hal yang kelihatan sepele bagi saya yang awam ini, yang sebenarnya saat penting, misalnya posisi senjata saat penyerahannya kepada kawan sepasukan. Moncong senjata harus tegak ke atas.
Aturan tadi sebuah disiplin. Namun, alasan lain juga ada. Senjata hanyalah benda mati, tetapi di tangan manusia yang punya macam-macam masalah, kepentingan, dan emosi, ia akan berubah jadi pembunuh kejam. Pikiran manusia bisa berubah dalam hitungan detik. Bahkan penelitian ilmiah menyebutkan bahwa pikiran manusia kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Untuk mempersempit peluang terjadinya insiden saat sentimen pribadi muncul dalam pasukan, posisi senjata dengan laras ke atas adalah tepat.
Pertama kali belajar memegang senapan buatan Rusia AK-47, tangan saya gemetar. Sendi-sendi saya terasa lemas, karena senjata itu lumayan berat.
Selain masalah pegang-memegang senjata, bongkar senjata jadi hal terberat bagi saya. Keteledoran dalam melaksanakannya hampir mencelakakan kawan sepasukan saya.
Suatu hari, setelah saya melepaskan magazin dari induknya, saya tidak tahu kalau di dalamnya masih tersisa satu peluru. Sebagai bagian dari latihan, saya pun mengarahkan senjata ke salah satu tenda kawan dan menarik pelatuknya.
Tak disangka, peluru melesat keluar dan hanya terpaut tipis dengan telinga kawan saya! Telinga kawan saya seolah berasap! Saya benar-benar ketakutan. Sedikit lagi peluru itu akan meledakkan kepalanya. Alamak!
Keringat dingin terbit di pori-pori tubuh saya. Ini kesalahan fatal.
Tiap kesalahan memiliki sanksi, karena tiap keteledoran bisa membuat nyawa orang melayang. Komandan regu atau danru memberi saya hukuman. Tiap hari saya harus mencari kayu bakar untuk memenuhi gudang berukuran 4 x 3 meter persegi. Selain itu, saya tidak diperbolehkan memegang senjata apa pun selama dua bulan. Saya juga tidak boleh keluar lokasi pos kami.
Walaupun sunyi dan jauh dari peradaban, hidup di hutan lebih tenang ketimbang di kota. Udara masih segar, jauh dari polusi. Pancaran matahari pagi yang menguatkan tulang-tulang lebih mudah diserap tubuh. Kebisingan lalu-lintas tak terdengar. Kebisingan yang disebabkan suara rentetan senjatalah yang terdengar.
Di sela-sela waktu tanpa kontak senjata atau keadaan siaga, kami belajar tentang ideologi negara Aceh Merdeka, sejarah Aceh, dan agama Islam. Kami yang belajar saat itu berjumlah 27 orang. Para pengajar berasal dari Biro Penerangan GAM. Rata-rata gerilyawan lulusan Tripoli.
Kami memperoleh materi sejarah Aceh yang sebenarnya. Bukan sejarah Aceh versi Nugroho Notosusanto, sejarawan militer yang pernah menjadi menteri pendidikan di masa Suharto berkuasa. Dalam buku sejarah yang ditulis Notosusanto, seluruh daerah bersatu melawan dan mengusir kolonialisme Belanda untuk negara Indonesia, termasuk Aceh. Nama-nama pejuang Aceh, seperti Cut Nyak Dien atau Cut Mutiah, dijadikan nama-nama jalan di Jakarta dan mereka disahkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sejarah Aceh disederhanakan dengan mengabaikan fakta. Bagi orang Aceh, setelah penjajahan Belanda dan Jepang, mereka justru dijajah Indonesia.
Di sekolah hutan ini pula saya jadi lebih paham posisi Aceh di mata internasional dan mengapa GAM menuntut merdeka dari Indonesia. Kekayaan alam kami banyak, tetapi rakyat kami miskin.
Namun, dari 27 murid itu yang masih hidup sampai hari ini hanya dua orang, yaitu saya dan Teungku Umar Busu. Sisanya meninggal dalam perang.
BERGERILYA di hutan dan pegunungan ternyata mengubah cara berpikir saya dalam memperlakukan alam. Satwa langka dan hutan lindung harus dilestarikan. Ekosistem harus dijaga. Dulu pengetahuan ini hanya sebatas hapalan atau teori. Setelah tinggal di alam terbuka dan bersentuhan langsung dengan tumbuhan dan hewan liar di dalamnya, pemahaman tentang lingkungan jadi benar-benar mengakar. Film Tarzan yang dulu disiarkan televisi ternyata tidak sekadar kisah manusia kuat dan pemberani yang dibesarkan kera, tetapi mengajarkan kita mencintai alam. Tarzan merupakan sosok pencinta dan pembela lingkungan.
Alam bisa sangat ramah dan menyediakan banyak kebutuhan manusia. Tetapi bagaimana saat alam marah dan melenyapkan sekitar 200 ribu jiwa di Aceh? Pengalaman tersebut sungguh menyadarkan saya sekali lagi bahwa kekuatan manusia sama sekali tak sebanding dengan kekuatan alam. Jika alam mengamuk, tak akan ada tawaran kompromi atau damai sebagaimana manusia bertikai atau berkonflik.
Lima menit sebelum tsunami, di pagi Minggu tanggal 26 Desember 2004 itu, kami dibombardir oleh tiga batalyon infanteri TNI, yaitu YONIF 114/KOSTRAD, YONIF 472/MAKASAR dan YONIF RAIDER-400. Mereka menggunakan mortir jenis 88 milimeter dan senjata jenis roket 105. Jumlah mortir yang ditembakkan sebanyak 115.
Ketika tsunami datang, saya tengah berada di pegunungan Tiro, Pidie. Saya dan kawan-kawan memperoleh informasi dari pusat informasi bahwa terjadi pengeboman dan pasukan harus siaga. Tak seorang pun dari kami yang menyadari bahwa bencana dahsyat baru saja melanda Aceh. Sebelum itu terjadi gempa besar, yang saya perkirakan sekitar 6 sampai 7 skala Richter. Tetapi kawan-kawan saya mengatakan bahwa kekuatan gempa mencapai 8 skala Richter.
Kepanikan sempat terjadi, karena terputusnya jaringan komunikasi. Hanya satelit dan walkie talkie, atau biasa disebut HT, yang bisa berfungsi.
Akhirnya saya berinisiatif mendengar siaran radio dari Kantor Berita Radio 68 H dan Elshinta, keduanya radio Jakarta. Kedua radio nasional ini tengah menyiarkan berita tsunami di Aceh. Saya masih belum paham tentang tsunami dan malah menghubungi radio tersebut untuk mengabarkan soal pengeboman oleh tiga batalyon tadi. Beberapa jam setelah itu, kontak senjata kembali terjadi antara TNA dan TNI di pegunungan Luengputu, Bandar Baru, Pidie Jaya.
Dalam catatan saya, selama masa darurat pascatsunami, telah terjadi 113 kali kontak senjata antara TNA dan TNI. Korban di pihak TNA berjumlah tujuh orang, sedang di pihak TNI mencapai seratusan. Sedikitnya korban di pihak kami, karena pemimpin GAM di Swedia meminta pasukan GAM bersikap defensif, tidak membalas serangan. GAM harus melakukan gencatan senjata sepihak, mengingat Aceh baru saja mengalami bencana.
Penanganan korban bencana pun sulit dilakukan di tengah situasi konflik. Ketika mendengar perjanjian damai akan dilakukan GAM dan pemerintah Indonesia, saya dan kawan-kawan sangat gembira. Kabar ini saya terima saat masih berada di pegunungan Tiro dengan panglima kami, Teungku Sardjani Abdullah.
SEKITAR sebulan setengah sebelum Kesepakatan Helsinki ditandatangani, saya berangkat ke Medan untuk berobat atas izin panglima. Saya diduga terkena malaria tropica.
Saya ditemani ibu, menumpang bus ke Medan. Lagi-lagi, operasi KTP Merah Putih terjadi di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Kali ini saya tenang-tenang saja, karena sudah memilikinya.
Situasi di Medan ternyata tidak aman. Saya terbang ke Jakarta dan langsung menuju rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang terkenal dengan sebutan RSCM.
Saya dirawat selama 27 hari di sini. Di RSCM saya hampir jadi korban malpraktek. Saya divonis terinfeksi virus HIV-AIDS.
Saya katakan kepada dokter bahwa mustahil saya terkena HIV. Selama dua tahun saya tidak pernah ke kota dan sebelum itu saya tak pernah melakukan hal-hal yang memungkinkan virus tersebut bersarang di tubuh saya. Lebih lengkap lagi saya sebutkan bahwa dari Medan saya langsung ke Jakarta, tidak mampir ke mana-mana dan langsung ke RSCM.
Para dokter yang menangani saya tetap ngotot bahwa saya terinfeksi HIV. Perdebatan serius pun terjadi. Di hari kelima, darah saya diperiksa. Lagi-lagi, mereka mengatakan saya tertular AIDS. Saya tetap menolak dituduh mengidap AIDS. Di hari ketujuh belas, darah saya diperiksa sekali lagi. Akhirnya, mereka menemukan virus malaria di dalamnya dan mereka mencabut kesimpulan sebelumnya.
Saya sungguh lega.
Lima bulan sesudah perdamaian, tepatnya di bulan Januari 2006, saya menyunting seorang gadis bernama Debit Juniar Ama. Saya telah mengenalnya hampir tujuh tahun silam saat ia masih duduk di kelas tiga sekolah menengah pertama dan saya di kelas tiga SMA.
Kami kini telah dikaruniai seorang putra, yang saya namai Teguh Agam Di Pidieya. Nama ini mempunyai makna tersendiri. Teguh, artinya istiqamah dan berpendirian. Nama ini mencerminkan sikap saya yang bertahan di pegunungan selama waktu yang saya sebutkan: 15.840 jam. Agam, dalam bahasa Aceh, berarti anak laki-laki. Namun, bisa juga diartikan sebagai Angkatan Gerakan Aceh Merdeka. Di Pidieya menisbahkan tempat kelahirannya.
Di masa damai ini saya berharap kehidupan rakyat Aceh lebih baik dan damai yang sejati terwujud. Meski optimistis dengan proses damai ini, tetapi kekhawatiran terbetik juga di hati. Pasalnya, sampai hari ini tak ada kejelasan tentang pengadilan Hak Asasi Manusia untuk kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di Aceh. Komisi Kebenaran belum terbentuk. Bahkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR yang semula menjadi harapan rakyat Aceh untuk menuntut keadilan telah dibekukan dengan keluarnya undang undang nomor 27 tahun 2004 tentang KKR. Tampaknya pemerintah Indonesia akan mengubur kasus ini atau membuat pengadilan basa-basi, seperti yang berlaku pada kasus penembakan mahasiswa Trisakti, kasus penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996, kasus Tanjung Priok, dan kasus penculikan aktivis prodemokrasi.
Perdamaian sejati di Aceh mustahil terwujud tanpa keadilan.
Suadi Sulaiman adalah kontributor sindikasi Pantau di Aceh. Ia mantan gerilyawan Gerakan Acheh Merdeka.
Catatan Libur Lebaran
Sabtu, 6 Oktober 2007
Sapariah dan aku mengantar Norman ke rumah ibu kandungnya, Retno Wardani, di Bintaro. Tepatnya, rumah neneknya Norman, Th. Koesmiharti, dimana Retno menumpang. Selama perjalanan, kami menghitung pola pembagian waktu liburan Lebaran Norman. Norman akan libur dari Rabu 10 Oktober dan masuk sekolah Senin, 22 Oktober.
Menurut keputusan pengadilan, pada masa liburan, Norman tinggal separuh-separuh antara Retno dan aku. Kami mengusulkan dia tinggal pada paruh pertama (10-16 Oktober) dengan aku. Paruh kedua (16-22 Oktober), jatah ibunya. Sorenya, Retno menelepon dan menetapkan Norman tinggal lebih dulu dengannya dan paruh kedua dengan aku. Aku oke saja.
Minggu, 7 Oktober 2007
Sapariah dan aku memasukkan mobil ke bengkel Alexander di Bintaro. Mobil ini pintu belakangnya ditabrak Metro Mini. Pihak bengkel minta aku mengambilnya hari Kamis. Asuransi Sinar Mas menutup biaya perbaikan.
Senin-Selasa, 8-9 Oktober 2007
Norman masuk sekolah seperti biasa. Dua hari ini dia diantar Retno sekolah. Ini pertama kalinya Retno mengantar Norman sekolah sesudah mereka pindah ke Bintaro Agustus lalu. Aku terpaksa minta tolong Retno berhubung mobil masuk bengkel.
Rabu, 10 Oktober 2007
Aku antar Sapariah ke airport. Dia hendak mudik Lebaran ke Pontianak. Aku tak ikut ke Pontianak. Kami memerlukan banyak uang sejak Norman dipindah ke Bintaro. Setiap bulan, kami harus keluar uang Rp 5 juta hanya untuk transportasi Norman. Penghasilan kami berdua tak cukup. Jadinya, kami memutuskan hanya Sapariah yang mudik Lebaran. Aku tetap tinggal di Jakarta. Masih banyak pekerjaan, dari menulis untuk jurnal South East Asia Research hingga menyempurnakan draft buku, yang harus aku selesaikan.
Kamis, 11 Oktober 2007
Aku mengambil mobil yang diperbaiki dari bengkel Alexander di Bintaro. Hasilnya mulus. "Pak Juwono" dari bengkel Alexander bilang dia ingin semua lancar sebelum dia dan anak buahnya pulang kampung. Lalu menjemput Norman di Bintaro. Mulanya dia kuatir tak diizinkan pergi dengan aku. Namun ibunya mengizinkan. Norman senang sekali. Dia meloncat-loncat. Kami pergi ke Pondok Indah Mall bersama. "Quality time," kata Norman, ceria. Berhari-hari ini Norman lewat telepon mengatakan dia bosan di Bintaro.
Kami makan siang bersama di Hoka Hoka Bento. Lalu membeli sepatu sandal Geox. Kami mengira lagi rabat 50 persen. Ketika sudah memilih, ternyata kami pilih yang tanpa rabat. Wah harganya cukup mahal untuk saku aku. Tapi Norman suka sepatu ini. Kami juga pergi membeli buku A Pratical Guide to Monsters terbitan Mirrorstone di toko buku Gramedia. Norman sudah mengincar buku ini sejak minggu lalu namun Retno menolak membelikan untuk Norman, kecuali aku transfer uang lebih dulu. Kami juga minum coklat dan makan pastries di Daily Bread. Pokoknya, kami ingin memakai waktu bersama ini semaksimal mungkin.
Jumat, 12 Oktober 2007
Pagi ini, aku jemput Mama dari stasiun Gambir. Mama datang dari Yogyakarta, memanfaatkan liburan Lebaran. Adikku, Heylen, serta anaknya, Cho Yong Gie, datang menemui Mama di tempatku di Senayan. Dua perempuan ini sibuk cerita sana sini di tempatku.
Siangnya, Norman tiba-tiba datang tersedu-sedu ke apartemen. Dia bilang Retno menuduhnya "ember" --suka cerita "semua rahasia" kepada aku. Retno juga menuduhnya lebih mencintai aku daripada dirinya.
Awalnya, Retno memberitahu Norman kalau Laksito Rukmi, kakak kandung Retno, akan datang bersama keluarganya dari Baturaja (antara Lampung dan Palembang di Pulau Sumatra) keesokan hari. Artinya, kalau Norman ingin bermain dengan dua anak Rukmi, Taufik Hidayat dan Ayu Paramita, maka Norman tak bisa menghabiskan waktu paruh kedua dengan aku di Senayan. Dia artinya akan menghabiskan liburan bersama Retno.
Rukmi bersama suaminya, Indra Rujadi, hendak nyekar ke Salatiga, Ambarawa dan Surakarta. Norman bilang Retno mempersilahkan dia seterusnya tinggal bersama aku, tanpa perlu mengunjunginya lagi. Aku kira ini melukai anak. Norman memang ingin tinggal dengan aku, namun anak mana yang tak sedih diusir oleh ibunya? Dia menangis tanpa bisa bicara.
Aku beri dia segelas air dan tissue. Aku hibur dia. Aku peluk dia. Aku ingatkan betapa senangnya bermain dengan Taufik dan Paramita? Aku serahkan kepadanya buku karangan J.K. Rowling Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Aku minta dia membacanya. Secara bergurau, aku bilang, ini punishment untuk Norman. Ini buku tebal, tanpa gambar, yang aku beli untuk Norman sejak akhir 2000 di Cambridge. Norman punya waktu membaca sekarang. Maka aku bilang sudah waktunya membaca buku tanpa gambar. Dia membawa pulang buku itu.
Dia bilang besok Sabtu ini minta aku menjemputnya. Dia ingin Sabtu pagi main dengan aku hingga sepupunya tiba dari Sumatra malam hari. Ketika sudah tenang, aku antar Norman ke lobby apartemen, menemui Retno. Mereka kembali ke Bintaro.
Sorenya, Rebeka, adikku yang lain, juga datang ke apartemen, menemui Mama. Tiga perempuan, sibuk diskusi dan gossip. Kami mengantar Heylen pulang ke rumahnya di bilangan Kebayoran Baru, seraya menengok toko buah Total, yang terbakar tadi malam. Mama membeli satu kardus susu kaleng untuk kedua cucunya, Yong Gie dan Norman. Juga buah-buahan. Semua dijual obral berhubung toko terbakar, barang harus dijual segera.
Sabtu, 13 Oktober 2007
Norman menelepon pagi-pagi sekali. Dia bilang Taufik dan Paramita sudah datang dari Baturaja. Dia minta aku tak datang menjemputnya di Bintaro. Dia ingin main dengan Taufik dan Paramita. Dia tak jadi pergi makan siang dengan aku. Mereka pun berangkat ke Salatiga dan lain-lain Sabtu sore.
Minggu, 14 Oktober 2007
Kesulitan menelepon Norman sejak Sabtu malam. Mereka naik dua mobil. Satu mobilnya Retno, satunya mobil Indra, kakak ipar Retno. Pagi ini bisa bicara via telepon. Norman bilang dia tak tahu kapan kembali ke Jakarta.
Senin, 15 Oktober 2007
Norman memberitahu aku dia lupa membawa inhaler untuk asmanya. Aku kuatir sekali. Aku pesan jangan capek-capek. Seorang penderita asma harus membawa inhaler bila bepergian. Cukup banyak kasus dimana pasien meninggal karena di tengah jalan susah mendapatkan obat hisap guna melegakan pernafasan ini.
Selasa, 16 Oktober 2007
Aku menjemput Sapariah dan Mamak di airport Cengkareng. Mamak berlibur di Jakarta. Aku prihati melihat badannya kurus sekali. Norman menelepon dan memberitahu bahwa dia sudah menamatkan buku Harry Potter. Wah, dia bangga sekali. Dia bisa membaca buku tebal tanpa bosan.
Aku memutuskan menerima tawaran meliput soal krisis air di Bandung. Aku pikir aku butuh uang. Air kebetulan juga kesukaan aku. Norman juga tak ada di Jakarta.
Rabu, 17 Oktober 2007
Sapariah, Mama, Mamak, Yong Gie dan aku naik mobil ke Bandung. Mama ingin bermain ke rumah kakaknya. Dia sekaligus membawa Yong Gie. Aku lewat jalan tol, Jakarta, Cikampek hingga Padalarang dan Bandung. Cepat sekali. Kami menginap di Hotel Grand Pasundan, bintang tiga, di Jalan Peta.
Pukul 17:28, Norman kirim SMS, Pa miss u, call me by hp. norman." Dia kirim SMS via telepon Kristin, adiknya Retno. Ketika menelepon Norman, dia bilang lagi dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Dia bilang ingin segera ketemu aku. Aku bilang aku sudah ada di Bandung. Dia kesal pada ibunya yang berangkat dan pergi tanpa perencanaan.
Kamis, 18 Oktober 2007
Norman sudah kembali ke Jakarta. Aku masih di Bandung meliput air. Dia minta aku meneleponnya. Dia kecewa ketika tahu aku tak bisa pulang ke Jakarta hari ini. Aku masih harus menyelesaikan wawancara dan mengambil gambar.
Jumat, 19 Oktober 2007
Aku berangkat dari Bandung pagi hari. Norman datang ke apartemen siang hari. Taufik, Paramita serta Kristin, adiknya Retno, datang ke apartemen untuk berenang. Norman tak sabar menunggu membaca Harry Potter and the Chamber of Secrets. Dia merangkulnya dengan erat. Kami mengobrol ibarat dua kawan lama yang baru bersua kembali.
Friday, October 19, 2007
Sebuah Bahasa, Sebuah Komunitas
Oleh LINDA CHRISTANTY
PERTAMA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.
KEDOEA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.
KETIGA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.
SAYA menjadi akrab dengan Sumpah Pemuda, karena upacara-upacara bendera yang dilaksanakan tiap hari Senin di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sumpah Pemuda ketika itu dibacakan sebagai bagian dari prosesi upacara. Bagaimana perasaan saya mendengar dan mengucapkannya? Terus-terang, saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak punya pararelisme pengalaman dengan peristiwa itu, bukan sekadar saya tak hadir pada momen kelahirannya.
Dalam buku sejarah Indonesia disebutkan bahwa Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ia merupakan hasil rumusan Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia atau disebut juga Kongres Pemuda II yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Peserta kongres itu terdiri dari wakil berbagai organisasi pemuda, antara lain Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Sumatranen Bond, dan Jong Batak. Mereka sepakat mengucapkan sumpah bersama dan sekaligus membuktikan bahwa negara Indonesia ini dicetuskan oleh anak-anak muda, bukan kaum tua.
Sebelum itu, pada rapat tanggal 27 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengemukakan gagasan briliannya tentang makna persatuan dan pemuda. Menurut Yamin, ada lima hal penting untuk memperkokoh persatuan, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Yamin muda penuh semangat, cerdas, kritis dan independen, meski setelah itu sejarah juga yang mencatat bagaimana dia putar haluan dan terlibat dalam pusaran kekuasaan; menjadi politikus Volksraad, lalu menjabat menteri kebudayaan.
Entah dengan alasan apa, suatu hari terjadi perubahan pada teks Sumpah Pemuda dan setelah itu masih terjadi lagi dan terjadi lagi. Yang paling saya ingat adalah ketika sila ketiga yang berbunyi “menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia” menjadi “berbahasa satu, Bahasa Indonesia”. Apakah itu buah dari kebijakan pemerintah Orde Baru atau kreativitas guru di sekolah? Saya tidak tahu. Ketika itu saya tak merasa keberatan. Cara berpikir saya masih sangat sederhana. Kalau tanah air dan bangsa itu satu, artinya bahasa pun sama, pikir saya.
Namun, bertahun-tahun kemudian, saya berpikir ada yang keliru pada kalimat “berbahasa satu”. Bukankah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan empat ratus suku bangsa yang mencerminkan empat ratus lebih pula bahasa? Teks yang asli lebih masuk akal. Artinya, bahasa daerah bisa berbeda, tetapi bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia.
Saya pun menjadi lebih berhati-hati terhadap kalimat “berbangsa yang satu” (kemudian diubah jadi “berbangsa satu”).
Ternyata bangsa Indonesia adalah komunitas khayal atau yang terbayang. Ternyata komunitas ini terbentuk oleh kesepakatan. Dalam bukunya, Imagined Community, Ben Anderson mengurai hal tersebut.
Pemerintah Suharto kemudian melindas tiap perbedaan dan keberagaman dengan mengatasnamakannya, mengatasnamakan bangsa itu.
Gagasan persatuan dimanipulasi secara politik oleh Orde Baru. Dan di tangan pemerintahan yang militeristik, ia menjelma sensor.
Pada suatu hari, di tahun 1994, di tengah aksi buruh dan mahasiswa, saya mendengar seseorang mengucapkan “Sumpah Rakyat”. Bunyinya seperti ini:
Satu, Kami putra-putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.
Dua, Kami putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa yang gandrung pada keadilan.
Tiga, Kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa kebenaran.
Saat itulah saya baru bisa menjiwai sumpah para pemuda di tahun 1928, saat rasa kebersamaan dibutuhkan untuk melawan kesewenang-wenangan dan penindasan. Kini saya punya pengalaman yang sama dengan mereka di masa tersebut.
Sumpah Pemuda yang disepakati Yamin dan teman-temannya pada 1928 itu masih tetap relevan dengan situasi Indonesia hari ini.
Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau tidak ada Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setiap daerah menggunakan bahasanya sendiri-sendiri dan bangsa yang satu tak bisa berkomunikasi dengan bangsa yang lain. Semua urusan sederhana menjelma rumit akibat kendala bahasa. Hal sepele bisa jadi sengketa, yang juga mengancam persatuan yang diimpikan Yamin dan para utusan organisasi pemuda waktu itu.
Dulu Bahasa Melayu yang menjadi lingua franca, terutama dalam perdagangan. Ia tidak hanya digunakan di Malaysia atau Semenanjung, melainkan digunakan juga di Jawa, Borneo, dan Sumatra sejak abad ketujuh masehi. Orang Arab, India, dan Cina juga berbicara dalam bahasa ini. Penjajahan Potugis, Belanda, dan Inggris memperkaya kosa kata Bahasa Melayu. Selanjutnya, Bahasa Inggrislah yang menyumbang begitu banyak kata serapan ke Bahasa Melayu. Namun, Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa ini, ternyata mengalami perkembangan yang semakin jauh dari akarnya.
Seorang teman Malaysia saya menyatakan bahwa Bahasa Indonesia jauh lebih indah dibanding Bahasa Melayu di Malaysia. Mendengar orang berbicara dalam Bahasa Indonesia, seperti mendengar tiap kata dalam puisi, merdu, katanya. Entah benar, entah tidak.
Bahasa Indonesia pula yang kini menyokong terbentuknya komunitas terbayang lain di mana-mana. Cerita dan berita yang saya terima dari Borneo, Celebes, Jawa, Aceh, Palembang, Ternate-Maluku Utara, bahkan Amsterdam dan Hongkong ditulis dalam Bahasa Indonesia, lalu disebar dan dibaca penutur serta pengguna bahasa yang sama, mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan Timor Leste. Bahasa ini juga yang membuat perbedaan waktu, tempat, adat-istiadat, kesusastraan, situasi politik dan ekonomi, dan gaya hidup bisa diketahui dan dipelajari orang banyak. Bahasa menjadi pengikat satu sama lain, melintasi batas-batas geografis. Media, suratkabar atau majalah atau televisi atau radio, adalah juga komunitas terbayang yang jangkauan jaraknya bahkan mencapai ribuan mil.
Di Melbourne, Australia, yang tengah mengakhiri musim dinginnya waktu itu, saya terkesima mendengar orang bicara Bahasa Indonesia di jalanan, kafe, trem, toko swalayan, atau telepon umum. Tiap dua belas meter, kamu akan bertemu Bahasa Indonesia. Di mana kita mendengar bahasa itu dituturkan seseorang, apa yang sayup menjadi begitu jelas, begitu dekat. ***
Linda Christanty adalah sastrawan cum wartawan, kini memimpin kantor berita Pantau di Aceh. Tulisan ini sebelumnya dimuat di majalah Eve.
Sunday, October 14, 2007
✒
Selamat merayakan Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali fitri di hari raya yang suci ini.
“Do not be too eager to deal out death and judgement, even the very wise cannot see all ends. All we have to decide is what to do with the time that is given to us.”
-- Gandalf, the shaman,
in J.R.R. Tolkien's series The Lord of the Ring
in J.R.R. Tolkien's series The Lord of the Ring

Tempio di Romolo, atau Kuil Romulus, berada di daerah Roman Forum. Pada zaman Roma Kuno, ini adalah daerah pertokoan, kegiatan seni dan agama, semua campur jadi satu. Romulus menjadi rajah pertama kota Roma pada 21 April 753 SM. Kuil ini dibangun guna menghormati Romulus.
Polemik Sejarah, Pers dan Indonesia
Kapan "pers Indonesia" lahir? Apa 1744 dengan Bataviasche Nouvelles? Apa 1864 dengan Bintang Timoer di Padang? Soerat Chabar Betawie pada 1858? Medan Prijaji pada 1907? Atau sesuai proklamasi Agustus 1945? Atau kedaulatan Desember 1949?
Suharto Helped Myanmar into Asean
In 1997, President Suharto visited Rangoon, promoting Burma's entry into Asean and developing his family's business. Suharto's legacy is still firmly upheld in Jakarta. Visitation report
Kursus Jurnalisme Sastrawi XIV
Idenya dari Washington DC, Janet Steele usul mengapa tak bikin kursus narrative reporting? Mulanya, dua kali saja. Kini ia bergulir terus, dari tahun ke tahun, tak terasa sudah angkatan ke-14.
Indonesian Military and Prostitution Racket
Global Integrity Report ranked countries worldwide on their integrity. It is a comprehensive outlook. Indonesia performs weakly. I wrote a note on the Indonesian military involvement in legal and illegal businesses.
Perjalanan Campania dan Roma
Setiap jengkal tanah di Napoli, Pompeii, Nocera, Salerno dan Roma, rasanya berisi sejarah peradaban Romawi dan Yunani. Apa makna realitas ini terhadap kesadaran manusia Barat?
Ford Foundation Menerima Draft Buku
Buku Debunking sudah selesai draftnya, diserahkan kepada Ford Foundation, namun masih butuh waktu hingga setahun sebelum terbit.
Perkembangan Pengaduan soal Norman
Retno Wardani menolak undangan Komisi Perlindungan Anak. Dia berpendapat keputusan pengadilan final. Norman tetap tinggal di Bintaro walau jarak ke sekolah sangat jauh.
A Jakarta court sentenced several Papuans for the killing of three Freeport teachers in August 2002. Why many irregularities took place in the military investigation and the trial? What did Antonius Wamang say? How many weapons did he have? How many bullets were found in the crime site?
Apresiasi Jurnalis Jakarta 2007
Siapa wartawan yang mendapat penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen? Dari media cetak? radio? televisi? Bagaimana rata-rata mutu peserta lomba ini?
Kursus Narasi Angkatan III
Yayasan Pantau membuka kursus penulisan panjang, untuk kelas November hingga Maret, buat mereka yang ingin belajar bertutur. Ada materi baru soal Pham Xuan An dari Saigon.
Protes Melawan Pembakaran Buku
Indonesia membakar ratusan ribu buku-buku pelajaran sekolah. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, maupun Hindia Belanda, dimana buku sekolah disita dan dibakar.
Indonesia: A Lobbying Bonanza
Taufik Kiemas, when his wife Megawati Sukarnoputri was still president, collected political money to hire a Washington firm to lobby for Indonesian weapons. This story is a part of a project called Collateral Damage: Human Rights and US Military Aid
 Dari Sabang Sampai Merauke
Dari Sabang Sampai MeraukeSejak Juli 2003, saya berkelana dari Sabang ke Merauke, guna wawancara dan riset buku. Intinya, saya pergi ke tujuh pulau besar, dari Sumatra hingga Papua, plus puluhan pulau kecil macam Miangas, Salibabu, Ternate dan Ndana. Inilah catatan kecil perjalanan tersebut.
Hoakiao dari Jember
Ong Tjie Liang, satu travel writer kelahiran Jember, malang melintang di Asia Tenggara. Dia ada di kamp gerilya Aceh namun juga muncul di Rangoon, bertemu Nobel laureate Aung San Suu Kyi maupun Jose Ramos-Horta.
State Intelligence Agency hired Washington firm
Indonesia's intelligence body used Abdurrahman Wahid’s charitable foundation to hire a Washington lobbying firm to press the U.S. Congress for a full resumption of military assistance to Indonesia. Press Release and Malay version
From the Thames to the Ciliwung
Giant water conglomerates, RWE Thames Water and Suez, took over Jakarta's water company in February 1998. It turns out to be the dirty business of selling clean water.
Dark Alliance Rules High Seas
For decades Southeast Asian waters have been a hunting ground for murderous pirates who are growing increasingly daring and dangerous. What is Batam's role? Who are the pirates?
Media dan Jurnalisme
Saya suka menulis soal media dan jurnalisme. Pernah juga belajar dengan asuhan Bill Kovach dari Universitas Harvard. Ini makin sering sesudah diminta menyunting majalah Pantau.
Bagaimana Cara Belajar Menulis Bahasa Inggris
Bahasa punya punya empat komponen: kosakata, tata bahasa, bunyi dan makna. Belajar bahasa bukan sekedar teknik menterjemahkan kata dan makna. Ini juga terkait soal alih pikiran.
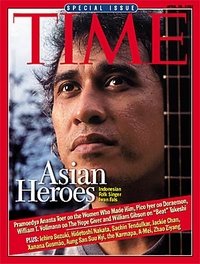 Dewa dari Leuwinanggung
Dewa dari LeuwinanggungSaya meliput Iwan Fals sejak 1990 ketika dia meluncurkan album Swami. Waktu itu Iwan gelisah dengan rezim Soeharto. Dia membaca selebaran gelap dan buku terlarang. Dia belajar dari W.S. Rendra dan Arief Budiman. Karir Iwan naik terus. Iwan Fals jadi salah satu penyanyi terbesar yang pernah lahir di Pulau Jawa. Lalu anak sulungnya meninggal dunia. Dia terpukul. Bagaimana Iwan Fals bangkit dari kerusuhan jiwa dan menjadi saksi?
Polemik Sejarah Pers Indonesia
Kapan hari jadi pers Indonesia? Sebagian orang mempertanyakan kriteria "pers Indonesia," atau kalau pun mau aman, lebih tepat disebut "pers di Indonesia." Ini bisa dimulai oleh surat kabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit 1744-1746, di kota Batavia, Pulau Jawa. Kemungkinan besar Bataviasche Nouvelles adalah suratkabar pertama yang terbit di Pulau Jawa zaman Hindia Belanda. Pulau Jawa hari ini adalah bagian dari Indonesia.
Namun banyak yang tak sependapat. Bataviasche Nouvelles kan berbahasa Belanda? Mengapa tak memulai dari surat kabar yang berbahasa Melayu? Tidakkah bahasa ini yang kelak dipakai sebagai bahasa nasionalisme Indonesia? Pada 1850-an sudah ada surat kabar berbahasa Melayu terbit di Jawa, Sumatra dan pulau lain. Pemiliknya, termasuk wartawan Tionghoa Peranakan.
Beberapa orang lagi, terutama novelis Pramoedya Ananta Toer, berpendapat "pers Indonesia" dimulai oleh Medan Prijaji, terbitan Bandung pada Januari 1907. Pramoedya menulis buku Sang Pemula guna mengedepankan peranan Tirto Adhi Soerjo, penerbit Medan Prijaji. Pramoedya juga melandaskan Tetralogi Pulau Buru, secara fiktif, pada tokoh Tirto. Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yoedhoyono mengangkat Tirto sebagai "pahlawan nasional."
Ada juga yang berpendapat "pers Indonesia" mulai sejak Republik Indonesia ada. Artinya, "pers Indonesia" ini ya termasuk semua yang terbit, atau sudah terbit, pada Agustus 1945, di seluruh wilayah Indonesia. Namun wilayah "Indonesia" pada 1945 de facto hanya Jawa dan Sumatra. Belanda praktis menguasai pulau-pulau lain. Bahkan sesudah perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia malah menciut cuma Jogyakarta dan beberapa tempat lain di Pulau Jawa? Artinya, secara legal "Indonesia" baru diakui dunia internasional sesudah penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949?
Saya mengumpulkan beberapa naskah terkait dengan isu ini. Isinya, banyak kritik terhadap keputusan Presiden Yudhoyono tersebut. Proyek ini diusung oleh Indexpress pimpinan Taufik Rahzen. Saya juga mempertanyakan cara mencari-cari hari jadi "pers Indonesia"?
Hari Jadi Pers Nasional Meremehkan Peran Surat Kabar Lain
Suryadi, peneliti Universiteit Leiden, berpendapat pemilihan Tirto Adhi Soerjo terkesan melebih-lebihkan peranan Tirto. Jasa Tirto tak lebih besar dari Dja Endar Moeda, misalnya, yang aktif di Sumatera, 1894-1910, atau Abdul Rivai lewat Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam, 1903-1907.
Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu
Nasrul Azwar dari Minang berpendapat sejarah surat kabar Sumatra lebih tua dari Medan Prijaji. Sejak 7 Desember 1864, orang Minang untuk pertama kalinya membaca surat kabar berbahasa Melayu ketika edisi perdana Bintang Timoer diluncurkan.
Pers, Sejarah dan Rasialisme
Saya menulis soal istilah "pribumi" dan "non-pribumi" dalam melihat sejarah surat kabar di Jawa, Minahasa dan Minang. Tirto Adhi Soerjo keberatan ketika Boedi Oetomo mencalonkan Ernest Douwes Dekker sebagai editor suratkabar mereka. Alasannya, Boedi Oetomo hanya untuk orang Jawa, Sunda, Madura.
Friday, October 12, 2007
Pers, Sejarah dan Rasialisme
Oleh Andreas Harsono
KALAU Anda memperhatikan harian Jurnal Nasional di Jakarta, Anda takkan sulit melihat sebuah logo “Seabad Pers Nasional” di halaman depan. Di dalamnya, Anda akan menemukan logo serupa dan sebuah kolom. Ia setiap hari menyajikan satu sosok organisasi media. Proyek ini diasuh oleh Taufik Rahzen, seorang penasehat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, redaktur senior Jurnal Nasional, sekaligus pemimpin Indexpress, organisasi yang menaungi kolom ini.
Menurut Rahzen, tahun 2007 adalah seabad pers nasional. Tarikh ini dihitung sejak Medan Prijaji terbit pertama kali pada Januari 1907. Medan Prijaji adalah “tapal dan sekaligus penanda pemula dan utama bagaimana semangat menyebarkan rasa mardika disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi.” Dua kegiatan itu dilakukan oleh hoofdredacteur-nya Tirto Adhi Surjo. Jurnal Nasional menghadirkan 365 koran, yang mereka anggap ikut membangun nasionalisme Indonesia. Hitungannya, antara 1 Januari hingga 31 Desember 2007, ada 365 hari. Jadinya, 365 media dalam 365 kolom.
Saya berpendapat ada 150 tahun sejarah sebelum Medan Prijaji, yang harus diperhitungkan oleh siapa pun yang hendak bikin ulasan sejarah media di Hindia Belanda. Kalau mau mencari data siapa yang terbit lebih awal, Abdurrachman Surjomihardjo dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia menyebut suratkabar Bataviasche Nouvelles, yang terbit 1744-1746, atau sekitar 150 tahun sebelum Medan Prijaji, sebagai penerbitan pertama di Batavia.
Mengapa patokan Taufik Rahzen bukan 1744? Mungkinkah karena Bataviasche Nouvelles diterbitkan dalam bahasa Belanda? Kalau patokannya bahasa Melayu, Claudine Salmon dalam Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, menyebut suratkabar-suratkabar berbahasa Melayu, antara lain milik orang Tionghoa, misalnya Soerat Chabar Betawie (1858), terbit sekitar 50 tahun sebelum Medan Prijaji? Salmon membuktikan bahwa suratkabar-suratkabar Tionghoa Melayu ini berperan dalam penyebaran bahasa Melayu di seluruh Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda.
Atau mengapa bukan bahasa Jawa, misalnya, Bromartani (1865) yang terbit di Solo? Di luar Pulau Jawa, juga ada Tjahaja Sijang di Minahasa (1868) atau Bintang Timoer di Padang (1864). Kalau bicara soal pengaruh dan perjuangan melawan ketidakadilan, saya juga ingin mengingatkan kita pada Multatuli, yang mengarang buku Max Havelaar (1859). Mengapa semua diabaikan? Multatulis alias Eduard Douwes Dekker menggunakan penanya buat menggugat kolonialisme Belanda di Jawa.
Saya mendapat jawaban Indexpress dari Agung Dwi Hartanto ketika hendak mewawancarai saya. Rencananya, Indexpress hendak memasukkan Pantau, organisasi di mana saya bekerja, ke dalam barisan 365 media tersebut. Dalam suratnya kepada saya, Agung menulis, “Medan Prijaji adalah pers yang sejak pertama terbit diawaki pribumi. Tirto Adhi Soerjo juga yang mendirikan NV Medan Prijaji.”
Tjahaja Sijang, menurut Agung, diabaikan karena “… sebelum diawaki pribumi menjadi milik zending Belanda. Demikian juga dengan Soerat Chabar Betawi. Koran ini bukan milik pribumi.”
Saya agak kaget mendapat jawaban tersebut. Benarkah Indexpress memakai ukuran yang rasialis tersebut? Tidakkah mereka sadar rasialisme hanya akan melahirkan diskriminasi. Rasialisme juga akan melahirkan rasialisme? Saya bikin riset lagi. Saya menemukan Taufik Rahzen juga memakai kriteria “pribumi” dalam sebuah kolom Jurnal Nasional, dengan judul, “Pers adalah Senjata.”
Rahzen menulis, “Salah satu penanda penting dari menyingsingnya fajar nasionalisme adalah tumbuh-kembangnya pers pribumi ….” Rahzen menganggap “… indikator dimulainya kebangkitan nasional, tumbuhnya pers-pers pribumi, yang diterbitkan oleh pribumi, yang mengangkat berita dan persoalan riil yang pribumi ….”
Saya rasa ada racial tone dalam proyek Indexpress. Saya menganggap tak ada masalah dengan memilih Tirto Adhi Soerjo. Dia termasuk penerbit yang berani melawan ketidakadilan pada zaman Hindia Belanda. Pengarang Pramoedya Ananta Toer menulis soal Tirto Adhi Soerjo dalam buku Sang Pemula maupun Tempoe Doeloe.
Tapi Tirto pun memakai pendekatan rasial ketika menyerang E.F.E. Douwes Dekker, wartawan Bataviaasch Nieuwblad dan cucu Multatuli, yang belakangan mendirikan Indische Partij. Pada 1908, organisasi Boedi Oetomo hendak menerbitkan suratkabar dan mencalonkan E.F.E. Douwes Dekker sebagai editornya. Alasannya, Boedi Oetomo membatasi keanggotaannya hanya untuk orang “Jawa, Sunda dan Madura.” Douwes Dekker orang Eurasian alias Indo. Paul W. van der Veur, penulis biografi Douwes Dekker, The Lion and the Gadfly, mencatat serangan ini, secara fiktif, diteruskan Pramoedya dalam tetralogi Pulau Buru.
Penelitian Indexpress ini bermasalah, ketika mengabaikan para penulis lain dengan dasar Tirto dan Medan Prijaji adalah "pribumi." Pada 1907, negara Indonesia belum ada. Slogan Medan Prijaji pun masih memakai nama Hindia Belanda. Pramoedya menulis soal Tirto dengan kedekatan emosional. Tirto dan Pramoedya sama-sama kelahiran Blora.
Benedict Anderson dalam pengantar buku Indonesia Dalem Bara dan Api menulis bahwa pada awal abad XX, "Koran mulai tumbuh di ampir setiap kota jang berarti, mirip tjendawan dimusim hudjan. Timbullah djagoan2 masa media pertama di Hindia Belanda, termasuk diantaranya Mas Tirto, F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, Marah Sutan, G. Franscis, Soewardi Soerjadingrat, ter Haar, Mas Marco, Kwee Kek Beng, dan J.H. end F.D.J Pangemanann pakai dua 'n'."
"Timbul djuga djago2 pers Belanda, termasuk Zengraaff, jang dengan keras membela pengusaha swasta sampai ditakutin pemerintah kolonial sendiri, dan D.W. Beretty, seorang Indo keturunan Italia-Djawa Jogja, jang selain mendirikan persbiro pertama di Hindia Belanda --Aneta, Pakdenja Antara-- djuga menerbitkan madjalah radikal-kanan, berdjudul De Zweep (Tjamboek)." Anderson menulis adanya keragaman dunia media yang mulai tumbuh subur pada awal abad XX.
Kriteria “pribumi” itu bakal menimbulkan dampak yang tidak tepat. Bila kriteria "pribumi" ini dipakai untuk menerangkan suratkabar dan "kebangsaan" Indonesia, sebelum dan sesudah Medan Prijaji, bisa kacau-balau penelitian ini.
Sekadar contoh. Kalau Anda perhatikan thesis Daniel Dhakidae di Universitas Cornell, Anda akan membaca setidaknya tiga suratkabar sekarang --Kompas, Sinar Harapan dan Tempo-- yang punya cikal bakal "non pribumi." Harian Djawa Pos di Surabaya didirikan The Chung Sen, seorang penerbit Tionghoa, pada 1949 sebelum dibeli PT Grafiti Pers, yang memiliki saham Tempo, pada 1982. Bagaimana Indexpress bikin barisan 365 media itu tanpa memasukkan Kompas, Sinar Harapan, Jawa Pos dan Tempo?
Tjahaja Sijang di Minahasa, sebelum diawaki orang Minahasa, antara lain, A.A. Maramis, memang milik Nederlandsch Zendeling Genootschap, sebuah lembaga zending Belanda. Namun NZG adalah lembaga yang melahirkan Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan kebaikan dan jasa sangat besar di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya kira mengabaikan Tjahaja Sijang, dengan alasan ia milik "Belanda," akan membuat wartawan di Minahasa bertanya-tanya. Maramis tak punya rekaman antagonistik terhadap orang-orang Belanda.
Contoh lain. Harian Flores Pos (1999) terbitan Ende, yang dipilih Indexpress, juga milik Societas Verbi Divini (SVD), sebuah organisasi Katolik dengan pusat di Roma. SVD adalah organisasi multinasional. Bisa jungkir balik Indexpress kalau mau dicari SVD itu pribumi mana? Cikal bakal Flores Pos adalah majalah Bintang Timoer (1928) dan dwimingguan Bentara (1948), yang juga punya komponen "non pribumi."
Lantas apa kriteria sih pribumi? Kalau kategori "pribumi" juga dipakai di Papua, bagaimana Taufik Rahzen memandang Eri Sutrisno? Dia orang Jawa, sekarang pemimpin redaksi mingguan Suara Perempuan Papua, suratkabar paling bermutu di Jayapura. Namun di Papua, Eri Sutrisno dianggap bukan “penduduk asli.” Bagaimana menyusun logika "pribumi" Indexpress terhadap orang Jawa, yang berjasa untuk jurnalisme di Papua, namun secara umum dianggap bukan pribumi Papua?
Kalau kriteria pribumi diletakkan di Timor Leste, negara yang baru meraih kedaulatannya, saya kira Rahzen juga akan jungkir balik. Irawan Saptono, orang Jawa warga Indonesia, lama bekerja di harian Suara Timor Timur pada zaman pendudukan Indonesia. Kini Timor Lorosae sudah merdeka. Irawan juga kembali ke Jakarta. Apakah Irawan tak berjasa dalam pengembangan jurnalisme di Dili?
Pada 1995, saya ada di Dili dan melihat sendiri kerja keras dan keberanian Irawan membela orang-orang Timor dari tentara Indonesia. Irawan belakangan terpaksa lari dari Dili karena ketidaksukaan militer Indonesia. Irawan bekerja untuk melayani masyarakat Dili dengan informasi tanpa ribut soal "kebangsaan" Timor Leste atau Indonesia. Tidakkah ini tindakan terpuji? Bagaimana perasaan Irawan Saptono bila namanya dihilangkan begitu saja dari sejarah Timor Lorosae? Tidakkah tujuan utama jurnalisme adalah memberitakan kebenaran? Tidakkah bisa dipertanyakan metode Rahzen ketika jurnalisme disejajarkannya dengan advokasi? Tidakkah ini menyamakan suratkabar partai dengan harian independen?
Saya kira logika ini bisa menjelaskan bahwa orang-orang macam F. Wiggers, H. Kommer, Tio Ie Soei, G. Franscis, ter Haar, Kwee Kek Beng, J.H. Pangemanann, F.D.J Pangemanann dan sebagainya juga, bekerja keras menyampaikan kebenaran kepada pembaca mereka, sama dengan Tirto. Mereka tak bisa diabaikan dengan mengambil Medan Prijaji sebagai tonggak media yang menyuarakan "kebangsaan" Indonesia.
Ide soal nation-state juga bukan pribumi di Hindia Belanda, atau yang sekarang disebut Indonesia. Ide ini mulanya berkembang di Perancis dan Amerika Serikat lebih dari 200 tahun lalu. Ide ini menyebar tanpa mengenal batas kerajaan, etnik, agama maupun lautan. Ia juga mendarat di Hindia Belanda dengan segala macam tafsir dan variasi. Kalau tiba-tiba ide soal nasionalisme ini “dipribumikan” ala Indexpress, saya kuatir, mereka kini sedang memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Proyek ini kurang mendidik warga Indonesia untuk belajar dari masa lalu dengan sebaik-baiknya.
Pramoedya Ananta Toer menulis dalam Sang Pemula bahwa guru Tirto dalam jurnalisme adalah Karel Wijbrands, warga Prancis, kelahiran Amsterdam dan meninggal di Batavia pada 1929. Tirto patuh dan hormat pada Wijbrands. Tirto juga bekerja bersama dengan F.D.J. Pangemanann, orang Minahasa. Tirto juga bekerja dengan F. Wiggers. Tirto menghormati tradisi Wiggers, yang menghargai dan menghormati golongan Tionghoa. Namun Tirto juga termasuk anak emas Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz, perwira militer yang memimpin Prang Athjeh dan membunuh cukup banyak warga Aceh pada awal abad XX. Saya tak bisa membayangkan bagaimana seorang politikus macam Tirto, yang dekat dengan van Heutsz, yang tangannya berlumuran darah orang Aceh, bisa diterima oleh wartawan di Aceh sebagai “pahlawan”?
Saya berpendapat Indexpress salah memakai kriteria “pribumi.” Kelak 100 tahun lagi, kalau kriteria ini konsisten dipakai terhadap Pantau, maka Pantau akan diabaikan karena ada “non pribumi” dalam komunitas ini. Ada juga wartawan-wartawan "non-pribumi" –Fikri Jufri, Toriq Hadad, Yosep Adi Prasetyo, Lenah Susianty dan lainnya-- ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen maupun Institut Studi Arus Informasi masing-masing pada 1994 dan 1995. Dua organisasi ini mendirikan media bawah tanah pada zaman Presiden Soeharto, guna menyiasati sensor dan bredel, sehingga beberapa anggotanya dipenjara. Tidakkah logika macam Indexpress ini juga kelak akan menghapus AJI dan ISAI berhubung ada “non-pribumi”?
Andreas Harsono adalah ketua Yayasan Pantau, bergerak di bidang pelatihan wartawan dan sindikasi feature, dari tiga kantor Jakarta, Banda Aceh dan Ende. Dia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen dan Institut Studi Arus Informasi.
Subscribe to:
Posts (Atom)
