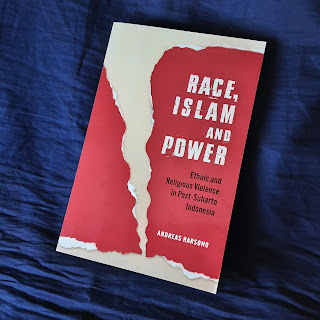JAKARTA (31 Januari 2022) – Eko Rusdianto, seorang wartawan dari Maros, Pulau Sulawesi, yang sering meliput diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan dan minoritas seksual, hak masyarakat adat dan petani, maupun kerusakan lingkungan hidup, meraih Penghargaan Oktovianus Pogau untuk keberanian dalam jurnalisme dari Yayasan Pantau.
Pada 6 Oktober 2021, laporan Rusdianto soal dugaan pemerkosaan tiga anak yang dilakukan ayahnya, seorang birokrat di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terbit di Jakarta. Ia merupakan penugasan dari Project Multatuli.
Liputannya berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan.” Liputan tersebut menggemparkan dunia maya. Ia membuat tanda pagar #PercumaLaporPolisi viral di Indonesia. Website projectmultatuli.org mendapat serangan DDOS (Distributed Denial of Service) sehingga down, dan dicap berita bohong oleh Polres Luwu Timur. Puluhan media lain menerbitkan laporan tersebut di website masing-masing.
Awalnya, Eko Rusdianto ingin menuliskan kisah “Ibu Lydia” namun merasa belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan soal liputan trauma, terutama terhadap korban kekerasan seksual. “Ibu Lydia” melaporkan mantan suaminya kepada polisi dengan tuduhan kekerasan seksual terhadap ketiga anak perempuan mereka.
Pada 2019, kasus ini dihentikan di Luwu Timur. Rusdianto mulai membaca berkasnya bersama kenalannya di Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Dia juga bikin liputan soal seorang transgender perempuan, Pada 2020, Rusdianto belajar pada beberapa aktivis hak perempuan serta membaca soal liputan trauma. Dia mulai sering menulis soal diskriminasi dan kekerasan terhadap individu transpuan di Sulawesi termasuk Ho Chiang Seng (biasa dipanggil Hae), yang sudah 36 tahun meninggalkan Makassar, mengembara di Pulau Jawa.
Pada 2021, Project Multatuli hubungi Rusdianto agar menulis tentang kasus-kasus hukum yang mandek. Rusdianto mengusulkan tentang kasus kekerasan seksual di Luwu Timur. Dia ingin menyambung suara “Ibu Lydia” yang disebut "gangguan jiwa" di Luwu Timur gegara memperkarakan mantan suaminya.
“Keputusan buat membongkar kasus yang sudah ditutup polisi adalah sebuah keberanian. Ini sesuatu yang lazim dilakukan wartawan dalam masyarakat yang dukung demokrasi,” kata Pontoh. “Project Multatuli membuat kebijakan yang baik dengan menyediakan dana buat bongkar kasus-kasus dingin.”
Eko Rusdianto kelahiran September 1984, di kampung Kombong, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dia kuliah jurnalistik di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Fajar. Cinta pertamanya, dalam dunia keilmuan, adalah arkeologi. Rusdianto beberapa kali menulis soal gua prasejarah atau bahasa yang terancam punah. Eko Rusdianto belajar jurnalisme dan penulisan di Yayasan Pantau di Jakarta pada 2008 serta pernah mendapatkan beberapa penugasan jurnalistik.
Rusdianto mengirim naskah ke berbagai penerbitan Jakarta, termasuk Mongabay, Vice, Historia maupun New Naratif (Singapura), Al Jazeera (Qatar), dan South China Morning Post (Hong Kong). Tahun lalu, Rusdianto juga menulis kesulitan bekerja sebagai wartawan lepas buat Remotivi. Judulnya, “Koresponden dan Penulis Lepas, Sama-sama Cekaknya.”
Di Mongabay, Rusdianto banyak meliputan soal perampasan tanah serta pengrusakan lingkungan hidup, termasuk penggusuran tanah warga Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, buat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sae. Tempatnya terpencil dan tak bisa dilalui mobil. Seko, terletak sekitar 120 kilometer dari Sabbang, Luwu Utara, atau 600 kilometer dari Makassar. Rusdianto naik ojeg sepeda motor, dua sampai tiga hari, dengan ongkos sekitar Rp 1 juta.
Dia juga menerbitkan antologi termasuk Titik Krisis di Sulawesi; Narasi Jurnalistik Atas Kehancuran Ruang dan Sumber Daya Alam (2020), Tragedi Di Halaman Belakang: Kisah Orang-orang Biasa dalam Sejarah Kekerasan Sulawesi (2020) serta Meneropong Manusia Sulawesi (2022).
Dalam pemeriksaan tahun 2018 terhadap kasus di Luwu Timur, Indonesian Judicial Research Society menyimpulkan berbagai prosedur yang cacat dari Dinas Sosial maupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Luwu Timur dalam menerima keluhan "Ibu Lydia." Mereka mengusulkan kedua kantor pemerintah tersebut, maupun kepolisian, membuka kembali kasus dengan prosedur pendampingan baru terhadap ketiga korban kekerasan seksual maupun ibunya.
Pontoh mengatakan, “Kami hormat pada pergulatan serta kesulitan wartawan lepas macam Rusdianto dalam melawan kebekuan birokrasi kepolisian. Liputannya seyogyanya dipakai sebagai masukan buat memperbaiki kinerja Polres Luwu Timur, maupun kepolisian secara nasional, dalam mengungkap kekerasan seksual.”
Tentang Penghargaan Pogau
Nama Oktovianus Pogau, diambil dari seorang wartawan Papua, kelahiran Sugapa pada 1992. Pogau meninggal usia 23 tahun pada 31 Januari 2016 di Jayapura, sesudah pulang dari perjalanan di Amerika Serikat sebulan sebelumnya. Tubercolosis kambuh karena perjalanan di musim dingin.
Pada Oktober 2011, Pogau pernah melaporkan kekerasan terhadap ratusan orang ketika berlangsung Kongres Papua III di Jayapura. Tiga orang meninggal dan lima dipenjara dengan vonis makar. Pogau juga sering menulis pembatasan wartawan internasional meliput di Papua Barat sejak 1965. Dia juga memprotes pembatasan pada wartawan etnik Papua maupun digunakannya pekerjaan wartawan buat kegiatan mata-mata.
Penghargaan ini diberikan buat mengenang keberanian Pogau. Ia diberikan sejak 2017 dengan Febriana Firdaus sebagai penerima pertama. Ia rutin diberikan setiap tahun: Citra Dyah Prastuti dari KBR Jakarta (2018); Citra Maudy dan Thovan Sugandi dari Balairung Press, Yogyakarta (2019), Yael Sinaga dan Widiya Hastuti dari Medan (2020); serta Phil Jacobson dari Mongabay, Chicago (2021).
Juri dari penghargaan ini lima orang: Alexander Mering (Gerakan Jurnalisme Kampung di Kalimantan Barat, Pontianak), Coen Husain Pontoh (Indo Progress, New York), Made Ali (Jikalahari, Pekanbaru), Yuliana Lantipo (Jubi, Jayapura) dan Andreas Harsono (Human Rights Watch, Jakarta).